Enam Belas ☁️ Perwakilan Kelas
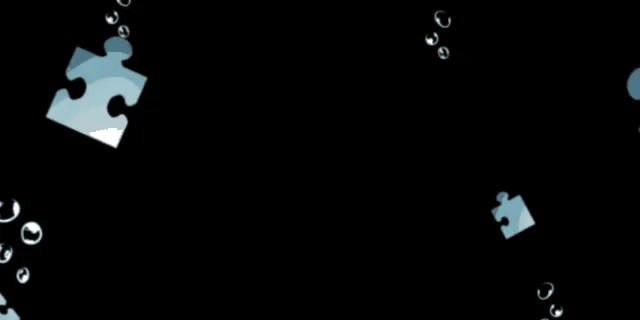
Sepanjang hari menuju Senin, Candala tak pernah absen dari kamarku. Entah hanya untuk mainan gitar sebentar, mengajakku jalan-jalan, membawa sketchbook-nya, atau numpang makan siang karena bapak dan ibu RT sedang bekerja. Kami kembali masuk sekolah hari ini, dan tak satu pun dari anak kelas akselarasi yang mau membicarakan tentang hukuman skorsing kami bertiga.
Hari pertama di kelas sebelas, aku langsung salah masuk ruangan. Aku duduk seperti orang bodoh di kelas yang biasanya, sendirian, sampai jam masuk. Ketika curiga sebab tak ada guru atau teman-temanku yang masuk, aku menelpon Bila.
"Kelas kita di lantai atas, Nad! Astaga, kita udah kelas sebelas!" pekiknya dari seberang sana, disusul deru napasnya membentur mikrofon. Kuduga dia berderap turun dan menjemputku.
Gadis itu menepuk dahi kala mendapatiku masih duduk di bangku dengan tenang, lantas menggeretku ke atas dengan cepat. "Untung Bu Nga belum masuk. Kau ini nggak baca grup kelas atau bagaimana?!"
Aku menggeleng. Sudah dua hari aku tak mengindahkan grup itu. Kupikir tidak ada pemberitahuan khusus, jadi tak ada gunanya membuka grup dengan notifikasi lima ribu lebih. Sepanjang lorong ke kelas baru, Bila memberitahuku banyak hal, tentang jadwal baru, wali kelas yang tidak berubah, dan beberapa peraturan tambahan khusus anak aksel yang tak lagi boleh mendapat nilai delapan puluh sembilan ke bawah.
Kelas kami lebih besar, dengan bentuk yang lebih normal—tidak seperti tadi yang memanjang ke belakang. Sebab belum ditentukan posisi duduk, Bila mengklaimku sebagai teman semeja dan menjulurkan lidahnya untuk mengejek Candala dan Abidine yang pernah menjadi partner semejaku.
Pelajaran dimulai, dan tampaknya aku masih belum beradaptasi dengan beberapa hal baru. Contohnya saat ini diriku bertanya-tanya ke mana Pak Faruq di jam pelajarannya. Padahal tadi Bila sudah bilang kalau beliau hanya mengajar kelas sepuluh. Untuk kelas sebelas, Bu Ngajirin yang mengambil alih mapel fisika.
Perlu sekiranya dua kali istirahat untukku menyadari kalau kelas kami dekat dengan kelas Rachel. Waktu itu aku tidak sengaja bertemu gadis ganjen tersebut di kantin bersama Bila. Pas mau masuk ke kelas ... lho kok kami mengikuti punggungnya? Untung Rachel tidak sadar atau menoleh.
Seharian ini, sungguh pikiranku melayang ke mana-mana. Aku tidak fokus dengan pelajaran, teman-teman kelas, atau guru yang memanggilku. Jamal berkali-kali datang ke mejaku untuk meminta maaf empat mata sebab karenanya aku kena imbas skors.
"Gapapa," kataku. Lagipula, selama skors itu aku banyak melakukan hal selain belajar. Menggambar misalnya, dan aku juga mendapatkan uang yang tak kusangka tidak sedikit untuk sekadar jajan.
Hari Minggu kemarin Candala meninggalkanku di atap sekolah sendirian. Dia menghilang entah ke mana sampai magrib dan kembali lagi dengan cengiran. "Maap, kelupaan bawa anak cewek." Kalau anak itu pulang, barulah aku main ke rumah Abidine untuk menyalin catatan dari sekolah.
Nah, begitulah caraku menghabiskan masa liburan lima hari yang panjang. Otakku mungkin terbawa suasana santai, makanya aku tidak bisa fokus.
Menjadi murid akselarasi bukan berarti kau bisa berleha-leha karena masa depan sudah terjamin setahun lebih cepat ketimbang murid reguler. Apa aku tidak pernah bercerita tentang bagaimana panasnya organ dalam tempurung kepala kalau ada ulangan dadakan? Nah, kuberi tahu kau sekarang tentang serba-serbi kelas kami, biar waktu dewasa dan membuka jurnal ini, aku ingat pernah separah itu membanting jidat.
Ada yang namanya SNMPTN dan SBMPTN. Hanya beda satu huruf kalau diperhatikan, N dan B. Nilai dan Bersama. Kami siswa akselerasi dididik untuk masuk perguruan tinggi lewat jalur N alias Nilai. Nah, kalau kau mau coba juga boleh, tetapi siap-siap bernasib seperti kami—gila. Syarat paling aman yang harus kuraih agar bisa lolos SNMPTN adalah nilai yang tiap semesternya terus naik, tidak ada yang turun barang satu angka pun.
Sejak pertama masuk akselerasi, guru-guru menetapkan KKM khusus untuk kami. Kalau murid reguler hanya 76 saja, kami mendapat 85. Terus naik tiap semesternya. Kalau turun atau sampai mendapat nilai -B satu saja, habislah kami dikembalikan ke kelas reguler. Maka dari itu kadang aku tak punya waktu untuk menceritakan beberapa detail seperti apakah aku gagal dalam ujian lintas minat sosiologi atau dapat nilai tertinggi di geografi.
Semisal aku tidak lolos SNMPTN, maka bulan selanjutnya akan ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Artinya, aku harus belajar mati-matian lagi untuk bersaing dengan kakak kelas 12 seluruh Indonesia agar bisa masuk kampus impian.
Dengan posisiku saat ini, jelas aku memilih fokus ke SNMPTN—biar belajarnya dicicil dan tidak mati di tempat saat mengulang mata pelajaran setelah lulus SMA. Itulah sekilas tentang kelas akselerasi. Masih mau mencoba? Kusarankan tidak kalau kalian masih mau menikmati masa muda dengan jalan yang lebih bahagia. Bukan berarti aku mengatai diriku dan teman sekelas tidak pernah bahagia. Hanya saja ... bahagia kami mungkin sedikit berbeda.
"Misi!"
Dan pandangan kami semua menoleh ke ambang pintu. Tepatnya tiga kakak kelas 12—yang bajunya sudah tahu kekecilan tetap saja tambah diketatkan—beserta map merah di tangannya.
Jam pulang sekolah, kami ditahan di kelas sendiri untuk mendengarkan beberapa baris kata dari anak-anak OSIS yang tidak rela lepas masa jabatan. Taufan sebagai ketua kelas sekaligus teman yang paling waras di sini menangani ceramah tiga senior itu dan dengan senang hati merangkum poin-poin penting.
"Jadi gini," katanya setelah kami berkumpul di meja paling depan. "Minggu depan, 'kan, ada DBL. Nah, anak OSIS minta tiap kelas punya perwakilan ke Jakarta lima orang buat berangkat dan bantuin ekskul militan. Biar keliatan kalo basket sekolah kita, tuh, rame."
Kami hanya manggut-manggut sampai Bila bertanya, "Bayar ke sana pake uang kas?" Sebagai bendahara, mungkin alarm keamanannya berbunyi saat berpikir bahwa akan ada transportasi dan beberapa biaya lainnya seperti makan kalau ke Jakarta.
"Nggak, pake uang masing-masing," jawab Taufan, lantas Bila menghela napas lega. "Biaya bis tujuh puluh ribu pulang pergi, tapi beli tiket stadion sendiri lima belas ribu. Dan itu belum sama makan, jadi kelola uangmu sendiri kalo mau ikut."
"Wajib banget, ya?" desah Abi, telungkup di mejanya yang bersebelahan dengan meja Taufan. "Males banget keluar duit lagi, nggak dapet apa-apa pula. Aku cuma mau liat Giam doang, sih."
Taufan mengangguk. Sudah tradisi dari tahun ke tahun kalau SMA kami paling meriah soal DBL, lalu menyeret pulang piala gubernur.
"Lho, kelas kita sekarang tujuh orang, kalo aku ikut tanding, otomatis ada satu orang yang nggak bisa ikut?" celetuk Giam, nyempil di sebelahku bau keringatnya nyaris mengalahkan durian.
"Jamal!" seru suara bariton dari belakang kami. Pak Faruq datang menggendong tas hitamnya yang dari jauh pun semua orang tahu itu beratnya seperti anak sembilan bulan. "Jamal nggak boleh ikut."
Kok gitu?
Bukan hanya aku yang bertanya-tanya, tetapi seisi kelas, kecuali yang namanya disebut itu.
"Mereka takut aku bikin onar," jawab anaknya enteng. Jamal merenggangkan tubuhnya, kemudian menatap kami satu persatu. "Maaf, bung. Salahku. Tapi Bila janji mau live Instagram biar aku bisa liat Giam kayang di lapangan."
Pak Faruq mendekati kerumunan kami. "Maaf, Mal. Bapak udah bilang ke Bu Endang. Tapi katanya emang lebih baik nggak ikut." Beliau meletakkan tasnya, disusul suara berdebum yang keras. "Bapak maunya kalian ikut semua, nanti bapak yang bayarin bisnya."
"Nggak papa, Pak. Aman aja." Jamal tersenyum. Awalnya kupikir dia mendadak punya jiwa patuh, tetapi kemudian. "Tapi Bapak traktir saya makan bakso di sebelah."
Ditempelengnya pelipis Jamal pelan. Pak Faruq ikutan tersenyum tipis—ciri khasnya yang tak pernah hilang. "Enak aja! Ayok!" Pria itu langsung merangkul Jamal yang meninggalkan tasnya. Namun, mata wali kelas kami itu mendapati anak didiknya tengah menatap satu arah padanya. "Apa liat-liat? Kalian nggak ikut, lah. Enak aja. Miskin saya nanti."
Sepertinya memang sesuai rencana Dala. Kami akan pergi ke Jakarta dan melihat Giam tanding basket, kemudian kabur saat jam bebas untuk mencari ayahnya Candala. Aku pasti ikut—kami sekelas akan ikut—dan Abidine mau tidak mau juga akan mengekor.
Pembicaraan tentang DBL masih hangat di telinga kami sampai seminggu ke depan. Bila terus menggangguku tentang apa saja yang akan kubawa, rencanaku begitu tiba di sana, dan beberapa pertanyaan tidak mutu misalnya apa perlu bawa sabun untuk berak di pom bensin. Sampai Pak Faruq membagi tempat duduk kelas perorangan di Rabu siang yang terik. Sejak hari itu sampai tiba jadwal kami berangkat ke Jakarta, Bila merajuk pada wali kelas kami.
Sabtu pagi, lapangan parkir di depan SMA sudah penuh para perwakilan kelas untuk DBL. Kami berlima yang ikut ke Jakarta menepi di sudut gerbang, sementara Giam sudah berangkat lebih dulu Kamis lalu.
Seluruh mata melirik rombongan kami dengan tatapan sinis. Satu-dua ada yang sengaja menyenggol bahuku dan Bila berkali-kali saat melintas. Itu menyebalkan, kalau kalian tahu, tetapi kelas kami sudah terbiasa dengannya. Semua orang tahu kelas akselerasi mendapat perhatian lebih dari kepala sekolah, dan kelas mana, sih, yang tidak iri dengan itu?
Abidine berkali-kali mengingatkanku untuk tak mengindahkan mereka, dan aku menurut. Tak ada gunanya juga meladeni anak-anak seperti itu, buang-buang waktu saja. Banyak desas-desus jelek yang beredar tentang perempuan akselarasi. Mulai dari pelet kepala sekolah, sampai guna-guna biar nilainya bagus terus. Yang laki-laki malah dipuja-puja sama anak-anak lain. Si jago basket, si juara olimpiade, si fotografer handal, si badboy cerdas, si tukang rusuh humoris. Padahal aslinya mereka tidak ganteng-ganteng amat. Jerawatan iya, bau keringat iya, kelainan jiwa juga iya. Oh seandainya cewek-cewek itu melihat kelakuan mereka di kelas.
"Ayok, Nad!" ajak Bila menarik tanganku begitu bis tiba dan memasuki halaman sekolah.
Semuanya riuh, berebut masuk bis satu persatu. Kelas kami kedapatan satu bis dengan angkatan kelas sebelas lainnya. Di tengah huru-hara, tabiat jelekku kumat; benci kerumunan dan keramaian.
Kakiku lemas seketika, lantas lantak di tanah sejenak kala mendapati pandanganku gelap berkunang-kunang seperti orang anemia. Yang bisa kupandangi dari sini hanyalah langkah kaki orang-orang melewati bahkan tak jarang menyenggolku.
Ini jelek. Ini jelek! Padahal hal beginian sudah jarang terjadi semenjak awal tahun.
"Nad?" Suaranya familiar di telingaku, kalian pun bisa menebak itu milik siapa. "Mau digendong?" tawarnya menjulurkan tangan. Kala mendapat gelengan, anak itu mengambil alih ransel kecil di pundakku. "Berat, bah. Kau bawa apa aja?" Dia ikut berjongkok di sebelahku, kami jadi orang bodoh di tengah ingar-bingar.
Begitu tiga perempat manusia itu sudah lesap dari pandangan, barulah aku bangkit. Duh, rasa mau muntah! "Barang cewek," jawabku, kemudian menerima uluran tangannya lagi untuk berdiri dan menyusul yang lain.
Aroma pengap dari bis semakin membuatku ingin muntahkan sarapan pagi dari lambung. Namun, kami tetap berjalan masuk mencari kursi kosong. Di sudut paling belakang, kursi yang berderet panjang, Pak Faruq melambaikan tangannya.
Aku tidak kuat kalau disuruh duduk di sana, yang guncangannya paling besar karena dekat ban belakang. "Dala," lirihku, mungkin dia tak mendengarnya sebab kebisingan sekitar. Tangannya tetap menggandengku agar tak terpisah sampai di kursi.
Kelas akselarasi sempurna menguasai kursi belakang. Enam kursi di sana, Bila di tengah, diapit Pak Faruq dan Taufan, Abidine di sudut dekat pintu, aku dan Dala di surut yang lainnya.
"Mabok?" tanya Dala usai kami mengambil posisi.
"Tidur aja, Nadir." Pak Faruq di sebelahnya pun menepuk pundakku. "Masih lama banget jalannya, kalo udah sampe bapak bangunin nanti."
Mana bisa aku tidur dalam kondisi begini. Bila juga sudah berkali-kali menawariku obat anti-mabok, dan berkali-kali pula selama perjalanan aku menelannya. Sampai rasa kantuk menghampiri, dan entah bagaimana caranya aku terlelap.
Segalanya menguap begitu saja. Rasa mual, sakit kepala, sampai rasa berdenyut di mataku. Ini perjalanan jauh paling menyebalkan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top