Hide & Shriek
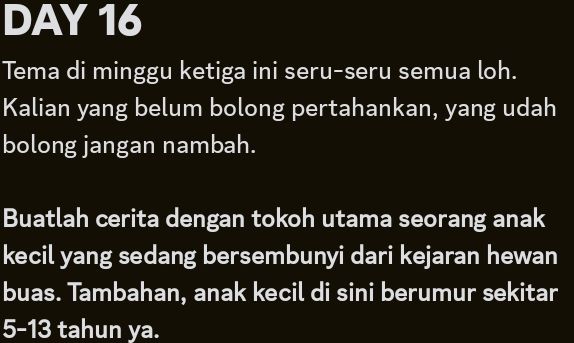
***
Empat anak kecil. Empat nyawa. Satu tikus raksasa.
Di sebuah kandang ayam, Burhan dan tiga anak SD yang lain tengah bersembunyi. Ia tak pernah menyangka petak umpet malam ini berubah menjadi petaka.
Kisahnya bermula sehabis salat Isya di langgar. Anak-anak seusianya selalu berkumpul di pelataran rumah almarhum kakek Burhan untuk bermain. Halamannya luas, dipagari teh-tehan dan dua pohon mangga. Banyak yang bisa mereka mainkan. Namun, seperti buah, tiap permainan ada musimnya. Kebetulan akhir-akhir ini di desa Burhan masih musim petak umpet.
Burhan yang jaga. Itu keapesan pertama. Desanya penuh dengan titik-titik yang gelap gulita. Pepohonan rindang, kandang hewan, tepi saluran irigasi, semua bisa jadi tempat yang ideal untuk bersembunyi. Berpindah-pindah tanpa terdeteksi. Tugas yang merepotkan bagi siapa pun yang harus mencari.
Target pertama berhasil ia tangkap. Nia, adiknya sendiri. Target keduanya adalah Faris, anak yang bersembunyi di bawah lincak pedagang kacang rebus. Beberapa anak berhasil lolos dan menyentuh tiang jaga sebelum Burhan, hingga tinggal satu anak yang belum terlihat. Agung.
Dibantu Nia dan Faris, Burhan memergoki Agung tengah menyantap sesajen. Ini malam Jumat Kliwon. Sudah jadi tradisi desa untuk menyiapkan sesajen berupa buah, rokok, kopi, dan aneka jajanan pasar. Termasuk keluarga Agung.
"Gung, curang kamu. Kan perjanjiannya nggak boleh masuk rumah," ujar Burhan.
"Sorry, Han. Laper nih," balas Agung. "Mau nggak? Ambil aja. Nia, Faris, yuk?"
Ia menawari ketiga temannya bubur merah putih. Namun, Burhan mencegah.
"Ya udah. Berarti abis ini kamu yang jaga! Dasar curang."
Burhan segera menarik Agung sebelum selesai makan. Pukul delapan malam. Kicau burung perkutut menggema seraya keempat anak itu keluar rumah. Suaranya rendah dan sedih.
Di luar sepi. Muda-mudi desa yang biasa bergadang, bapak-bapak yang biasa mengobrol di pos ronda, wujudnya tak terlihat sama sekali. Padahal, malam masih muda. Burhan dan kawan-kawan biasanya baru disuruh pulang pukul sembilan malam.
Makin jauh berjalan, makin ia sadar bahwa tak satu pun orang dewasa ia temukan. Sorak-sorai gembira yang tadi memenuhi pelataran kakeknya, berubah menjadi tangis dan pekik mencekam.
"Wirok! Wirok! Ada tikus wir—ohk!"
Burhan bersembunyi di rumpun bambu, diikuti tiga anak yang lain. Dari sela batang, ia menyaksikan sesosok tikus sebesar macan kumbang tengah menggerogoti tubuh seorang anak. Nia hampir menjerit, untung Burhan sigap membekap.
Tikus itu menoleh ke rumpun bambu, memperlihatkan mulut yang penuh darah dan robekan baju. Agung dan Faris sontak lari terbirit-birit, membuat perhatian makhluk itu tertuju ke arah mereka. Burhan dan Nia berlari ke arah yang berlawanan. Tetap menuju rumah sang kakek.
Suara anak-anak yang lain turut sirna. Tinggal sisa ceceran darah dan kain yang berserakan, seperti bekas prosesi penyembelihan kurban.
Sesosok pria bercaping terlihat di sudut latar, dekat pohon mangga. Kedua tangannya sibuk menggaruk sampah menggunakan garu.
Burhan semringah. Akhirnya ada orang dewasa. Namun, ekspresinya berubah saat ia mendekat.
Pria itu berpaling. Tangan dan wajahnya tinggal rangka. Sampah yang ia kumpulkan adalah tulang dan rambut anak-anak korban tikus raksasa yang Burhan temui.
Burhan dan Nia pun kabur sejauh mungkin, hingga tiba di tepi saluran irigasi. Mereka meniti tepian dengan hati-hati, berharap tak ditemukan siluman tikus dan tengkorak tadi.
"Psst, Han! Sini!"
Suara Agung. Ia dan Faris tengah bersembunyi di kandang ayam.
Demikian asal-usul keempat anak tersebut berkumpul. Namun, perjuangan belum selesai. Maut masih mengintai di luar kandang.
"Kita harus keluar desa," usul Burhan.
"Percuma," bantah Faris. "Tikus itu nunggu di gapura."
"Kalau gitu, lewat sawah aja."
"Dan bikin tikus itu ngejar kita di tempat terbuka? Hiii .... Kamu aja sana!" sahut Agung.
"Bener, Han. Tikus itu, biarpun gede, larinya kayak tikus biasa. Kalau kejar-kejaran di sawah, kita pasti kalah," tambah Faris.
"Terus, kita sembunyi di sini sampai mampus? Siapa yang bakal nolong kita? Orang-orang tua juga nggak tahu pada ke mana," ujar Burhan.
"Oke," kata Faris. "Biar kucek barangkali dia udah pergi dari gapura."
Faris keluar sambil mengendap-endap. Ketiga kawannya turut mengawasi dari sela-sela bambu penyusun kandang. Di antara mereka, Faris adalah pelari tercepat. Burhan cuma bisa percaya sambil berdoa.
Anak itu mengintip gapura dari semak-semak. Dibantu cahaya purnama, Burhan melihat temannya menoleh dan mengacungkan jempol. Artinya aman.
Faris tersenyum. Sesaat kemudian, kepalanya hilang. Tikus itu melesat bagai angin, menyergap dan menggoncang-goncangkan tubuh anak itu hingga koyak tak bergerak.
Nia tak mampu menahan tangis. Air mata menetes, bibirnya mengatup sekuat tenaga agar tak mengeluarkan bunyi.
Burhan memeluk sang adik dengan erat. Ia sendiri ingin berteriak, tetapi kata Ibu, ia harus jadi contoh dan pelindung bagi adiknya.
"Modar aku ... Mamak, Bapak, Agung mau pulang ... hik, hik."
Agung pun sudah mencapai batas.
"Ini pasti gara-gara aku makan sesajen. Hiks."
"Hus, jangan mikir aneh-aneh. Takhayul itu," hardik Burhan. Ia dan adiknya juga pernah makan sesajen pada malam Jumat Kliwon. Namun, tak sampai separah ini.
"Buktinya, ada siluman tikus ngamuk habis aku makan sesajen!" racau Agung. "Mak, Bapak, Gusti Pangeran ...."
Burhan menoleh ke arah saluran irigasi. Selagi makhluk itu menikmati tubuh Faris, ia harap ia bisa menyelinap ke belakang kandang hingga melintasi area persawahan.
"Mau ke mana kalian?" tanya Agung.
"Kabur. Ikutan nggak? Apa cuma mau nangis di sini?" balas Burhan.
"Emoh!"
"Ya udah. Nanti kukabarin kalau ketemu orang-orang dari desa lain."
Burhan dan Nia pun keluar, melompati saluran irigasi, lalu berlari menyusuri pematang demi pematang. Di tengah perjalanan, cericit tikus raksasa kembali terdengar di belakang. Burhan memegangi lengan sang adik sambil terus berlari. Pandangannya fokus ke depan.
Ia tiba di kuburan, tepat di perbatasan desanya dan desa sebelah. Cericit tikus tak terdengar lagi. Ia duduk bersandar di balik pohon beringin, rehat sejenak.
"Nia, kamu nggak—" Burhan menoleh ke samping. Adiknya tinggal sepotong lengan bawah dan telapak tangan yang ia genggam.
"NIAAAA!!!!!"
Burhan menjerit sekencang-kencangnya. Di tengah sawah, si tikus dedemit asyik menyantap tubuh sang adik. Pantas saja dia tak mendengar suara makhluk itu. Pantas saja dia tak mendengar isak tangis Nia.
Tikus itu terusik. Suara Burhan membuatnya kembali agresif dan berlari ke kuburan. Namun, Burhan tak peduli lagi. Tenaganya habis, harapannya sirna, kaki-kakinya tak lagi sanggup menopang beban.
Saat si tikus hendak menerkam, sebatang garu melayang menusuk matanya. Pria tengkorak tiba. Ia naik ke tubuh tikus yang masih tersungkur, mencabut garunya, lalu menghujamkan lagi berkali-kali hingga makhluk itu benar-benar mati.
"Aku terlambat lagi," katanya. "Hanya satu anak yang bisa kuselamatkan kali ini."
Pria tengkorak berbalik ke arah Burhan. Ia memakai setelan safari yang sudah lusuh dan sobek-sobek. Lamat-lamat Burhan melihat tanda pengenalnya. Sutarman. Kakeknya yang sudah lama wafat.
"M-Mbah Kakung?" tanya Burhan.
"Burhan," sahutnya sedih. "Maaf, harusnya kalian tidak di sini."
"K-Kami nakal ya, Mbah? Apa demit itu marah gara-gara kami makan makanan mereka?"
"Tidak, akulah yang salah," balas Sutarman. "Kami sebagai orang tua, sebagai leluhur kalian, terlalu pengecut. Terlalu menaruh hormat pada makhluk-makhluk itu. Akhirnya mereka ngelunjak. Kalian yang tak tahu apa-apa jadi kena."
Burhan terisak-isak.
"Padahal, harusnya mereka yang takut pada kita. Bukan sebaliknya," lanjut kakek Burhan.
Setelah mengumpulkan sisa tubuh Nia dan teman-teman Burhan, beliau mengajak Burhan ke jembatan Kali Siwalan. Katanya, sungai di bawah jembatan itu adalah gerbang antardimensi.
"Terjunlah. Hanya itu cara agar kamu bisa kembali ke orang tuamu," kata Sutarman.
Burhan melihat ke bawah. Permukaan sungai yang berlumpur tampak kemilau diterpa cahaya bulan.
"Nia dan yang lain gimana? Apa mereka bisa selamat?" tanya Burhan.
"Hanya Tuhan yang tahu," balas Sutarman. "Yang jelas, tempat ini adalah hukumanku. Aku bakal terus berupaya menyelamatkan anak-anak yang terdampar di sini, meski selalu gagal."
Burhan tak begitu paham. Namun, ada ketulusan di kata-kata sang kakek. Anak itu meloncat tanpa ragu, menyelam hingga kedalaman yang dingin, gelap, dan tak menentu.
***
"Han? Burhan?"
Suara Ibu.
"Burhan! Pak, Bapak! Burhan bangun, Pak!"
Burhan membuka mata. Bapak dan Ibu berdiri di sisi kasur yang sama. Ia tengah berbaring di ranjang putih, dengan berbagai peralatan medis yang terpasang di tubuhnya.
Setelah kondisinya stabil, mereka berbagi kisah. Ayahnya bilang, ia habis tenggelam dan hanyut di saluran irigasi. Tubuhnya baru ditemukan di dekat jembatan Kali Siwalan.
Burhan pun bercerita. Tentang petak umpet, sesajen, tikus raksasa, hingga pertemuan dengan sang kakek. Ia menyampaikan pesan kakek agar warga desa melakukan pembersihan besar-besaran, berhenti memuja setan, dan kembali ke jalan yang benar.
"Oh ya, Nia gimana? Apa dia juga selamat?" tanya Burhan.
Orang tuanya saling pandang. "Nia? Nia siapa?"
"Adik Burhan, lah! Siapa lagi?"
Ibunya mengernyitkan dahi. "Adik? Sejak kapan kamu punya adik? Kan kamu anak semata wayang."
Jantung Burhan berdegup kencang. Ia ingin pulang. Secepatnya. Pada detik itu juga.
Sesampainya di desa, tak ada anak yang seumuran dengan Burhan. Tak ada yang lebih muda. Ia satu-satunya anak di bawah 12 tahun yang masih tersisa.
***
1326 kata
[A/N] Rasanya bakal makin banyak "penyimpangan" seiring meningkatnya keabsurdan tema dan menurunnya tingkat kewarasanku.
DF Rost, 16 Februari 2024
Image by Gerd Altman from Pixabay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top