Bab 27
Sialan!
Kenapa, sih, air mataku harus keluar di saat-saat seperti ini? Menangis di depan Ian karena terlibat masalah dengannya bukanlah sesuatu yang baik. Aku tidak ingin terlihat lemah di matanya.
Beruntung aku langsung meninggalkannya saat mulai merasakan hujaman air mataku yang akan datang tak lama lagi. Dan benar, begitu keluar dari kamarnya, tangisku meledak. Buru-buru aku memasuki toilet di lantai dua dan menumpahkan air mataku di sana.
Aku menangis sesenggukan, tetapi sebisa mungkin menahan diri agar isak tangisku tak terdengar sampai luar. Aku pun terpaksa harus menutupi mulutku dengan telapak tanganku untuk sedikit meredam suaraku.
Bukan baru sekali aku bertengkar dengan Ian, malah kami bisa dikatakan sering bertengkar. Namun, bila cekcok di antara kami cukup besar dan sudah melibatkan perasaan pribadiku, aku memang kerap menangis setelahnya walau sebisa mungkin menyembunyikan tangisanku dari Ian. Sialnya, aku tadi kelepasan.
Kutarik napas dalam-dalam saat isak tangisku mulai mereda. Kuhapus pelan jejak air mata yang membasahi wajahku. Aku lantas bangkit berdiri, mematut diri di depan cermin kamar mandi yang berbentuk persegi.
Kutatap wajahku di sana dan meringis pelan. Padahal, tangisanku hanya berlangsung selama kurang lebih lima menit, tetapi mataku sudah tampak begitu sembap.
Sekali lagi kutarik napas panjang. Kemudian kunyalakan keran air dan mulai membasuh wajahku, berharap bisa sedikit menyamarkan bekas tangisanku yang tampak jelas.
Kumbil tisu untuk mengeringkan wajahku. Sial! Bengkak di kedua mataku tetap kelihatan jelas. Aku butuh makeup, tetapi tasku berada di halaman belakang. Kalau aku mengambil tasku di sana, mereka akan tetap bisa melihat mataku yang sembap.
Apa aku harus menggunakan strategi mengendap-endap?
Baiklah.
Sepertinya itu tidak terlalu buruk untuk dicoba.
Setelah membuang tisu ke tempat sampah, aku bergegas keluar dari kamar mandi dengan kepala yang sibuk menyusun siasat agar tasku bisa berada di tanganku tanpa terlihat oleh siapa pun.
Aku terlonjak kaget dan nyaris menutup kembali pintu toilet yang baru kubuka ketika menemukan Ian yang sedang berdiri di hadapanku. Napasku sempat terhenti sejenak dengan mata yang berpusat padanya.
Aku masih berusaha mengembalikan kesadaranku dari keterkejutan yang luar biasa, tetapi tiba-tiba saja Ian mengambil tanganku dan menarikku dengan lembut ke dalam pelukannya.
Bukannya mendapatkan kesadaranku, aku malah semakin terombang-ambing dengan reaksi yang campur aduk. Kaget. Bingung. Bimbang. Semuanya bercampur menjadi satu.
“Maaf.”
Suara Ian yang terdengar lemah mampir di telingaku. Dekapannya pun semakin erat. Sementara tubuhku membeku. Masih sibuk mencerna keadaan yang terjadi sangat cepat ini.
“Gue terlalu egois dan nggak pernah bisa ngertiin perasaan lo. Gue selalu nyimpulin tentang lo seenaknya. Gue nggak pernah nyadar udah seberapa banyak rasa sakit yang gue kasih ke elo,” sambung Ian, dengan suara yang begitu lirih dan penuh penyesalan. “Maaf. Maafin gue, Nya.”
Aku mengerjap sebanyak dua kali sembari memaksa akal sehatku agar segera kembali mengisi otakku yang mendadak terasa kosong.
“Gue bener-bener minta maaf.” Kata maaf terus keluar dari mulut Ian, seakan-akan dia bisa mengucap hal yang sama sampai ribuan kali.
Sedikit demi sedikit saraf-saraf di otakku mulai kembali tersambung, dan reaksi pertama yang kuberikan pada Ian adalah menarik diriku dari dalam dekapannya.
Ian tampak tidak rela tatkala aku melepas pelukannya. Matanya terlihat sayu dan penuh pengharapan. Kedua bahunya meluruh lemah. Air mukanya benar-benar menunjukkan penyesalan, sesuai dengan omongannya barusan.
“Kita udah kenal sejak kecil, Yan. Kenapa sikap yang lo tunjukkan ke gue kayak orang yang baru saling kenal selama beberapa bulan?” Emosiku kembali terpancing.
Bibir Ian membentuk satu garis tipis. Dia diam dengan kepalanya yang perlahan menunduk.
“Udah selama itu kita sahabatan, apa lo belum bisa mengenali gue sama sekali? Seenggaknya beberapa sifat gue yang selama ini kelihatan secara kasat mata.” Aku melanjutkan saat menyadari Ian memilih untuk tetap bungkam. “Atau selama ini lo nggak pernah peduli sama gue?”
Kepala Ian terangkat dengan cepat, kembali menatapku. Matanya bergetar cemas dan dia menggeleng dengan cepat.
“Nggak gitu, Nya. Gue peduli sama lo.”
Aku berdecih. “Terus selama ini kenapa lo selalu bikin spekulasi seenaknya tentang gue tanpa berusaha untuk melihat dari sudut pandang gue?”
“Iya. Gue salah soal itu.” Ian terdengar patuh, tak ada bantahan sama sekali.
Aku menghirup napas dalam-dalam bersamaan dengan mata yang kupejamkan sejenak. Berusaha menetralkan emosi yang bergejolak di dalam sana. Sementara kedua tanganku sudah mengepal di sisi tubuhku, meluapkan segala emosi yang datang bertubi-tubi.
“Maafin gue, Nya.”
Kubuka kedua mataku saat mendengar suara Ian dan merasakan sentuhan di satu tanganku. Dia rupanya mengambil tanganku untuk digenggamnya, terlihat berusaha membantuku untuk meredakan amarahku.
Aku membiarkannya. Tidak lagi menarik diriku seperti sebelumnya.
“Gue emang bodoh banget.” Nada suaranya masih dipenuhi dengan penyesalan. Binar di kedua matanya pun seakan-akan sedang memohon ampunan dariku.
Kuhela napas panjang sebelum akhirnya mengangguk, menerima permohonan maaf Ian.
Ketersinggungan akan ucapan-ucapan Ian yang memantik pertengkaran di antara kami memang masih tersisa, tetapi perasaanku kini sudah jauh lebih lega.
Setelah menangis dan mengungkapkan sebagian isi hatiku pada Ian, aku sudah cukup merasa lega. Sedikit puas bisa menumpahkan unek-unekku selama ini.
Secepat kilat ekspresi Ian berubah. Senyum hadir di sudut bibirnya, tampak begitu senang mendapat maaf dariku. Tanpa tedeng aling, dia langsung memelukku.
“Mulai sekarang, gue akan mencoba untuk lebih peka,” ucap Ian, terdengar penuh tekad dalam kalimatnya yang disuarakan dengan tegas.
Aku pun tak bisa menahan senyumku. Kubalas pelukan Ian sambil mengangguk-anggukan kepalaku. Di dalam hati berharap kepekaan Ian nantinya bukan hanya tentang unek-unekku barusan, tetapi lebih dari itu.
Aku ingin dia menyadari perasaanku. Rasa cinta yang selama ini kupendam untuknya.
“Tapi gue nggak akan narik kata-kata gue yang tadi,” ujarku seraya mengurai pelukan kami.
“Yang mana?” Ian memegang kedua tanganku, menahan agar aku tetap berdiri di dekatnya, tidak menjauh seperti sebelumnya.
“Soal kita yang udah nggak perlu saling mengurusi kehidupan satu sama lainnya,” jawabku. “Gimana?”
Ian tak langsung menjawab. Bola matanya sempat bergerak ke atas, seakan sedang memikirkan jawaban atas permintaanku yang satu itu.
“Hmm ... okay.” Pada akhirnya Ian menyetujui gagasanku meski terdengar ragu. Huh! Padahal, omongan itu berasal dari mulutnya, tetapi kenapa malah dia yang ragu?
“Sekarang, boleh nggak gue minta tolong sesuatu?”
“Apa?” Ian menaikkan sebelah alisnya.
“Tolong ambilin tas gue di bawah. Gue butuh makeup gue buat nutupi mata gue yang sembap.”
Karena masalah di antara kami sudah clear dan kami juga sudah berdamai, bodo amatlah bahas soal mataku yang sembap gara-gara menangis.
Ian tertawa kecil.
Tuh! Mulai, deh, aku jadi bahan tertawaannya.
“Maaf ya udah bikin nangis,” kata Ian sembari mengusap lembut kedua mataku yang otomatis memejam. “Tapi mata lo bengkak kayak gini, kecantikan lo tetep nggak berkurang kok, Nya,” tambahnya seraya menarik tangannya dari mataku.
Aku mencebik dengan wajah cemberut. Sementara Ian nyengir lebar.
“Udah sana buruan ambilin tas gue.”
“Siap, Tuan Putri.” Ian membuat sikap hormat padaku, yang tak pelak membuatku tak lagi bisa menahan tawaku.
Dia lantas bergegas turun ke bawah dan memintaku untuk menunggunya di kamarnya saja.
•••
Heyooo! Adakah yang udah baca Ian's Voice Bab 2 & 3 di Karyakarsa? Ssttt diem-diem aja, ya. Jangan spoiler🤭
Buat yang mau baca, silakan mampir ke akun KK aku yaa. Btw, kalo kalian nggak mau baca Ian's Voice juga gak masalah, karena gak berpengaruh sama alur di sini🥰
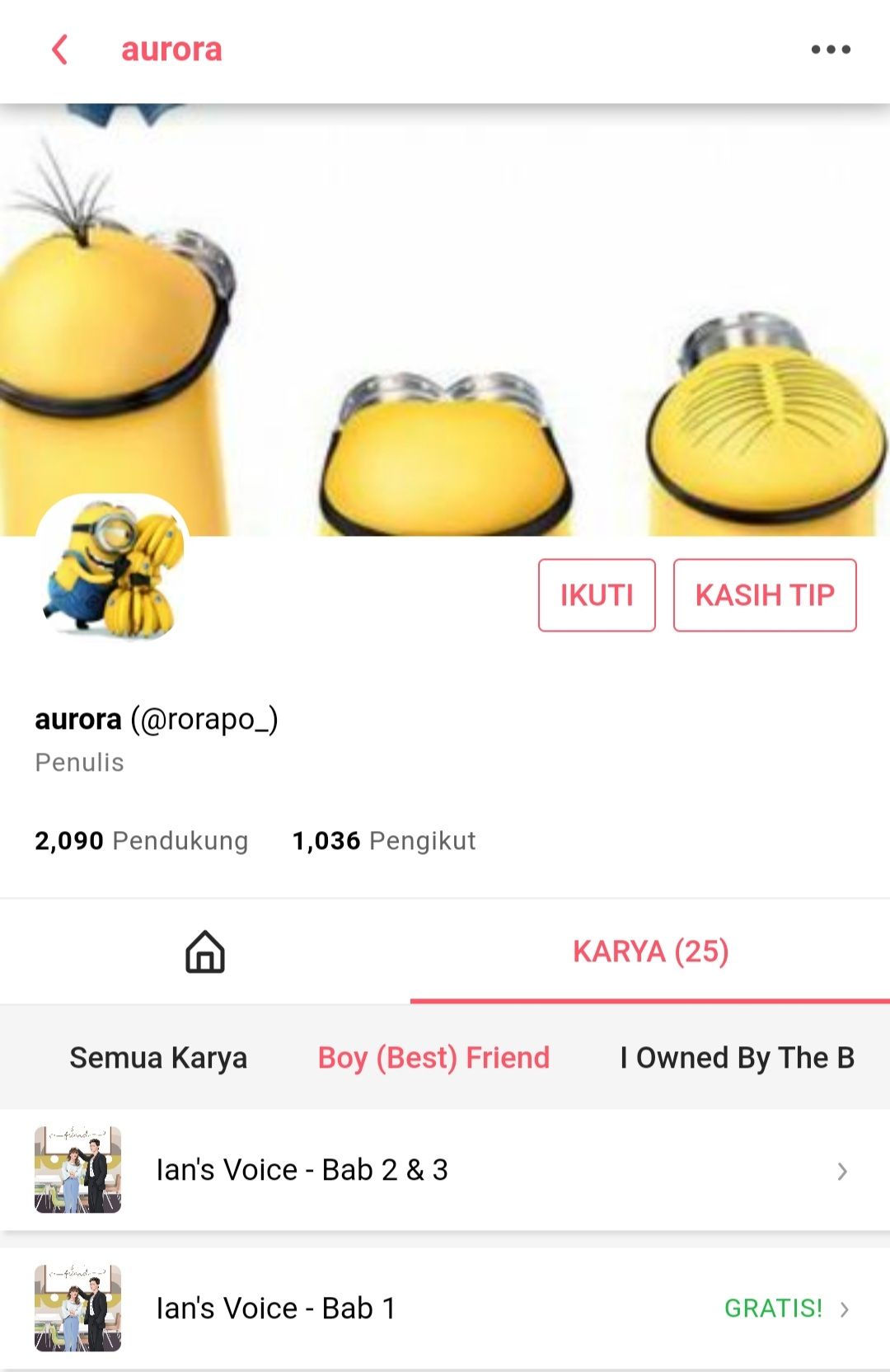
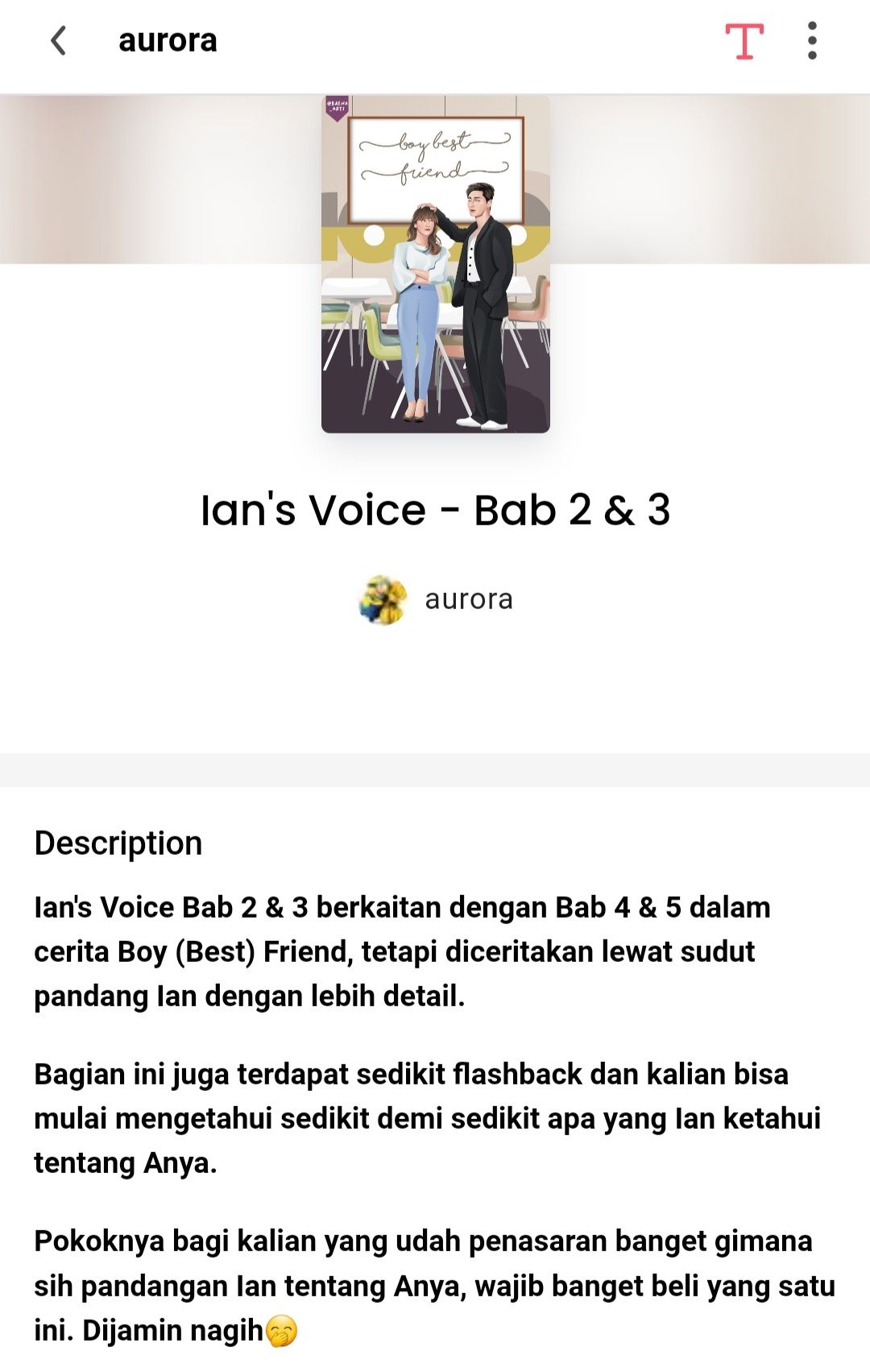
15 November, 2022
Follow aku di
Instagram: rorapo
Dreame/Innovel: rorapo_
Karyakarsa: rorapo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top