V. Pasien Lepas
Sabtu, 20 Januari 2018
—Adira
Sesuai janjinya, Altair menelponku pagi-pagi buta. Hanya demi mengingatkan siang nanti kami memiliki janji sebagai partner dadakan. Siang itu juga, aku mau tak mau datang karena tak enak hati padanya.
Lelaki itu sungguh bersemangat dengan kaos dibalut kemeja lengan pendek dan celana training. Sebelas dua belas dengan pakaianku.
"Aku tak mau lama-lama, langsung aja pilih. Pertama kita selamatkan yang ada di gedung pendamping. Kelebihannya, dokter Flo tidak akan berada di sana hingga tengah hari," jelasnya panjang lebar, "tapi, pasien di sana tidak mudah diajak kompromi. Mereka rata-rata subjek penelitian remaja yang melibatkan kekuatan otak manusia. Jadi mereka bisa kapan saja menjerit memanggil Flo."
Dokter kemarin, kami memutuskan memanggilnya Flo. Entahlah, Altair mungkin memiliki dendam kusumat dengan nama itu. Dia sudah menceritakan semuanya padaku kemarin petang, sebelum kami pulang masing-masing.
Sampai saat ini, Altair hanya mendapatkan informasi seputar gedung pendamping. Apa saja keamanannya, isinya, sampai tiap-tiap kepribadian subjek. Di luar itu, kami masih sama-sama buta.
"Kedua, kita bisa menunda rencana pertama, dan melakukan study tour ke gedung utama. Dengan catatan, nyawa taruhan." Laki-laki itu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Kami belum beranjak dari pagar belakang.
Benakku berpikir sejenak, menimbang-nimbang. Namun, keduanya sama-sama berbahaya. "Nggak ada yang lebih baik?" Saat mendapat gelengannya, aku berdecak pelan. "Yang kedua aja. Aku belum siap sakit mental sama pasien."
"Bagus! Inilah untungnya punya partner. Ayo!" Senyumnya kembali mengembang, belakangan ini dia senang tersenyum. Jauh berbeda kalau di dalam kelas.
Aku cukup mengikutinya, membiarkan Altair mengoceh tentang keberadaan dokter Flo di lantai atas siang-siang begini. Kami masuk melewati pintu depan. Sepasang kaca itu dirantai pegangannya, tetapi tubuh kami mampu menyelinap di sela-selanya dengan mudah.
Bau besi berkarat bercampur alkohol kuat menyusupi indra penciumanku. Hawa-hawa dingin menyeruak saat langkah berjalan lima ubin ke depan. Meja resepsionis ditumpuki berkas-berkas berdebu, lama tak disentuh kurasa.
"Mau ke mana?" tanya Altair mencekal pergelangan tanganku, mencegah pergi seorang diri.
"Study tour. Kamu mau laporan kita diterima kepolisian, 'kan? Kita harus punya bukti, minimal foto." Kurogoh saku celana panjangku, mengeluarkan ponsel dari sana, lantas mendekati meja resepsionis perlahan.
Masih terdengar suara biarpet dari balik dinding tripleks. Namun, aku tak akan menyangkal kalau memang ada orang lain di sini selain dokter Flo. Itu sebabnya kami harus berjaga-jaga
Altair mengekor di belakang, celingukan mengawasi tiap sisi dan sudut, memastikan tidak ada yang datang. "Ra, cepetan. Aku nggak bisa jamin apa emang ada orang lain."
Terlalu gelap di sini, tetapi aku tak bisa menyalakan flash ponsel. Kalau ada orang lain, keberadaan kami akan terungkap. Bahkan yang mampu kulihat hanyalah benda-benda besar, itu pun berwarna gelap kebiruan.
"Foto secukupnya. Kita kudu pergi sekarang, seseorang datang!" bisiknya, lekas mengamit tanganku untuk bersembunyi di balik meja besar yang tadi kuambil gambarnya.
Kami berlutut saling berhadapan dengan dada berdebar. Sementara dari sisi lain meja, cahaya minim mulai memancar tipis-tipis. Memang benar, ada orang lain di sekitar sini. Artinya, dokter Flo tidak sendirian karena jadwalnya sekarang bukan di ruangan ini.
Inilah mengapa Altair mengatakan bahwa opsi kedua lebih berbahaya dan mengancam nyawa. Namun, setidaknya dengan ini kami tahu apa yang ada di dalam.
Keningku mengernyit, menyadari sesuatu. "Kamu belum pernah masuk?" tanyaku tanpa suara, tetapi aku tahu dia tahu maksudku.
Lengkap dengan cengirannya, Altair menggeleng. "Nunggu ada temen."
Aku menepuk jidat pelan-pelan. "Terus gimana caramu tau dokter Flo nggak di sini?" Kepalaku menoleh, menyapu sekitar memperkirakan apa yang terjadi kalau seseorang itu menangkap kami, mencari senjata dari peralatan sekitar.
Ada tripod poster, terbuat dari besi dan aku bisa menggunakannya sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Jaraknya terlalu jauh, dan untuk meraihnya perlu meloncati beberapa tempat duduk besi panjang.
"Dulu aku punya peta tempat ini. Tapi folder di ponsel ilang. Intinya, orang ini bukan dokter Flo." Dia mendongak, menatap cahaya di langit-langit ruangan yang mulai mengecil lantas hilang di balik pintu.
Belum, bukan berarti orang itu juga menghilang di balik sana. Bisa saja dia memang menunggu kami keluar dari sisi lain meja. Namun, tidak ada satu pun dari kami yang mendengar suara bahkan deru napas lainnya.
Altair kembali merosot di sebelahku, merapatkan tubuhnya dengan lutut. Saat dia menoleh, netra kami bertemu. Alih-alih tersipu, tanganku sigap menariknya untuk tiarap di lantai. Detik berikutnya, tiga pinset tweezer terbang menancap pada meja kayu tempat kami bersandar sebelumnya.
Tanpa aba-aba, aku sungguhan berlari melewati bangku-bangku besi demi meraih tripod poster. "Jangan diem aja!" desisku lirih.
Percuma bisik-bisik, seseorang telah mengetahui keberadaan kami di sini. Aku menoleh ke segala arah, bersiap untuk serangan selanjutnya dan menyiapkan jalur terbuka untuk angkat kaki.
Satu lagi, kali ini scalpel melayang melewatiku dari arah poli-poli yang berjajar di bagian gedung yang lebih gelap. Tatkala penglihatanku mulai beradaptasi dengan gelapnya sekitar, cepat kusadari perempuan dewasa mengenakan jubah bedah hijau pasien dengan kepala ditutupi perban kian mendekat menggeret troli meja operasi.
Entah bagaimana, Altair sudah selangkah lebih maju dariku. Lelaki itu mengambil tripod poster lainnya sebagai tameng dan berlari kecil menyusuri satu sisi ruangan.
Tidak ada reaksi dari pasien. Tangannya hanya merogoh-rogoh permukaan meja besi, lantas melemparnya kembali tanpa perkiraan.
Dia buta.
"Dira!" panggilnya pelan di sela bunyi aluminium bergesekan. Aku tahu dia mencoba mengalihkan perhatian pasien gila itu. "Indranya lumpuh. Menjauh dari sana!"
Sialnya kepalaku menoleh lebih dulu mengikuti sumber cahaya dari balik pintu. Di sana berdiri sebuah kepala ... tanpa tubuh di bawahnya. Seandainya aku percaya kuyang, mungkin kayang adalah pelarianku saat ini. Namun, di bawah sana terdapat besi panjang, menyangga kepala itu tetap bertahan, lengkap dengan anatomi organ buatan.
"Keluarkan aku dari sini," rengeknya di ambang pintu. Jeratan kabel tak mengizinkannya melewati meja resepsionis. Itulah mengapa kami tak mendengar langkah kaki tadi.
"Dira!" Altair mengibaskan tangannya, memberi kode padaku agar cepat menyusulnya.
Lagi-lagi aku menoleh, seakan enggan membiarkan gadis bersurai panjang tanpa tubuh asli itu sendirian. "Aku bakal balik," ujarku menempelkan telunjuk pada bibir, memberinya isyarat agar tutup mulut tentang keberadaan kami.
Ketukan sepatu menyadarkanku bergegas melesat ke sisi Altair detik itu juga. Dadaku berdebar kencang, kami hanya bersembunyi di balik brankar dorong yang ditumpuk, meninggalkan tripod poster tadi di tempat sebelumnya.
"Tadi ngomong sama siapa?" Napasnya menyentuh leherku hangat. Keringat dingin mengucur dari pelipis lelaki itu.
Tidak langsung kujawab pertanyaannya, karena beberapa langkah di depan kami, sepasang sepatu hitam muncul dari balik tangga. Ini pertama kalinya seumur hidupku berdebar tak keruan dan rasanya ingin cepat-cepat menghilang dari sini sekarang juga.
Seorang pria dengan jas putih khusus dokter, lengkap dengan celana hitam panjang beserta sarung tangan. Langkah pelannya mampu membuatku menahan napas bersama Altair.
Dari jarak dekat, kami mengamati pria itu menghampiri pasien yang hobi main lempar-lemparan alat bedah itu. Sekali gerakan, kerah belakang perempuan tadi dicengkeramnya hingga sang empu meronta.
Masih tidak ada suara jeritan yang sudah kutunggu-tunggu sejak tadi. Sebagai gantinya, bunyi yang keluar dari tenggorokan itu hanyalah deritan serak memilukan. Leherku ngilu mendengarnya!
Tanpa sepatah kata, pria itu menyeretnya melewati kami. Pasien dengan kepala diperban hingga matanya itu berkali-kali membentur kaki-kaki kursi besi.
"Bisu. Pasien itu bisu," jelas Altair tanpa suara. "Pria itu sudah melakukan sesuatu terhadap pita suaranya."
Ini bukanlah dongeng putri duyung yang suaranya diambil demi menukarnya dengan sepasang kaki manusia. Selamat datang pada realita, di mana kala dirimu lengah, di sanalah nasibmu berakhir lebih mengenaskan.
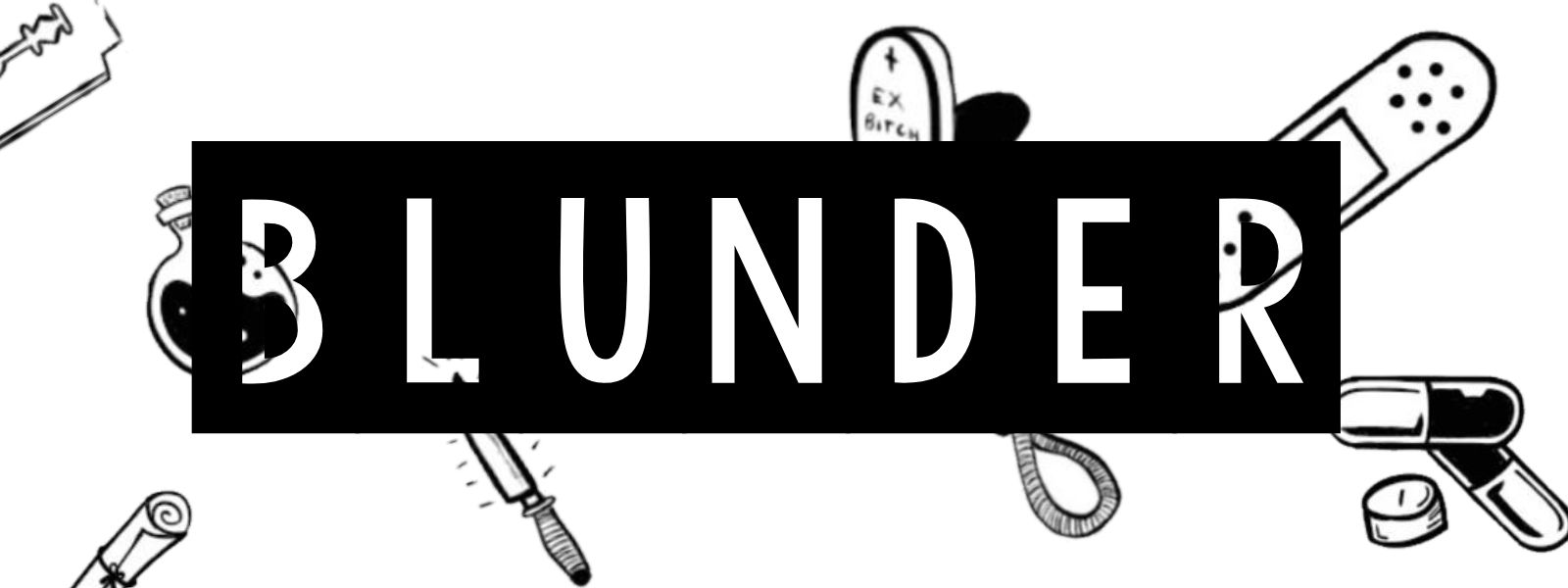
~('-' 1200 words '-')~
R/E/U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top