IX. Narasi Berdarah

Senin, 22 Januari 2018
—Adira
Hari libur selalu berakhir lebih cepat dari hari-hari biasanya. Senin kembali menyerang, dan aku harus kembali pada rutinitas; berangkat lebih awal, menyiapkan pasukan upacara bendera sebagai anak OSIS, lalu berdiri di barisan terdepan sambil membawa map berisi teks undang-undang dasar.
Setelah semalaman Altair meneror dengan segudang rencananya hari ini, mataku masih sayup-sayup tertutup terkena semilir embun pagi menyejukkan. Rasanya punggung ini masih mau menempel dengan kasur bin selimut.
Tadi pagi, begitu kuberi tahu Altair kalau OSIS ada rapat sepulang sekolah, membahas tentang persiapan ulang tahun kota kami, wajahnya tertekuk. Seharian anak itu melipat tangannya di meja, memasang wajah berpikir serius, lalu menulis sesuatu di buku tulisnya, kemudian mengulangi hal yang sama hingga lonceng pulang sekolah.
Teman-temannya menghambur ke meja kami, membuat keributan kala aku bergegas memasukkan semua peralatan ke dalam tas.
"Kutunggu di lapangan, sini tasmu." Telapak tangannya terulur, bak majikan yang minta kembalian uang belanja. "Baca juga catetanku, hafalin." Dia menyodorkan buku tulis tipisnya setelah kuberikan tasku padanya. Altair bahkan tak repot-repot mengubah ekspresi dinginnya di depan teman-teman sekelas kami.
Tepat setelah aku menerimanya, para lelaki itu berlarian keluar kelas sambil teriak-teriak. Sudah, begitulah Seninku yang monoton seperti biasanya.
Rapat selesai pukul setengah lima sore, matahari sudah main perosotan di langit barat. Kupikir Altair bakal pulang duluan, malas menunggu gadis sepertiku di lapangan sekolah. Nyatanya, anak itu masih bermain bola dengan temannya yang tadi, oh ralat, Altair hanya duduk memegang ponselnya di sudut lapangan bersama Bara.
Begitu aku menghampirinya, tas kami sudah terdampar manis di dekat pantat Bara. Mereka serentak mendongak, menyadari cewek yang rambutnya mirip Simba di berdiri dengan napas ngos-ngosan.
"Udah baca, 'kan?" Altair bangkit, menepuk celananya, menyambar tas kami dan melambaikan tangan pada Bara. "Duluan!"
Aku memang sudah membaca catatannya-yang dia kerjakan selama jam pelajaran. Isinya hanya jadwal Dokter Flo beserta keterangan di beberapa tempat. Dia juga menggambar denah masing-masing lantai rumah sakit tempo hari. Bakat tersembunyinya menjadi arsitek mulai keluar.
Sekolah sudah sepi, menyisakan beberapa anak OSIS tadi yang memegang ponsel minta jemput di depan gerbang. Satpam mulai berkeliling, memeriksa tiap kelas terkunci.
"Jadi apa rencanamu abis ini?" tanyaku, langkah kami sudah melewati halaman depan gerbang sekolah.
"Kita ke basemant hari ini. Sampe nanti malem, Dokter Flo bakal di lantai tiga buat eksperimen pasien cewek." Wajahnya mendadak berubah lagi, ada senyum di sana dengan makna yang berbeda.
Keningku mengernyit, menyadari sesuatu hal yang tidak biasa. "Dari mana, sih, kamu dapet jadwal beginian?" decakku, memperbaiki rambut dan posisi tas di punggung.
Altair terkekeh-semacam mendengkus, sambil tersenyum lebar. "Observasi." Kedua alisnya terangkat, melirikku menggunakan tatapan merendahkan. "Jangan salah tangkap, ini aku lagi seneng. Orang tuamu pulang abis isya, 'kan? Soalnya misi kali ini bakal lebih lama."
***
Kami kembali ke rumah sakit itu, dan baru kali ini kuperhatikan papan nama berjajar karatan, satu-dua huruf ambruk kian rapuh. Posisinya menghadap ke barat, tepat di samping air mancur mati gersang. Rerumputan liar tumbuh jarang-jarang di sela tanah-tanah dan aspal retak.
Lagi-lagi kami harus menyelinap di tengah-tengah pintu kaca berantai. Kutemui Putri memejamkan matanya di depan pintu meja resepsionis lantai satu. Gadis itu terlelap bersama paru-paru buatannya, kembang-kempis seirama deru napas dan jantung menyeramkan.
Altair memimpin di depan, mengindahkan Putri dan jeritan kecil dari dalam poli saraf. Langkahnya menuntun kami melewati ruang tunggu, mendorong pintu transparan menuju taman mini dalam gedung berbentuk persegi.
"Kamu beneran mau ikut, 'kan?" tanyanya lagi, mungkin ini ketigakalinya dalam dua puluh empat jam terakhir dia melirikku demikian.
Masih menggendong tas, kurangkul lelaki itu gemas. "Sekali lagi kamu nanya, aku beneran pulang, Al," geramku meremas bahunya.
Dia menghentikan langkahnya di depan undakan dan tangga menurun pada salah satu sisi taman. "Gak tau, rasanya kayak maksa kamu buat ikut. Nggak enakan aku." Altair menoleh, napasnya merambati kulit punggung tanganku.
"Elah ... harusnya kamu ngerasa kayak gitu waktu kita tukeran jawaban PTS," cibirku memonyongkan bibir.
Tangannya merogoh saku, mengeluarkan ponsel dan menyalakan flash. "Di bawah bakal gelap, nggak ada listrik. Tambahan, map yang tadi kukasih itu masih denah lama."
Aku ikut mengeluarkan ponsel, sekilas melirik jam yang sudah menunjukkan pukul lima kurang seperempat. "Masih ada sejam lagi sebelum magrib, kita cuma mau ngambil foto sama bukti, 'kan?"
Langkah kami mulai maju, turun melewati undakan gelap. Penciumanku menangkap bau berbeda dari sebelumnya. Tiap-tiap lantai memiliki aroma khasnya masing-masing. Seperti lantai satu ini, yang kucium adalah bebauan saat pertama kali masuk mobil panas di bawah terik matahari siang. Bedanya, hawa di sini dingin dan lembab akibat tiadanya alat sirkulasi udara.
"Dir, jangan lepasin rangkulanmu," bisiknya begitu tiba di lantai bawah.
Pintu kaca transparan menyambut kami, menjadi gerbang menuju gelapnya basemant. Seperti perkiraan Altair pada buku tulisnya, tempat ini adalah parkiran biasa yang luasnya bahkan lebih kecil dari lantai-lantai di permukaan. Tidak mengherankan, pengunjung pasti lebih memilih parkir di lapangan rumah sakit ketimbang harus repot-repot masuk sini.
Maju beberapa langkah dari undakan paling bawah, kami menjumpai lift tertutup usang. Jelas tidak beroperasi, listrik bahkan jarang di sini. Bersama-sama kudorong pintu kaca dengan mudah, tidak ada yang terkunci di sini.
"Di sini?" Aku celingukan, mengendarkan cahaya flash ke segala arah. Ketika kuingat lagi hari mulai gelap di luar, bulu kudukku merinding seketika.
"Bukan, satu lantai lagi di bawah." Tangan dingin itu menggenggam milikku di bahunya. "Jangan dilepas."
Satu undakan lagi kami lewati, bebauan selisih berganti kembali. Kali ini aku sungguhan tidak bisa mendeskripsikan bagaimana aroma sekitar. Ini bau yang aneh, berbeda dari empat lantai di atas.
Altair menghentikanku di depan lift. "Rekam dari sini," perintahnya, netra gelap itu menatapku intens, "mulai dari sini, aku ragu bakal baik-baik aja."
Kuturuti maunya, menyalakan perekam sebelum mendorong pintu kaca bersamaan. Kameraku tidak bisa menangkap apa-apa sangking gelapnya, hanya pilar-pilar terdekat yang kami lewati dan lantai kami berpijak.
Aku terlalu sibuk melihat ke mana kameraku berjalan, hingga tak sadar kami sudah berada di depan pintu besi putih dengan pegangan silver berkarat. Altair menyenterinya, tanpa berkata apapun menarik terbuka benda itu.
Kupikir lorong gelap akan menyambut kami, tetapi nyatanya justru membuatku tercengang. Altair mematikan flash, menyimpan ponsel dalam saku lalu mengamit lagi telapak tanganku di pundaknya.
Terang, ruangan ini bahkan memiliki cahaya lampu! Bagaimana bisa?! Listrik bahkan padam di atas sana!
"Ada CCTV di sini," dengkusnya melepaskan tanganku demi menurunkan ransel. "Stop dulu rekamannya, aku kudu meretas CCTV biar kita nggak ketauan nanti." Dibukanya tas sekolah, mengeluarkan laptop hitam dengan cepat.
Kepalaku seakan berhenti memproses segalanya. Di balik Altair yang tampangnya nolep di kelas, sering minta jawaban ulangan, dan kalem-kalem menyebalkan, anak itu justru menyimpan segudang rahasia mengenai kebolehan dirinya sendiri.
Beberapa menit aku menunggu, turut berjongkok di sebelahnya. Ponselku sudah menunjukkan pukul lima tepat, dan lelaki itu selesai meretas sistem keamanan lantai ini. Aku melihatnya membuka jendela sesuatu di laptop, entah itu apa tidak ada yang bisa kupahami kalau menyangkut alat-alat elektronik.
"Sudah." Dia menutup laptop, memasukkan kembali ke dalam tas. "Nyalakan lagi rekamannya." Diambilnya lagi tangan kananku untuk melingkar di dekat leher.
Lorong terang menyambut, semakin jauh kami melangkah, semakin dingin hawa sekitar. Saat ujung lorong mulai terlihat, suara-suara mengerikan menyayat telinga memaksaku berhenti.
Hampir kupeluk anak itu, seandainya pikiran ini sudah tidak logis sejak awal. "Kamu belum kasih tau rencanamu abis ini, maksudku selain ngambil bukti-apa yang mau kita ambil di sini, coba?!"
Besi-besi berdenting nyaring, kami kembali maju meniti lorong, berbelok di pertigaan menuju ruangan besar berisi rak-rak besi tinggi.
"Total pasien di sini ada tiga puluh empat. Dua belas di antaranya nongkrong di gedung pendamping, sisanya dua puluh dua orang di sini." Altair terus menuntunku melewati tengah-tengah ruangan berbau perlengkapan medis. "Lantai 1 ada dua pasien, lantai 2 tiga pasien, dan lantai 3 tiga pasien. Totalnya delapan, jadi masih ada empat belas orang di bawah sini," jelasnya panjang-panjang.
Aku mencerna kalimatnya. "Terus? Kita cuma foto-foto selfie gitu? Posting di Instagram 'Halo gais, kita berdua lagi jalan-jalan di rumah sakit horor, lho! Serem banget, banyak mayatnya-'"
Seketika tubuhku mematung tak bergerak, melepas rangkulan di bahu Altair. Rasanya kaki ini menjadi jeli, kepalaku berdenyut melihat banyaknya genangan cairan keramat di balik dinding kaca transparan.
Altair terus melangkah di depan, menuju persimpangan selanjutnya sementara aku masih bertahan di depan dua orang laki-laki yang meronta terhalang kaca tebal. Lengan mereka hitam kehijauan diloncati belatung. Mulutnya sama-sama terbuka, menjerit dari dalam sana dengan sepasang bola mata merah berputar-putar tak jelas.
Ruangan di depan sana jelas kedap suara, buktinya aku sama sekali tidak mendengar jeritan bahkan suara kecipak darah saat mereka berlarian. Salah satunya membenturkan kepala pada dinding kaca, mengikut ke mana arahku pergi. Keduanya bertelanjang dada, hanya menggunakan celana pendek selutut yang bernoda darah.
Netraku bergetar ketakutan. Selama ini kupikir zombie hanya ada di film-film science fiction. Hari ini semuanya berubah, aku percaya semua film itu bisa benar-benar terjadi seperti sekarang ini.
Tunggu, harusnya aku tidak berpisah dengan Altair. Namun, begitu aku menoleh, punggungnya sudah menghilang di balik lorong lain. Aku harus segera menyusulnya, dan meninggalkan ruang penyimpanan ini.
Baru selangkah langkahku menjejak, pandanganku lebih dulu berpendar kunang-kunang nan berat. Ada yang salah, terbukti saat kutolehkan kepala ke belakang, sosok pria menggunakan jas putih sudah menyeringai lebar, mencekal kerah belakang seragamku.
"Lepas, argh!" Aku meronta, berteriak keras-keras kala menyadari sebuah jarum menusuk leherku. "Emak!" jeritku panjang, memberi kode pada Altair sebelum segalanya gelap dan tubuhku lemas.
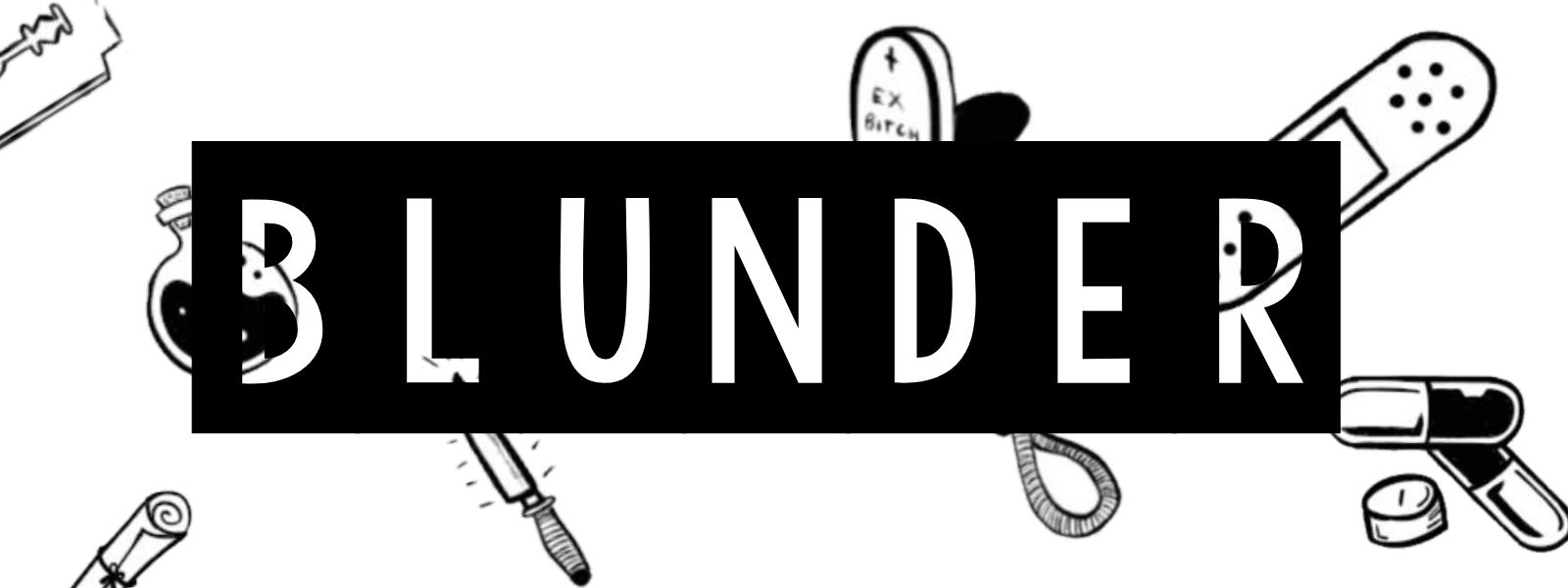
~('-' 1550 words '-')~
B'/E/U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top