10. Melupakan Galoeh
Weda pun akhirnya berpamitan dengan Harti di depan rumah gadis itu di daerah Kauman setelah mereka pergi ke Setabelan, bertepatan dengan azan maghrib yang berkumandang dari masjid desa itu. Tak ingin mengulur waktu, Weda kembali mengayuh sepeda untuk pulang ke Lawejan dengan pikiran penat. Status ‘kawin’ yang tersemat dalam kartu pengenalnya, kini membatasi dirinya berinteraksi dengan Harti.
Langit sudah gelap ketika roda sepeda menggelinding di jalan utama kota Soerakarta. Tak lagi banyak orang lalu lalang mengingat waktu sudah menjelang pukul tujuh. Berteman dengan lampu dinamo yang remang-remang menyinari jalannya, ia bergegas mengayuh pedal agar segera tiba di rumah sebelum jam malam diberlakukan. Seiring dengan berputarnya roda sepeda, otaknya juga kembali memutar ingatan tentang peristiwa siang tadi.
“Masih ingat, Mbok Panti bukan?" Gala memulai percakapannya siang itu. Jelas Weda mengenal wanita yang disebut Gala. Mbok Panti adalah istri seorang abdi Mangkunegaran yang dituduh memberontak. Mendapat anggukan Weda, Gala meneruskan. "Beliau sakit dan keluarganya kekurangan makanan."
“Kasihan Mbok Panti. Waktu itu dia hamil besar ketika suaminya dieksekusi.” Harti menggeleng berulang menunjukkan keprihatinannya.
“Bagaimana kamu bisa tahu kalau Mbok Panti sakit?” tanya Weda.
“Sudancho Pantja yang memberi tahu tadi sewaktu mendapat kabar dari adiknya. Awalnya, Windu mau cari kamu. Berhubung kamu ndak ada, Pantja meminta tolong aku ke sini untuk mencari dokter. Sementara dia mau ke sana,” terang Gala.
Mendapati cerita Gala berdasarkan yang ia dapat dari Windoe, adik Pantja yang juga tetangga Mbok Panti, mereka bertiga akhirnya pergi ke Setabelan di mana keluarga almarhum Karman yang dieksekusi tahun lalu tinggal. Mbok Panti, istri Karman, tinggal bersama tiga orang anaknya. Saat mereka tiba, Pantja sudah ada di situ. Ia membawakan Bubur Perjuangan yang sebenarnya tak cukup mendongkrak nilai gizinya.
Weda langsung dipersilakan masuk ke dalam kamar berdinding tembok yang lembab. Ia lalu duduk dan mengorek riwayat penyakitnya sebelum Harti mengulurkan stetoskop.
"Apa yang dirasakan?" tanya Weda melakukan pemeriksaan pada wanita berusia tiga puluh tahun yang itu.
"Sesak." Mbok Panti meringis.
“Kapan terakhir makan?” Weda melakukan pula pemeriksaan pada perut sambil otaknya merangkai diagnosa dan rencana terapinya.
“Sehari lalu. Sudah saya buatkan ubi tapi muntah.” Anak berusia tujuh tahun yang menggendong anak bayi beberapa bulan itu menjawab.
“Masmu mana, Nduk?” tanya Gala.
“Sekolah. Habis itu kerja.” Gadis kecil itu berdiri masih sambil menimang bayi.
“Sini, Nduk. Biar Mbak gendongkan.” Harti kasihan dengan anak kecil itu.
Anak itu mengulurkan adiknya untuk digendong Harti. Wajahnya tampak lega karena bisa mengistirahatkan lengan kurusnya sejenak.
“Keterlaluan sekali Nippon!” Pantja mendesis geram.
Amarah Pantja juga dirasakan Weda. Namun, untuk saat ini ia harus meredamnya karena harus fokus memberikan terapi pada Mbok Panti. “Saya usahakan akan carikan obat. Njenengan (Anda) tenang saja.”
“Iyo, Mbok. Dokter Weda ini lulusan Londo. Ndak main-main ilmunya.” Pantja berusaha membesarkan hati Mbok Panti.
Peristiwa yang ia alami hari ini—terpaksa menjadi suami dan melihat sendiri penderitaan istri dan anak-anak dari seseorang yang dieksekusi karena ingin menentang pemerintah yang semena-mena—menimbulkan gelegak amarah Weda. Ia tak pernah berpikir kedatangan Dai Nippon akan membuat rakyat Indonesia menderita. Dan, kalau Jepang tak segera hengkang dari bumi ini, ia yakin sumber daya negeri ini akan terkuras habis.
Pikiran-pikiran yang memenuhi kepala Weda akhirnya terjeda saat roda membelok ke halaman kediaman Tirtonagoro. Tepat pukul 18.30, Weda masuk ke rumah dan disambut Ibu dengan senyum lebar.
“Lama sekali kalian. Ke mana saja?” Ibu Lastri menyongsong kedatangan Weda.
“Tadi saya …” Tenggorokan Weda yang kering tercekat. Ia tak mungkin mengatakan pada ibunya kalau ia bersama Harti seharian. “ada perlu sebentar.”
“Lho, mana Galoeh?” tanya Tika yang juga tampak antusias menunggu kedatangannya.
“Galoeh ….” Jakun Weda naik turun. “belum pulang?” Suaranya serak karena ia melupakan Galoeh begitu Gala mengabarkan berita itu.
“Ya belum to? Wong kamu juga baru datang.”
Seketika Weda menoleh ke belakang seolah menyusuri jalan menuju Panti Rogo. Tak ingin menduga-duga, ia lalu memelesat keluar menembus malam untuk kembali ke Panti Rogo, tak memedulikan omelan Ibu Lastri.
Dalam hati Weda merutuk kalau ia benar-benar mendapati Galoeh ada di sana! Ia yakin Galoeh tak akan di sana. Seingat Weda, gadis itu tak ada di tempat ia memarkir sepeda sehingga Weda pun tak ingat kalau ia datang bersama Galoeh saking tergesanya.
Saat ia mendekati rumah sakit yang tampak suram di malam hari, ia menekan rem. Roda yang berputar pun berhenti. Kaki jenjang Weda turun, menapak tanah. Kepalanya meneleng mendengar suara perempuan menyanyikan lagu Jepang yang sering diputar di radio berjudul Aikoku no Hana atau Bunga Patriotik.
“Galoeh?” Weda memicing.
Buru-buru Weda kembali mengayuh sepeda, menghampiri Galoeh yang sedang bercangkung sambil bersenandung. Seketika dada Weda yang disesakkan kecemasan, bisa bernapas lega begitu melihat gadis itu. Ia lantas berdeham, menutupi perasaan bersalah karena melupakan gadis yang sudah menjadi istrinya. “Sepertinya orang yang menginap di rumah sakit ini akan mimpi buruk kalau mendengar suaramu.”
Galoeh mendongak. Matanya berbinar. “Mas Weda!” Ia bangkit dengan senyum merekah lebar di kegelapan menguak gigi putihnya.
“Kenapa kamu masih di sini? Bagaimana kalau aku ndak ke sini?” Nada Weda meninggi. Entah kenapa ia marah. Mungkin laki-laki itu cemas karena Galoeh begitu polosnya menunggu Weda, atau karena ia yang merasa bersalah. Semua perasaan itu bercampur aduk. Namun, di balik kekesalannya, ia lega, Galoeh aman di sana. Menunggunya. Hingga ia memeluk gadis yang tubuhnya begitu dingin.
“Saya tahu Mas Weda bakal balik,” Suara Galoeh teredam di dada Weda. Ia tak menolak dipeluk Weda yang tulus mencemaskannya.
Hati Weda berdesir. Ia berusaha menguasai diri agar tak menyemburkan kata-kata nylekit, lalu mengurai rengkuhannya. “Lagian kamu dari mana saja siang tadi? Sewaktu aku keluar ke sini, kamu ndak ada.” Weda memberi alibi, berusaha menutupi kesalahannya.
“Oh, ya,” Galoeh mengambil sesuatu dari tas selempang, lalu menyodorkan ke hadapan Weda. “Ini. Tadi saya beli jagung. Katanya Mas Weda lapar.”
Weda mengerutkan alis, menatap jagung yang masih terbungkus klobot, bergantian ke arah mata Galoeh yang sayu. Rahangnya mengerat. “Kamu ….” Weda kehilangan kata. Tenggorokannya tercekat. Rasa bersalah semakin menghantuinya. “Jangan bilang kamu habiskan semua uangmu untuk beli ini? Trus kamu ndak ada karena beli jagung di tempat yang kita lihat tadi?” Padahal jarak penjual jagung ke rumah sakit cukup jauh.
“Mau bagaimana lagi. Dulu satu sen bisa dapat lima jagung. Sekarang cuma satu jagung.” Galoeh prihatin dengan mahalnya harga jagung yang sepertinya sikapnya tidak ideal di saat seperti ini. “Ini, makan. Tapi, sudah ndak panas lagi.”
Jakun Weda naik turun. Ia mengetuk dahi Galoeh dengan buku jarinya. Matanya tersengat panas sehingga bayangan gadis itu perlahan memudar. Untungnya pencahayaan malam itu sangat redup, sehingga Galoeh tak perlu melihat mata Weda yang berkaca-kaca disentil ketulusan Galoeh. “Seharusnya kamu pulang waktu lihat sepedaku ndak ada? Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Trus kenapa jagungnya ndak dimakan?”
Galoeh meringis, mengelus dahinya. “Mas pikir saya juga pengin kaya orang bodoh nunggu Mas di sini? Tapi, saya ndak bisa pergi karena Kempetai itu datang.” Dagu Galoeh bergerak lurus ke depan. Weda mengurut arah pandang Galoeh dan mendapat Souta membungkuk di kabin belakang ketika pandangan mereka bersirobok.
“Dia bilang apa?”
“Kalau Mas menjemput saya sebelum jam malam, berarti kita benar-benar suami istri. Suami ndak akan melupakan istrinya.”
“Sial!” rutuk Weda. Saat ia akan berbalik, mobil sudah berlalu. “Ya sudah, ayo kita pulang. Orang rumah sudah kuatir. Aku yakin bakal disemprot Ibu habis-habisan.”
Galoeh kemudian duduk di boncengan belakang. Seperti waktu berangkat, ia juga berpegang di sadel. Karena mengejar waktu dan hari sudah gelap, Weda tak lagi memperhitungkan jalan. Walau lampu dinamo bisa menerangi jalan mereka, tetap saja tak bisa membedakan tekstur tanah yang ia lalui. Hingga akhirnya ban sepeda melalui lubang yang membuat kedua penumpangnya terguncang. Seketika Galoeh mengalungkan tangannya dengan kencang di perut Weda.
“Kamu ndak pa-pa, Loeh?” Weda menghentikan sepeda sejenak, lalu menengok ke belakang.
“Ndak pa-pa, Mas.” Saat Galoeh tersadar ia meremas kain kemeja Weda, buru-buru ia melepas cengkeramannya. Namun, Weda menahannya.
“Pegangan yang kuat. Kita harus sampai sebelum Kempetai melihat kita berkeliaran.” Galoeh rupanya begitu penurut. Tak hanya menanti hingga semalam ini, ia pun masih mengalungkan lengannya di perut Weda.
Pada akhirnya, mereka tiba rumah lewat pukul tujuh malam. Seperti yang ia tebak, Ibu Lastri siap menyemburkan ocehan. “Kenapa kalian bisa berpisah? Kamu ada perlu apa kok sampai ninggal Galoeh?”
Galoeh mendekati Ibu Lastri dengan wajah semringah di balik wajah lelahnya. “Bu, saya yang salah. Tadi saya malah jalan-jalan sendiri. Makanya Mas Weda mikir saya sudah pulang.”
Kembali batin Weda nyeri. Ia tak menyebut Harti.
“Tapi, Nduk ….”
“Bu, boleh ya, saya istirahat.” Galoeh melempar tatapan memohon yang tak bisa ditolak Ibu Lastri.
“Ya sudah.” Ibu Lastri mengalah. Sepertinya wanita paruh baya tak bisa berkelit bila berhadapan dengan menantunya. “Oh, ya, Mbok Mi sudah mindah barang-barangmu ke kamar Weda. Karena kalian sudah suami istri, kalian bisa tidur bersama.”
“Apa?” Sontak Weda dan Galoeh berseru bersamaan tanpa aba-aba.
“Kalian sudah resmi jadi suami istri.”
“Bu, kenapa Ibu—” Weda tak bisa berkata-kata lagi. Apalagi melihat raut Galoeh yang memutih, ia yakin gadis itu sama terkejutnya dengannya.
“Kalian sudah menikah. Masak ndak sekamar?” Ibu Lastri menatap Weda dan Galoeh bergantian.
“Ka-kami belum pemberkatan.” Weda gagu melontar alasan yang nalar. Jelas tak mungkin ia menghabiskan malam sekamar berdua dengan Galoeh yang belum ia kenal dekat.
“Kamu tenang saja, Mas. Ibu dan Romo tadi yang mengurus pemberkatan siang tadi. Nanti akan ada kabar, kapan pemberkatan akan dilaksanakan.”
Kalau tidak melihat wajah pucat Galoeh, pasti Weda akan meneruskan perdebatan ini. Sehingga untuk kali ini, ia mengalah dan melangkah begitu saja ke kamarnya.
“Mas,” panggil Galoeh dengan langkah kecil yang tergesa mengikuti Weda. “Saya bisa tidur di kamar tamu. Mas tenang saja.”
Weda mendengkus sambil meremas rambutmya yang basah karena keringat. “Dan kamu mau Ibu marah-marah ke aku?”
“Lha terus?” Galoeh tak bisa berkata-kata.
“Ya, malam ini kita ti-dur …” Weda memberi penekanan pada kata tidur. “bersama. Hanya tidur.”
Mau tak mau, Weda menerima titah Ibu. Ia tak tega melihat wajah kuyu Galoeh yang kebingungan. Setelah ia masuk, Galoeh mengikuti di belakang.
“Mas, ini jagungnya!” Kali ini Galoeh menarik tangan Weda dan mengulur jagung yang sudah dingin itu.
Weda melongo, menatap jagung yang ada di tangannya. Batinnya bergemuruh tak nyaman. Padahal tadi ia sudah makan nasi goreng dengan telur buatan Harti di Setabelan. Sementara, ia yakin perut Galoeh sudah kosong karena tak terisi makanan tadi siang dan malam ini. “Besok lagi kamu ndak usah kuatirkan aku.”
Galoeh tersenyum kaku. “Mas lapar. Saya hanya punya uang yang cukup buat beli jagung. Apa Mas ndak suka jagung?”
Susah payah Weda menelan ludahnya sendiri. Setidaknya ia paham kenapa Ibu Lastri mati-matian meminta Galoeh menjadi istrinya. Gadis ini dididik untuk peduli terhadap sesama. Kalau tidak, tak mungkin Romo Tjokro rela menanggung risiko besar untuk mengirim beras ke keluarganya yang memang kekurangan beras karena di daerah ini beras susah didapat. Kalaupun ada, harganya menjadi selangit.
“Matur nuwun.” Hanya itu yang bisa ia katakan.
“Ya sudah, kalau begitu, saya mandi dulu.” Galoeh terlihat bingung. Tas koper yang ia bawa sudah ada di atas lemari di kamar Weda. “Baju saya?”
“Coba lihat di lemari.”
Galoeh pun membuka lemari dan mendapati beberapa potong bajunya ada di bagian paling bawah. Ia mengambil satu baju yang ia pinjam dari Tika dan bergegas ke luar.
Weda mendengkus, menatap pintu yang tertutup lalu kembali mengamati jagung yang masih terselubung kulit pembungkusnya. Satu persatu ia buka klobotnya menguak biji jagung yang masih tertata di bonggol. Ia mencoba satu gigitan dan entah kenapa, jagung dingin itu mampu menghantarkan kehangatan di sukmanya.
Tanpa sadar Weda menitikkan air mata. Batinnya merutuk karena Galoeh berhasil membuatnya menangis seperti anak kecil. Sebagai pria dewasa, ia bahkan lupa kapan terakhir kali bulir bening menetes di pipinya. Sial! Sejak Galoeh datang, hidupnya benar-benar tak bisa tenang. Gadis itu selalu berhasil membuatnya merasa bersalah!
💕Dee_ane💕
Partnya panjang-panjang yak😬
Makasih udah ngeramaiin di part kemarin. Tetap kasih vote dan komen banyak2 yak🥰
Macem gini penampakan Galoeh pas bonceng di depan😬
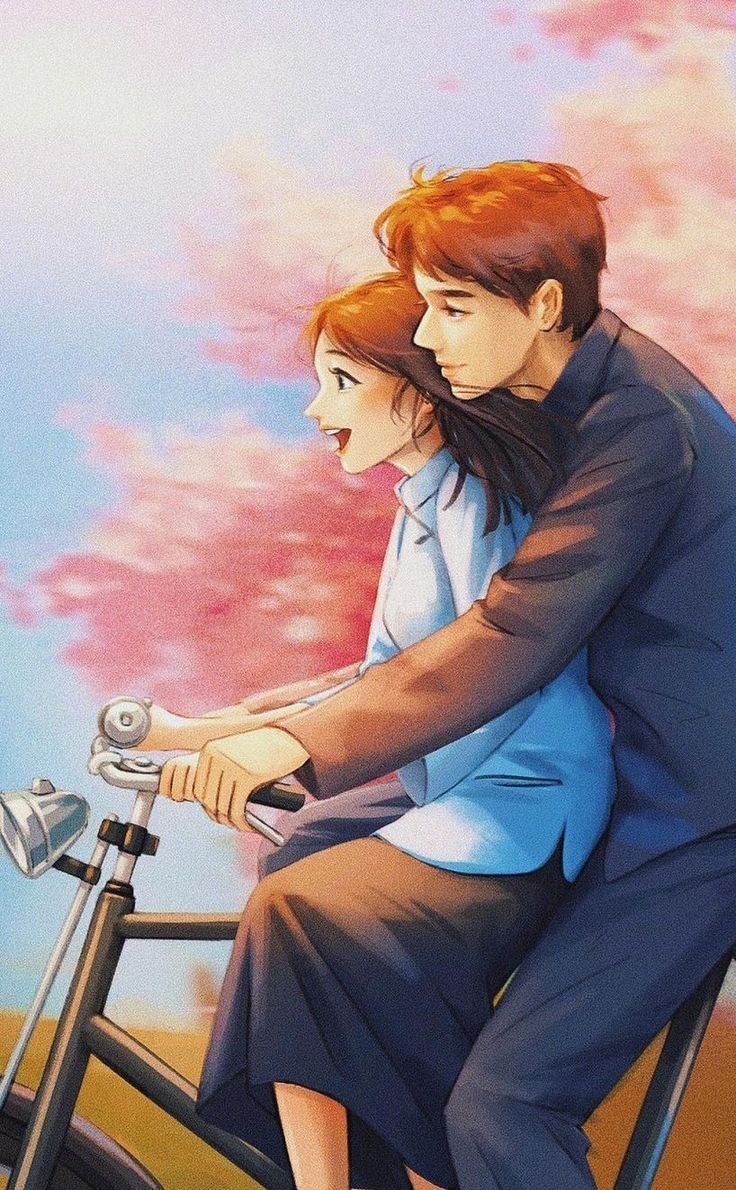
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top