Amateur
Jam empat sore, ketika hujan sudah benar-benar reda, aku duduk di samping kemudi, membiarkan Ghani membawaku ke pameran. Lagi-lagi, aku memakai bajunya. Aku numpang mandi lagi di kamar mandi mewahnya. Kali ini ada aroma terapi yang menguarkan aroma sereh. Bikin makin betah untuk mandi lama-lama. Tapi Ghani tidak membiarkanku untuk terus bersemedi di bawah pancuran air hangat dan aroma sereh yang menenangkan. Aku tidak boleh bersembunyi di kamar mandi, katanya.
Pandanganku menerawang langit yang sudah tidak lagi menjatuhkan butiran sejuknya itu. Aku penasaran, apa yang sedang mengintaiku di balik para awan dan atmosfer bumi ini. Hati kecilku menjerit-jerit tak karuan "culik aku! Ayo culik aku!"
Aku menoleh pada Ghani yang sedang asik menyetir. Lelaki ini memang dingin. Tapi tampan. Aku tahu, yang suka padanya banyak. Dia malah suka padaku. Dasar Ghani. Dan aku tidak pernah menyadari kalau ternyata Aurora dekat dengan Ghani. Aku juga tidak pernah tau kalau Rama juga ada kaitannya dengan Aurora. Bahkan aku merasa Lana juga menyembunyikan beberapa hal dariku. Ah. Aku jadi berpikir, sebenarnya aku ini bermakna apa bagi teman-temanku? Mengapa mereka menyembunyikan hal-hal penting ini dariku? Mereka tau sesuatu dan hanya aku yang tidak. Apa selama ini aku dikelilingi para penipu? Apa aku terlalu payah terjebak pada sandiwara yang bahkan aku tak memiliki peran di dalamnya?
Kami menghabiskan perjalanan tanpa kata-kata. Hanya suara radio dengan volume pelan yang mengisi kekosongan. Jarak yang memang tidak terlalu jauh, jadi terasa makin dekat. Karena aku tiba-tiba diharuskan turun semenjak Ghani mematikan mesin mobil dan membuka kunci pintu.
"Ayo Kat, jangan biarkan seniman menghilang saat pameran."
Aku menghela napas kasar. Ucapan Ghani mendorongku pada realita. Lari dari masalah memang bukan pilihan baik. Ghani terus berjalan di sisiku sampai kami masuk ruang pameran. Saat aku menoleh padanya untuk terus minta ditemani, ternyata dia menghilang. Meninggalkan aku yang berdiri kaku dengan tatapan menyapu seluruh ruangan.
Di dekat sekat papan yang memajang lukisan dedaunan berembun di tengah cangkir-cangkir teh, aku melihat sosok yang amat kukenal.
Ada Fera di sana, sedang mengobrol dengan seseorang. Rama. Lelaki itu kemudian menyadari kedatanganku dari jauh lalu dia perlahan memundurkan langkah dan pergi meninggalkan Fera yang langsung berbelok arah untuk pergi. Sayangnya, dia menemukan mataku dan menghentikan gerakan kakinya.
"Kat."
"Rama kemana? Eh, Bram-mu maksudnya."
"Hah." Fera menarik semua lelahnya dalam satu tarikan napas panjang. "Tidak tau."
————————
Fera POV
Semalam, Lana memang sengaja mengajak Katina untuk pulang duluan. Rama mau bicara padaku, katanya. Tidak lama setelah mereka pulang, aku dan Rama berpindah tempat ke rumah temannya. Dia memang jarang di kosan. Sekalinya di kosan hanya membuat berantakan dan tidak pernah ada niatan untuk bersih-bersih.
Rama kembali melontarkan permintaannya. Urusan tanah yang kemarin sudah selesai. Aku membatalkannya. Membuat dia semakin marah. Aku tidak pernah melihat Rama semarah itu. Dia bilang aku sudah mempermainkannya. Tentu aku balik marah padanya. Dia sudah mengacaukan hari-hariku belakangan ini.
Lalu dia semakin membuatku seram. Tatapannya tidak pernah sebengis itu. Giginya gemeratakan menahan emosi. Di rumah itu sepi. Aku tidak tahu kemana temannya pergi atau setidaknya jika ada penghuni lain di rumah itu, jelas mereka semua tidak ada. Atau mereka memilih untuk bersembunyi dan menghindari pertikaian kami.
Rama mengancamku.
Ancaman yang menurutku hanyalah bualan karena dia sedang tersulut emosi sejenak. Setidaknya, itu yang aku yakini.
"Nanti kamu akan tau." Bisiknya.
"Apa?"
Rama justru tertawa melihatku yang nyaris muak. Tanpa menunggu dia untuk menjawab, aku berbalik badan dan segera pergi. Ucapannya terasa tidak penting untuk diladeni.
"Halo." Katanya. Aku terdiam dan menoleh padanya sekali sebelum aku benar-benar pergi meninggalkan dia. Aku tidak tahu temanku ini mulai sakit jiwa atau bagaimana, tapi aku ingin sekali mengatainya begitu.
Kini, saat ini, ketika aku menatap mata coklat tua Katina yang sedang balas menatapku, aku seperti kehabisan kata-kata. Guratan kecewa begitu jelas dapat kutemui di wajahnya.
"Kamu sudah tau?" Tanyaku, mencoba untuk tersenyum sesudahnya. Senyuman kecil yang ternyata terlihat lebih tulus ketimbang senyuman lebar yang kuberikan pada banyak orang sebelum Katina datang lagi kemari.
Kini wajahnya begitu datar tanpa ekspresi. "Menurutmu?"
"Ya, karena kamu tadi menyebutnya dengan nama itu, dan melihat kekesalanmu, jadi, kamu sudah tau."
"Aku mulai tidak suka dengan cara kalian dekat seperti tadi."
"Kamu tidak perlu khawatir tentang Rama."
Katina menatapku tidak percaya. Aku tau akan terasa sangat membingungkan baginya. "Barusan aku juga ngobrol sama Aurora. Ternyata dia dekat dengan Ghani, jadi aku tebak kamu sudah dapat banyak info dari Ghani, kan?"
"Ya."
"Hmm, Kat, apa kamu mau ikuti permintaanku saat ini?"
Katina terdiam cukup lama dan aku cukup sabar untuk menunggu responnya. Sampai dia melontarkan tanya padaku. "Apa?"
"Jangan benci Rama."
"Kenapa?"
"Hah, Kat, aku banyak menyimpan cerita darimu. Maaf ya, karena aku tidak berpikir kalau hubunganku dan Rama sebelumnya mesti diceritakan. Aku dan Rama sudah pernah sepakat untuk tidak pernah membahas tentang masa lalu lagi. Tapi Kat, aku kenal Rama. Tolong jangan benci Rama dulu. Bukan karena aku membela dia atau bagaimana, tapi.."
Katina mengangguk-angguk cepat sambil menggenggam kedua tanganku. "Lebih baik tidak usah bahas dulu. Aku mau ke karyaku. Sepertinya, ada yang mau bertanya. Seniman tidak boleh pergi dari karyanya saat pameran, kan?"
"Ah, ya. Ya. Apresiatormu menunggu."
Begitulah aku membiarkan Katina yang pergi setelah memotong ucapanku. Aku senang dia kembali. Hanya kurang senang pada beberapa hal.
Semalam, setelah aku pergi meninggalkan Rama dan rumah temannya, aku baru sadar malam sudah begitu larut. Rupanya, obrolan dan pertikaian yang kurasa singkat bersama Rama menghabiskan waktu yang cukup panjang. Bernegosiasi dengan lelaki yang satu itu memang tidak bisa bersikap impulsif.
Aku berjalan kaki di trotoar jalan raya yang mulai sepi. Udara Bandung utara malam itu dingin sekali. Meski aku sudah memakai jaket yang cukup tebal, tetap saja rasanya tak cukup. Dadaku seakan mau beku. Napasku juga mulai tak karuan. Ditambah dengan pikiran yang berkelana kesana kemari.
Lalu sebuah motor berhenti di depanku. "Naik. Aku antarkan pulang. Atau kamu mau cari minuman hangat dulu? Kedai kopi Kodok masih belum tutup. 24 jam." Serius, tidak jauh dari tempat ini, ada kedai kopi bernuansa kayu yang namanya kedai kopi Kodok. Tapi belum pernah aku menemukan ada seekor kodok pun di sana.
Aku mengikutinya. Mungkin masih ada yang ingin dibicarakan dan aku memang menginginkan suasanya nyaman dengan minuman hangat. Rama memang cukup tau tentang aku. Beberapa sikapnya yang seperti ini membuatku begitu mudah untuk memaafkannya berkali-kali.
Dia memesankan minuman rempah sebelum aku bilang apa mauku. Yasudah, toh, memang itu yang ingin aku pesan. Awalnya kami saling menyesap minuman masing-masing dalam diam. Lalu Rama mulai mengajakku berbicara. Lebih ke obrolan santai. Bahasan yang membuat kami segera lupa tentang pertikaian sebelumnya. Tentang hubungan kita yang memang lebih indah saat menjadi teman. Beberapa kalimat ketakutan tentang sendirian, juga harapan yang terasa begitu semu. Masa depan begitu abu-abu jika dilukis pada lembaran buku. Hingga kami terbuai menertawai beberapa kebodohan kami. Tak ingin ada benci, namun tak pernah ada damai. Seperti kutukan yang terikat terlalu kuat. Kami mencari jalan keluar. Dan menertawai lagi kegilaan ini semua.
"Sudah jam tiga, sebentar lagi matahari muncul. Ayo pulang. Tidur sebentar lalu ke pameran pagi." Ajakku.
"Ayo."
Lalu kami mulai melindasi aspal lagi dengan motor Rama. Jalanan benar-benar sepi. Ditambah kanan kiri jalan hanyalah pepohonan, dan ada bagian yang menunjukkan sisi jurang.
Dari arah belakang, ada motor yang melaju dengan kencang.
"AKH!!" Aku memekik. Reflek. Perih sekali. Ghani buru-buru menghentikan motor dan pengendara yang baru saja menggores lenganku juga ikut berhenti di depan motor Rama.
Darah mulai menetes, mengalir di jaketku.
"Buka helmnya!" Pengemudi itu dengan kasarnya menarik helm Rama dan sedetik kemudian terkejut. "Bram? Maap, teu apal euy. Duh hampura pisan. Ieu abi aya tisu. Hampura pisan Bram. Eta lukana kumaha? Atuh, Bram. Rek dibawa ka rumah sakit teu?" Lelaki itu menyimpan pisaunya di saku, dia menunduk-nunduk dengan tangan memohon ampun pada Rama.
Sambil menahan perih di lengan kananku, aku mencerna ucapan orang itu. Pasti dia teman Rama. Dan dia begal? Rama berteman dengan orang seperti itu dan disegani?
"Sini tisunya. Cari perban sana. Sama obat luka." Dengan gesit Rama membersihkan darah di jaket bomberku yang memang berbahan mayer. Untungnya jadi tidak menyerap darah dan mudah dibersihkan.
Tak lama, dengan tergesa teman Rama datang membawakan apa yang Rama pinta. Aku membuka jaketku, membiarkan Rama membersihkan sisa darah, memberikan obat merah dan memasang perban untuk menempelkan kapas. Untung saja kaos yang kupakai berlengan pendek dan tidak terkena noda darah. Temannya itu dengan setia menemani Rama dan menampung apa saja yang Rama buang padanya. Tisu-tisu yang sudah dipenuhi darah, sisa kapas yang sudah terkena obat merah, dan apapun itu.
"Maaf ya neng."
Aku mengangguk, tanpa menatap wajah temannya itu. Lalu Rama membawaku pulang, menyuruhku segera melepas jaketku dan segera ganti baju. Dia berusaha sebisa mungkin agar aku tidak merasa takut atau larut dalam keterkejutanku.
Lalu jam setengah lima pagi, saat Rama sedang membuatkan teh hangat untukku, Katina menelepon. Memintaku segera ke tempat pameran. Buru-buru aku mengambil jaket yang baru, berwarna abu, dan meminta Rama mengantarku.
Itu.
Itulah yang terjadi semalam.
Hal yang tidak Katina tahu.
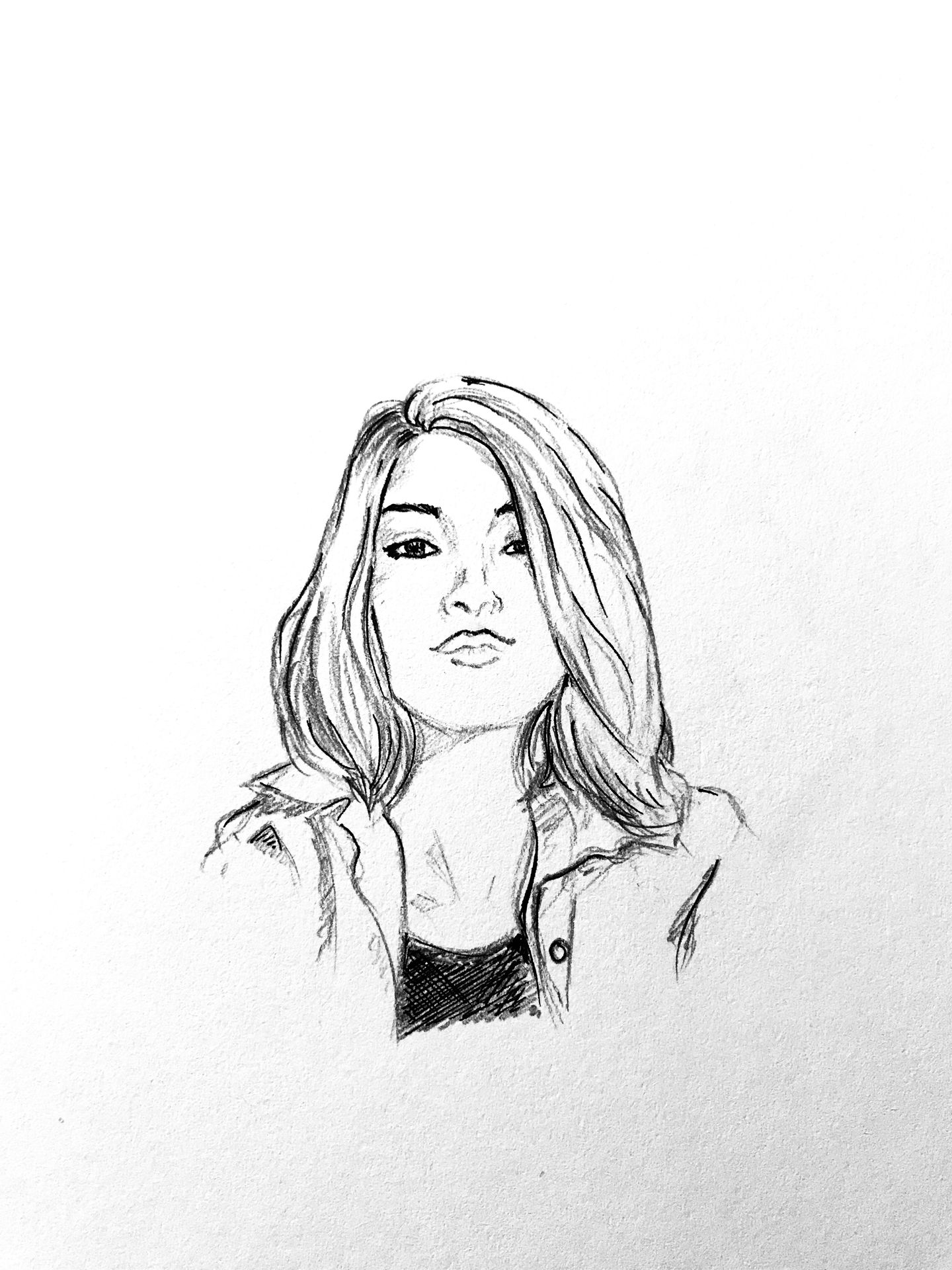
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top