00. | prakata oleh rené hartanto

—cogito, ergo sum.

KONON KATA RENÉ Descartes, yang namanya dipinjam Papi untuk dijadikan nama depan saya, aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Bagi Descartes, pemikiran kita sendiri adalah bukti paling nyata kalau kita ada, lebih dari bukti-bukti konkret kayak yang diajari guru Biologi saya waktu SMP:
Saat pikiran tersebut (tuh, kan, saya berpikir!) terlintas di benak saya, saya tengah buang air besar. Waktu itu, saya tengah membaca buku Puisi Mbeling-nya Remy Sylado, meski saya sama sekali nggak fokus ke berbagai puisi aneh yang ada di tiap halamannya. Pikiran saya lari kemana-mana. Tepat sebulan yang lalu, saya ulang tahun ke-enam belas. Di usia yang sama, Alexander Agung sudah berguru ke Aristoteles dan mempersiapkan diri untuk menguasai dunia, Mozart sudah menjadi komposer ternama yang bikin banyak opera dan tur keliling Eropa, dan Pascal sudah bikin teori matematika. Nggak usah jauh-jauh, deh—anak-anak seumuran saya sudah banyak yang jadi pemain bola yang diincar klub-klub ternama atau jadi idol K-Pop yang diteriaki anak gadis di seluruh dunia cuma gara-gara mereka bernapas.
Lalu, saya bagaimana? Saat anak-anak lain seumuran saya sudah meninggalkan jejak yang signifikan di dunia ini, saya masih jadi beban orangtua. Boro-boro menguasai bumi, di sekolah saja nyaris nggak ada yang kenal saya. Boro-boro diteriaki anak gadis di seluruh dunia, terakhir kali saya naksir cewek waktu SMP, saya ditolak gara-gara gebetan saya waktu itu nggak dibolehin pacaran. (Lalu, besoknya, dia malah jadian sama cowok paling ganteng di angkatan saya. Telek memang.)
Yang membuat saya memikirkan kembali alur hidup saya selama enam belas tahun ke belakang, mempertanyakan alasan saya ada di dunia dan kenapa hingga kini saya masih menjadi manusia yang nggak relevan. Pertama-tama, mulai dari nama filsuf Prancis ternama, sang Bapak Filsafat Modern sendiri, yang namanya dipinjam Papi untuk menjadi nama saya. The man, the myth, the legend—René Descartes.
***
Saya sempat bertanya ke Papi, dulu banget waktu saya kecil, kenapa saya dikasih nama "René". Kayak nama cewek, soalnya. Waktu SMP, bahkan sampai kelas sepuluh, saya memang sempat jadi korban bully-an parah, dan meski nama saya bukan satu-satunya alasan (atau bahkan alasan terbesar), saya tetap merasa agak risih karenanya. Minggu lalu, karena frustrasi, iseng saya bertanya ke Papi kenapa nama saya kayak nama cewek. Sudah saya duga, Papi, yang menggandrungi dunia sastra dan filsafat sampai-sampai rumah kami punya perpustakaan pribadi yang isinya koleksi bukunya semua, adalah pengagum berat Descartes dan konsep aku berpikir, maka aku ada-nya itu. Kata Papi, saya harus menjadi manusia yang nggak cuma sekadar menerima saja apa yang ada di dunia. Saya harus jadi manusia yang berpikir, dan yang paling terutama, manusia yang yakin akan pemikirannya sendiri.
Rupanya nama memang doa, dan doa yang Papi sematkan pada nama saya terlalu manjur. Saya tumbuh menjadi anak yang kelewat cerdas untuk ukuran usia saya. Sedari dini, saya sudah jadi "manusia berpikir". Sesaat setelah saya sudah bisa ngomong "Mami" dan "Papi", hal pertama yang saya lakukan adalah meraih salah satu koleksi ensiklopedianya Papi. Iya, sebelum saya bisa ngomong lancar, saya sudah bisa membaca, padahal nggak ada yang ngajarin.
Kalimat pertama yang keluar dari mulut saya setelah saya bisa ngomong adalah: "Mami, kata bukuna Papi Lené datangna dali pelut Mami, kan?" Saya menunjuk salah satu halaman ensiklopedia Papi, yang menunjukkan anatomi janin di dalam kandungan.
Mami tertegun mendengar pertanyaan yang saya lontarkan. Tiba-tiba banget, memang, buat ukuran anak berusia tiga tahun. Kendati demikian, Mami menggangguk.
Lalu saya bertanya lagi: "Teluc Lené jadi baby gala-gala sebelumnya jadi jigot, kan? Teluc abic itu ada molula, blatula, gatula, cama oganogeneci?"
Mami tentu saja kaget mendengar saya, yang masih berumur tiga tahun, sudah ngerti yang namanya morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Tapi Mami ngangguk-ngangguk saja.
"Teluc jigot munculna gegala cel telul ama cel pelma?"
Mami mengangguk lagi.
"Cel telul ama cel pelma ketemuna gimana?"
Saat itulah, Mami mulai malas menanggapi. Mami bilang, "Nanti Mami kasih tahu kalau kamu udah gede," tapi saya malah balik bertanya, "Napa haluc nunggu Lené gede?" Mami kelabakan, sementara saya tantrum, karena ngebet ingin tahu jawabannya di saat itu juga.
Sejak saat itu, saya nggak lagi diperbolehkan membolak-balik buku ensiklopedia Papi. Mami memutuskan kalau saya harus diberi bacaan yang lebih sesuai umur, yang tentu saja membuat saya merasa nggak puas. Bagi saya, dongeng Si Kancil itu membosankan dan nggak menarik kayak ensiklopedia yang menjelaskan secara mendetail tentang lapisan-lapisan cincin Saturnus.
Tapi rupanya Papi punya pendapat berbeda. Gara-gara pertanyaan saya yang nyeleneh itu, Papi kayaknya yakin banget kalau anak semata wayangnya ini bukan hanya manusia yang berpikir, tapi juga jenius. Salah satu memori pertama saya adalah mengikuti tes IQ di sebuah ruangan yang isinya boneka-boneka raksasa dan wangi Stella jeruk, aroma yang sampai sekarang menjadi favorit saya. Saya ingat banget kalau waktu itu saya mengerjakan tes tersebut layaknya main puzzle, dan setelah tesnya selesai, saya tantrum lagi.
Yang terjadi setelah itu saya nggak terlalu ingat, tapi saya masih ingat betul hasil tes IQ pertama saya. 145. Pihak yang memberi saya tes bahkan sempat menyarankan agar saya didaftarkan masuk Mensa, tapi Mami menolak. Mami ingin saya hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya.
Intinya, seandainya Mami nggak bersikeras agar saya hidup normal, saya mungkin nggak akan jadi remaja medioker kayak sekarang.
Namun, usaha Papi dalam membuat saya menjadi seorang anak yang spesial nggak berhenti di situ saja. Di usia yang baru menginjak empat tahun, Papi langsung memasukkan saya ke SD meski seharusnya saya masih TK. Saya menduga Papi ingin saya menjadi kayak anak-anak jenius di TV yang sudah lulus SMA di usia sebelas tahun dan jadi profesor di usia enam belas tahun. Yang berarti, sekarang seharusnya saya sudah menjadi guru besar UI. Sayangnya, lagi-lagi hal itu nggak terjadi, gara-gara saya tantrum besar di hari pertama saya sekolah. Saya ingat betul, di usia segitu saya takut ditinggal sendiri, apalagi teman-teman sekelas saya sudah besar-besar dan semuanya sudah bisa kencing di kamar mandi.
Jika kesempatan pertama saya menjadi orang yang ternama disabotase oleh Mami, maka kesempatan kedua saya disabotase oleh diri saya sendiri.
Herannya, Papi masih nggak menyerah dalam berusaha menjadikan saya "manusia". Waktu saya SD, karena saya menganggap perkalian dan pembagian terlalu gampang, saya diikutkan les sana-sini di mana saya sudah belajar aljabar tingkat SMP. Saya ikut olimpiade tingkat SD di sana-sini, sampai saya bahkan memenangkan medali emas OSN tingkat SD, mengalahkan anak-anak lain yang setahun dua tahun di atas saya, waktu kelas 4. Waktu kelas 5, saya sudah bisa bikin robot sendiri, yang sekarang masih dipajang di lemari kaca tinggi ruang tamu beserta dengan piala-piala dan piagam yang saya peroleh selama SD. Bahkan sampai sekarang, kalau ada yang bertamu ke rumah, Papi masih suka membangga-banggakan prestasi saya.
Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya saat itu saya nyaris jadi "manusia". Sayangnya, nggak lama kemudian saya masuk SMP.
Waktu itu, seakan-akan nggak belajar dari pengalaman, saya dimasukkan di kelas akselerasi. Agaknya Papi masih nggak menyerah dalam menjadikan saya seorang jenius ternama, atau minimal lebih pintar dari anak lain seumuran saya. Memang nggak sebombastis menjadi penemu mobil terbang di usia 16 tahun, tapi tetap saja saya akan tetap menjadi orang ternama yang terekspos media. Katanya, biasanya maba termuda di suatu angkatan akan dipanggil ke depan oleh rektor. Kalau nama saya dipanggil rektor di depan ribuan maba karena saya bisa masuk FKUI atau STEI ITB di usia 16 tahun, saya pastilah akan jumawa setengah mati.
Ironisnya, meski saya sedari dini diajari untuk jadi manusia berpikir, di saat itulah saya malah benar-benar berpikir untuk yang pertama kalinya. Saya masih ingat banget pemikiran pertama saya, yang terjadi waktu saya karantina OSN tingkat provinsi.
Sambil melihat rumus-rumus Fisika kelas sembilan yang ada di atas meja, saya berpikir, anjirlah, saya nggak suka Fisika. Dan nggak cuma Fisika—saya nggak suka Matematika, Biologi, dan robotik, ketiganya hal-hal yang menghantarkan saya dalam jalan menjadi "manusia" sejauh ini. Saat itu, saya berusaha membayangkan masa depan saya setelah ikut OSN, tapi bayangan saya paling mentok ya jadi mahasiswa termuda yang dipanggil rektor ke depan. Setelah itu, segala sesuatunya kabur.
Ironisnya, dengan penolakan saya terhadap jalan yang telah diberikan hidup agar saya menjadi "manusia", saya pertama kali merasa seperti manusia yang sesungguhnya.
Saya agak ragu untuk memberitahu Papi kalau saya nggak mau lagi ikut-ikutan olimpiade atau belajar di kelas akselerasi. Tapi, di luar dugaan saya, Papi mengiyakan. Saya masih ingat banget senyum Papi waktu itu—jauh lebih lebar, bahkan jauh lebih tulus dibandingkan senyum yang Papi berikan ke saya tiap kali saya menang lomba dulu. "Papi bangga sama kamu, Nak," ujarnya sambil menepuk bahu saya. "Kenapa nggak kayak gini dari dulu? Papi senang kamu akhirnya berani menentukan pilihan hidup kamu, berdasarkan pemikiran kamu sendiri." Sesudah itu, saya dibelikan es krim sekotak. Saya masih ingat banget, rasanya mint chocolate, yang sampai sekarang jadi rasa es krim favorit saya. (Bodo amat kalau kata orang rasanya kayak Promag.)
Sayangnya, lewat tindakan menjadi manusia tadi, saya malah gagal menjadi "manusia". "Manusia", maksud saya, adalah seseorang yang meninggalkan jejak berarti, yang nggak cuma numpang hidup dan bernapas di bumi. Sekarang saya seharusnya sudah masuk daftar 30 Under 30-nya Forbes atau minimal jadi mahasiswa termuda ITB, tapi nyatanya saya hanya seorang remaja medioker yang minggu depan harus kembali masuk SMA layaknya remaja-remaja lainnya. Yang hidupnya isinya cuma bangun, sekolah, pulang, main game, ngerjain PR, lalu tidur. Lalu, setelah ini apa? Kuliah (tapi nggak dipanggil ke depan sama rektor), jadi pekerja kantoran, menikah, punya anak, menua, dan mati. Yang ingat saya paling cuma keluarga saya.
Lantas, untuk apa saya ada?
Gara-gara pertanyaan tersebut muncul di benak saya waktu saya BAB tadi, saya tiba-tiba jadi ingat kutipan René Descartes tentang bagaimana kita ada karena kita berpikir, tapi yang ada saya malah tambah bingung. Dulu, waktu SMP, saya berpikir untuk yang pertama kalinya, dan gara-gara pemikiran saya, saya ada dan tiada di waktu bersamaan. Di satu sisi, berpikir menghantarkan saya ke jalur hidup saya sekarang, membuat saya "ada". Tapi, di sisi lain, pikiran saya jugalah yang membuat keberadaan saya sekarang nggak berarti.
Lalu, saya mengintip sebentar ke bukunya Remy Sylado yang terletak di pangkuan saya. Ndilalah, di halaman yang terbuka, tertera salah satu puisi mbeling ikonik beliau, judulnya: Teks atas Descartes.
Orang Perancis berpikir maka mereka ada. Orang Indonesia tidak berpikir, namun terus ada.
Berangkat dari puisi di atas, layaknya Newton yang tersandung apel dan menemukan teori gravitasi, saya memperoleh pencerahan. Lalu, kumpulan esai ini pun lahir.
***
Kalian mungkin bertanya-tanya, Ren, hubungannya puisi Remy Sylado sama kumpulan esai ini emang apaan? Kalau itu yang kalian tanyakan, saya sudah punya jawabannya.
Kalau dipikir-pikir, benar juga apa kata .Remy Sylado. Orang Indonesia—apalagi, menurut pengamatan saya, yang lahir setelah tahun 2005—tidak berpikir, namun terus ada. Contohnya banyak. Ethan, misalnya, anak kelas 10-3 yang gonta-ganti pacar sesering dan segampang ganti lockscreen ponsel. Saya nggak ngerti apa yang dia cari dari gonta-ganti cewek, dan kenapa dia enteng banget melakukannya. Mantan terakhirnya, Ramona, cuma pacaran tiga bulan dengannya. Untuk seorang Ethan, itu rekor. Nggak jarang dia pacaran cuma dua-tiga minggu. Belakangan ini Ramona jadi sering ngegalau di Insta-story, Saya sedikit kasihan padanya, tapi saya juga bertanya-tanya kenapa dia masih mau sama Ethan meski track record-nya sejelek itu. Saya yakin, di tahun ajaran baru minggu depan, Ethan bakal gandeng cewek lagi.
Atau, kalau mau contoh yang lebih konkret, si Marco, teman sekelas saya waktu kelas 10. Marco, mentang-mentang bisa (dan, harus saya akui, memang jago), main gitar, hobi banget menggelar konser dadakan di kelas waktu jam istirahat. Pernah, suatu hari ia membuat konser kecil-kecilnya menjadi konser besar-besaran. Marco dan konco-konconya mengatur meja-meja depan layaknya panggung, lalu ia dan teman-temannya mencuri sound system dari ruang serbaguna untuk disambung ke gitarnya Marco. Marco dan teman-temannya, diiringi dengan cajon yang juga dicolong dari aula, menyanyikan lagu-lagu campursari khas kondangan kabupaten kayak Rungkad atau Kartonyono Medot Janji. (Kalau kamu tanya dia apakah dia tahu Kartonyono di mana, dia nggak bakal bisa jawab.) Eh, nggak tahunya, waktu ia memanggil kami dengan ajakan khasnya, "ji ro lu pat, sek!", ia terjatuh dari kursi, pantatnya kena lantai duluan. Kakinya patah. Ada sebulan dia jalan pincang. Semuanya demi mencari validasi.
Sebulan kemudian, begitu kakinya sudah nggak lagi digips, Marco melakukan hal yang sama.
Mengingat kedua contoh di atas, ditambah dengan banyaknya contoh-contoh lain yang nunjukkin betapa nggak jalannya otak anak-anak seusia saya, saya seakan memperoleh pencerahan. zaman sekarang sudah nggak ada lagi penulis ternama yang membuat esai. Dulu, banyak sekali penulis dan filsuf ternama yang mengamati masyarakat, memikirkannya dalam-dalam, dan menuliskannya dalam sekumpulan esai. Descartes sendiri bikin banyak buku dari pemikirannya, yang beberapa saya baca sekilas di perpustakaan pribadinya Papi. George Orwell bikin buku tentang pengalamannya melarat di London dan Paris dan orang-orang yang ia temui selama hidup susah. Murakami bikin buku cuma buat ngejelasin kenapa dia suka berlari. Atau, nggak usah jauh-jauh, deh—Seno Gumira Ajidarma, salah satu penulis kesukaan saya, bikin esai-esai nyelekit tentang kehidupan urban Jakarta. Si Parasit Lajang-nya Ayu Utami saja sampai ada sekuelnya. Sekarang?
Intinya, saya teringat lagi akan sosok yang menjadi asal-mula nama saya. René Descartes, bapak filsafat modern. Jika Papi memberi saya nama itu supaya saya menjadi manusia yang berpikir, kenapa nggak sekalian saja saya turuti jalan hidup yang sudah ditentukan oleh nama saya dan jadi filsuf sekalian? Dulu, banyak sekali penulis dan filsuf ternama yang mengamati masyarakat, memikirkannya dalam-dalam, dan menuliskannya dalam sekumpulan esai. Descartes sendiri bikin banyak buku dari pemikirannya, yang beberapa saya baca sekilas di perpustakaan pribadinya Papi. George Orwell bikin buku tentang pengalamannya melarat di London dan Paris dan orang-orang yang ia temui selama hidup susah. Murakami bikin buku cuma buat ngejelasin kenapa dia suka berlari. Atau, nggak usah jauh-jauh, deh—Seno Gumira Ajidarma, salah satu penulis kesukaan saya, bikin esai-esai nyelekit tentang kehidupan urban Jakarta.
Tapi, sejauh ini, belum pernah ada filsuf ternama dari generasi saya. Yang membuat saya teringat pada sosok René Descartes, yang namanya Papi pinjam untuk jadi nama saya, dan saat itulah pencerahan datang. Kalau bukan saya yang meneliti mereka, siapa lagi? Kenapa saya nggak sekalian saja menjadikan nama saya doa, dan nggak hanya menjadi manusia yang berpikir, tapi juga menjadi filsuf ternama abad ini?
Berangkat dari situlah, saya memperoleh pencerahan: begitu saya masuk sekolah nanti, saya akan mengamati anak-anak di sekolah saya, dan segala tindak tanduk mereka akan saya abadikan dalam esai-esai di buku ini. Mahasiswa di masa depan akan menjadikan tulisan saya bahan skripsi. Generasi yang akan datang akan membaca karya saya dan bertanya-tanya kenapa generasi saya begitu aneh. Saya akan memperoleh Nobel Sastra, atau minimal Kusala Sastra Khatulistiwa. Orang-orang di masa depan akan ingat akan nama René Hartanto.
"KO??" di luar kamar mandi, gebrakan pintu menghancurkan momen bahagia saya. "BERAKNYA MASIH BERAPA MENIT LAGI?!"
"BENTAR!" balas saya, membalasnya dengan ikutan berteriak.
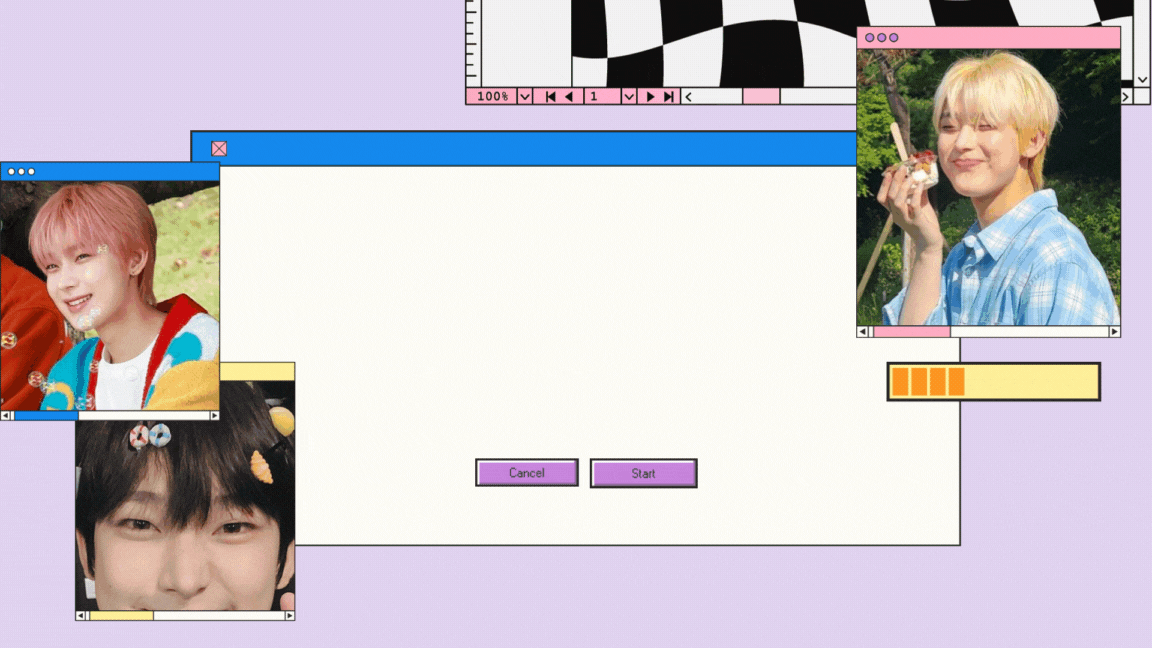
editor's note; iya, rene bikin prakata aja sampe 2000-an kata. dan iya, dia anaknya emang rada nyebelin. ̶m̶e̶n̶u̶r̶u̶t̶ ̶k̶a̶l̶i̶a̶n̶,̶ ̶y̶a̶n̶g̶ ̶g̶a̶n̶g̶g̶u̶i̶n̶ ̶d̶i̶a̶ ̶b̶a̶b̶ ̶s̶i̶a̶p̶a̶?̶ ̶hehe.
mengingat cerita ini bentukannya emang esai, jadi emang banyak narasinya ahahahaha. kalian ngerasa bosen nggak kalo baca banyak narasi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top