- • The Luminosity • -
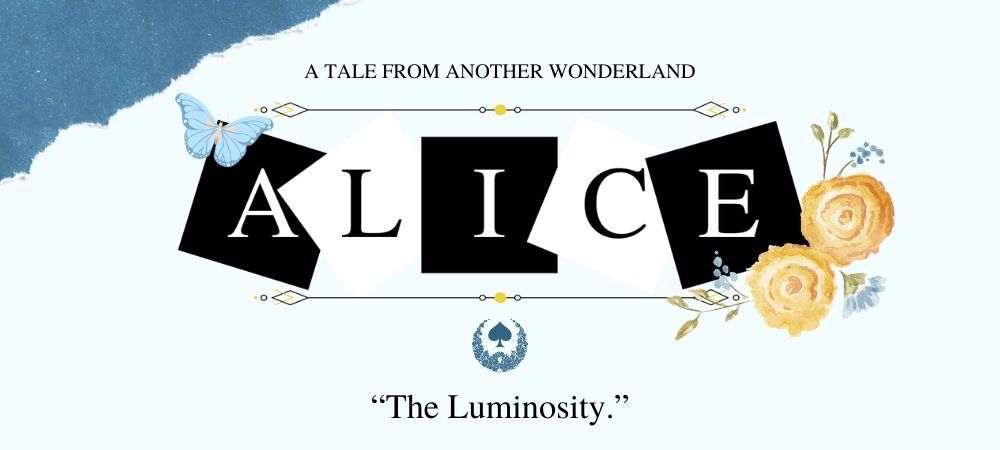
Malam itu, sebelum perayaan tahun baru Dunia Atas dimulai, pintu tinggi dengan lambang kelinci kecil yang digurat di permukaannya diketuk tiga kali. Pelakunya adalah seorang pria berpostur tinggi tegap yang mengenakan kemeja putih sambil menyampirkan jas hitamnya pada bahu kiri. Ujung sepatunya yang mengilap tak henti-henti menciptakan ketukan kecil di atas lantai. Agak gusar dia melakukan gerakan mengusap pada rambut putihnya yang panjang dan berikatkan pita hitam.
Orang-orang yang berlalu lalang bisa salah mengiranya sedang gugup mengetuk pintu kekasih. Padahal yang dia datangi sekarang adalah ruang kerja rekannya yang meninggalkan agenda makan malam untuk yang ketiga kalinya dalam sepekan.
Ada sekotak kue di tangan kanannya. Dia dapatkan kue itu dari para dayang kurcaci di dapur. Katanya untuk mengganti makan malam si rekan.
Tepat setelah menghela napas, gagang pintu mulai berderak. Akhirnya pintu itu dibuka dan muncullah pemandangan agung berupa sesosok wanita anggun berpakaian serba hijau di ambang pintu.
Melihat ada tamu tak terduga di jam malam, kelopak mata wanita itu melebar cepat.
"Tuan Caleb?"
"Malam, Isabel." Pria itu, Caleb, menganggukkan kepalanya sedikit sebagai gestur sopan santun selama tangannya penuh. "Maaf mengganggu waktumu malam-malam, tapi aku harus bertemu dengannya."
"Itu ...," Isabel menoleh ke belakang sejenak, lalu kembali menghadap ke depan sampai sedikit membungkuk guna merendahkan suara, "bukannya saya melarang, tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana cara membawa beliau masuk."
"Dia di luar?"
"Tidak jauh dari jendela, saya jamin."
Caleb mengangkat alis, menurunkan kotak kue. "Ada sesuatu yang terjadi?"
"Ini tidak seburuk yang Tuan bayangkan. Maksud saya, surat dari Mad Hatter," jawab Isabel. "Saya menemukannya terbuka di atas meja. Tidak terbuka sepenuhnya, tapi saya yakin beliau keluar setelah membaca sedikit suratnya."
Caleb mengerutkan keningnya. Surat lagi?
"Omong-omong, silakan masuk, Tuan. Akan saya pikirkan bagaimana caranya memanggil Tuan Ruviane. Mari, saya bawakan kotak itu ke mejanya."
Caleb menyerahkan kotak kue itu pada Isabel. Senyumnya terbit dan dia melangkah masuk seraya mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan.
Benar apa yang dikatakan Isabel, anak itu tidak ada di sudut mana pun. Ini tidak jauh berbeda dari biasanya karena sejak dulu pun sama-anak itu selalu menghindari orang-orang begitu mendapatkan sepucuk surat penugasan dari Mad Hatter. Caleb menyebut kebiasaannya itu sebagai Proses Pendinginan Kepala Ala Warden Terbungsu.
Bukan bungsu secara harfiah, tentu saja. Ada artian khusus bagi para Warden untuk kata yang satu itu.
"Hei, Ruv," panggilnya seraya mengempaskan diri di atas sofa. "Kemari dan lihatlah apa yang kubawa. Ini makanan kesukaanmu. Kue wortel yang dibuat dengan potongan wortel segar tanpa ada campuran bahan apa pun, lalu dihias dengan potongan wortel lainnya. Bukankah ini menggiurkan, sobat?"
Kue adalah sebutan yang cukup berlebihan. Padahal sejatinya yang ada di dalam kotak itu hanyalah wortel biasa.
Isabel berjalan mendekat dengan sebuah nampan dan secangkir teh di atasnya. Diam-diam dia mendengkus sebab tahu betul arti ucapan Caleb. Lucu rasanya mendengar Caleb berkata demikian. Mirip seperti seorang paman sedang membujuk keponakannya yang masih remaja labil.
Sembari menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi geli terang-terangan, Isabel meletakkan cangkir teh di atas meja, menyambut Caleb layaknya tamu pada umumnya.
Belum sempat Isabel berbalik undur diri, angin malam tiba-tiba berembus kencang dan meniup selendang hijaunya dengan lembut. Begitu piring cangkir berdenting saat bertemu permukaan meja, dia menarik selendangnya merapat kemudian berdiri tegap. Selanjutnya Isabel berbalik, melangkah mundur, dan sedikit membungkukkan tubuhnya sebelum tak sengaja beradu tatap dengan netra rubi yang berkilat di bawah sinar rembulan.
Caleb tidak melakukan hal serupa. Dia tetap duduk santai di tempatnya. Memindai pemuda yang malas-malasan bersandar pada bingkai jendela dari kepala sampai kaki.
"Kenapa kau di sini?"
"Hanya untuk mengatakan jangan meninggalkan makan malam lagi, Ruv." Caleb menegur. "Anak remaja butuh banyak nutrisi untuk tumbuh dan berkembang."
Si empunya mata semerah batu rubi diam bergeming di bingkai jendela. Tatapannya tidak lepas dari kotak kue yang dibawa Isabel ke atas meja kerjanya. "Aku tidak seremaja yang kaukira."
"Apa pun itu yang namanya kelaparan bisa mengakibatkan kematian."
Ruviane mengangkat alis tanpa minat. "Kau mengatakannya seolah-olah lupa aku pernah mati sebelumnya."
"Oh, astaga. Lihatlah suasana hatimu sekarang. Buruk sekali. Bahkan diajak bergurau sedikit pun tidak bisa." Caleb mengerucutkan bibir, mengangkat cangkir, kemudian mengangguk sopan pada Isabel sebelum mulai menyesap isinya. "Isabel bilang padaku kau begini karena surat dari Mad Hatter."
Ruviane menurunkan alis. Berusaha keras untuk tidak menunjukkan ekspresi terganggu. Sebagai gantinya, dia menatap kotak kue pemberian Caleb sebagai pengalihan fokus.
Desainnya norak. "Tidak juga. Aku bahkan belum membaca seisi suratnya sampai habis," elaknya.
"Bukankah justru di sana penyebabnya?" Caleb melirik. "Mad Hatter memang gila setiap saat. Saranku, jangan terlalu keras kepala setiap kali dia menggunakan kegilaannya. Bisa-bisa kau mati akibat tertekan."
Ruangan lengang dalam detik yang panjang. Isabel yang berdiri di tepi ruangan menurunkan pandangan begitu merasakan hawa ganjil dari cara Caleb menatap tuannya, yang masih terpaku pada kotak kue dengan tatapan tak bercahaya bak ikan mati.
Betapa hening yang sama sekali tidak menyenangkan.
"Ruviane," suara Caleb mendadak serius, "kau tidak berniat seperti itu, bukan?"
Ruviane berkedip dua kali, dan entah bagaimana itu membuat cahaya di matanya kembali. Seolah baru berhasil diseret ke daratan, dia menarik napas dan mengembuskannya perlahan sampai bahunya melemas.
"Tidak, setidaknya untuk sekarang," katanya.
Kedua alis Caleb menukik. Itu bukan jenis jawaban yang ingin dia dengar.
Namun, Ruviane yang tak kunjung membuka mulut juga bukan opsi yang menyenangkan.
"Baiklah," pria itu menenggak tehnya sampai tandas. "Aku akan kembali ke ruanganku. Jangan lupa makan, Ruviane. Mereka menyisakan makan malam untukmu andai kau tidak tertarik dengan kue itu. Kalau kau ingin, pergilah ke dapur. Jangan sampai kau mati kelaparan. Itu konyol."
Ah, dia bisa menjadi sangat banyak bicara hanya ketika dia menghadapi makhluk sejenis Ruviane.
Caleb menunduk kecil pada wanita anggun di depannya. Dia izin pamit sebelum melangkahkan kakinya dengan ringan menuju pintu dan menahan Isabel untuk tetap diam di tempat. Aku bisa keluar sendiri. Kau diam saja di sini menjaga tuanmu, ujarnya lewat tatapan.
Tatkala punggung Caleb hilang di balik pintu, Isabel menghela napas. Kedua bahunya melemas seakan-akan bersikap sopan setiap ada tamu adalah hal yang paling melelahkan. Masih dengan sopan santun walaupun tidak sekaku sebelumnya, dia tatap tuannya yang kini sedang duduk malas-malasan di kursi kerja.
Wanita itu lantas menyusun cangkir dan teko di atas nampan.
"Hari ini adalah hari perayaan terbesar di dunia Atas. Tidakkah Anda ingin berkunjung ke sana, Tuan? Berbelanja kue untuk para kelinci, mungkin? Saya akan senang bila Anda mendinginkan kepala dengan cara yang lebih positif dibandingkan dengan berdiam diri di atas gedung."
Ruviane melirik. Pura-pura tidak mendengar kalimat terakhir itu. "Untuk apa aku ke sana?"
"Sebagian besar penduduk Negeri Ajaib mengerti bahwa itu adalah kebiasaan Anda. Begitu melihat Anda tidak melakukan hal serupa seperti tahun-tahun sebelumnya, bukankah itu menjadi sebuah pertanyaan?"
"Aku sibuk. Lagipula tidak ada yang ingin aku lihat di sana."
"Anda yakin?"
Kerut halus muncul di kening si pemuda beriris rubi. Dia lebih curiga dengan maksud dan tujuan wanita di depannya ini. "Apa yang sebenarnya ingin kaukatakan, Isabel?"
Isabel diam di tempat dengan nampan berisi cangkir di tangan. Penuh gemulai dan percaya diri menyelipkan rambutnya ke balik daun telinga. Tidak tampak gentar ataupun ragu untuk mengatakan apa pun bahkan ketika suasana hati tuannya sedang tidak jelas.
"Cucu keempat Mandalyn Sonata berulang tahun tengah malam ini," ujar Isabel tenang. "Bukankah dia orangnya—Nona Alice yang berikutnya?"
Ruviane menghela napas. "Kau tahu sendiri dia tinggal di Amerika. Yang ada di rumah besar itu hanya keluarga sepupu beserta neneknya. Tidak ada gunanya juga datang ke sana."
"Oh, Tuan. Inilah kenapa saya meminta Anda untuk membaca laporan dengan teliti." Isabel terkikik menang melihat ekspresi bingung Ruviane. "Esmephia Sonata berangkat ke Inggris dengan kakaknya malam ini. Mungkin besok Anda harus bertegur sapa dengannya."
Ketika wanita anggun itu berbalik untuk membawa nampan ke dapur, Ruviane dihantui oleh berbagai pertanyaan di atas kursinya. Dalam diam dia mengambil sepotong kue yang dibawakan Caleb, lantas mengunyahnya perlahan. Dalam sekejap saja dia tenggelam dalam pikiran yang tiba-tiba berkecamuk di dalam kepalanya.
Kenapa dia pindah?
- • -
Untuk pertama kalinya sejak beberapa jam tinggal di rumah besar itu, Esme menemukan ibunya. Masih secantik, sediam, dan secanggung yang dia ingat.
Mungkin ceritanya tentang dia melapor bahwa Peter dan pacarnya sudah sampai tahap berciuman terdengar lucu; seperti anak kecil mengadu pada orang tuanya. Padahal nyatanya sesi laporan itu berlangsung dengan super singkat dan tidak berkesan sama sekali. Karena yang Esme lakukan hanyalah mengirim video, lalu Clara meresponsnya dengan emoji tertawa.
Secanggung itu hubungan mereka walaupun tinggal seatap.
Kali ini Clara datang sendirian untuk menghadapnya di pintu kamar. Benar-benar sendiri tanpa membawa barang apa pun kecuali pakaian yang dikenakannya. Dalam hitungan detik yang panjang, mereka tenggelam dalam hening yang tidak mengenakkan.
Esme tahu ibunya bukan orang jahat, tetapi berhadapan seperti ini membuatnya merasa terintimidasi dan bahkan sama sekali tidak nyaman. Kepalanya memberi perintah, Balik kanan! Tutup pintu! Nahas hati kecilnya menampar alam bawah sadar untuk lebih sopan ke orang yang lebih tua. Lebih-lebih lagi kepada wanita yang sudah susah payah melahirkannya.
Namun, ini terlalu aneh bagi Esme.
Bukankah seharusnya seorang ibu dan anak saling tersenyum cerah ketika sudah lama tidak bertukar kata?
"Padahal hanya berpisah beberapa jam," mulai Clara, "tapi kenapa rasanya anak Ibu yang satu ini mendadak lebih dewasa, ya?"
Esme menatap ibunya. Dalam hati menjawab, Itu karena sebenarnya kita berpisah bertahun-tahun lamanya, bahkan saat sedang bersebelahan sekalipun. Dia tidak bisa mengatakannya terang-terangan. Ada banyak hal yang harus dia tanggapi dengan dewasa, dan hubungannya dengan ibu kandung sendiri adalah salah satunya.
"Mungkin karena 'beberapa jam' itu memakan waktu satu tahun? Ibu tahu, maksudku semalam masih akhir Desember dan sekarang sudah masuk ke Januari yang baru." Esme mengedikkan bahunya, berusaha bercanda.
Clara memintal senyum geli. Air wajahnya berubah menjadi lebih cerah padahal matahari sudah terbenam separuhnya.
"Oma memanggil," katanya. "Waktunya hadiah tahun baru."
Bagi Esme, keluarga Sonata memiliki banyak agenda hadiah. Oh, dia tidak keberatan, tentu saja. Siapa yang tidak suka hadiah?
"Apa itu alasan kenapa di bawah sana lebih ramai?" Esme bertanya.
"Ibu selalu bilang telingamu bagus, bukan?" Clara tergelak. "Kalau tidak salah Feodora membawa temannya ke sini. Sedikit lebih muda dibanding Peter, tapi sebaya dengan Feodora. Tadi mereka sempat canggung, tapi sepertinya mereka sudah berteman sekarang. Nah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Elena bilang setiap tahunnya memang begitu. Anak itu tinggal bersama paman dan bibinya, tapi sering ditinggal pergi. Bukan ide yang buruk untuk menjadikannya teman baru, bukan?"
Esme angkat bahu. "Tergantung bagaimana orangnya."
"Ibu akan senang kalau kau membuat teman baru."
"Ya, tentu. Aku juga."
Sebelum Clara menginjak anak tangga untuk bergabung di lantai dasar, putri bungsunya bertanya, "Apa Ibu masih akan bekerja? Maksudku, walaupun sudah pindah rumah?"
Wanita itu menoleh, menatap Esme lekat-lekat. "Apa itu jenis pertanyaan yang harus Ibu jawab?"
Esme membuang pandangan. Sudah menduga respons ibunya akan seperti itu. Inilah waktunya dia memuntahkan semua yang selama ini bersarang di kepalanya.
"Padahal Ibu bisa lebih bersantai di sini. Desain baju Ibu bisa dijadikan kesenangan pribadi saja, atau jualan kecil-kecilan. Bahkan kalaupun Ibu membuat baju, tidak akan ada atasan menjengkelkan yang mengekang Ibu. Ibu bisa bekerja sama dengan Bibi Elena ...."
"Elena tidak seluang yang kaubayangkan. Dia ikut kursus memasak, kau tahu?" Clara berkacak pinggang. "Esme, apa kau melarang Ibu bekerja?"
"Yah, melarang itu kata-kata yang kuat. Sebenarnya aku berpikir terkadang Ibu harus lebih sering memikirkan yang ada di rumah."
"Apa maksudmu?" Clara mengernyit, tertawa kecil nan canggung. "Tentu saja Ibu memikirkan kalian. Peter memang sudah mulai bekerja, tapi masih ada Esme yang harus Ibu perhatikan, bukan? Sebentar lagi masa-masa kuliah. Ibu tidak ingin merepotkan ayahmu lebih jauh."
"Kalau alasannya begitu, bukankah itu artinya Ibu tidak percaya Ayah? Aku bisa mengejar beasiswa atau kerja paruh waktu kalau memang masalahnya ada pada biaya. Saling repot dan merepotkan itu bukannya berarti pertanda bagus? Sebuah keluarga harus saling begitu, bukan? Ibu tahu betul yang kumaksud bukan soal uang—"
"Esmephia."
Ah, sial. Intonasinya.
Esme menutup mulutnya rapat-rapat tanpa mengalihkan pandangan. Dia menolak untuk menurunkan pandangannya sedikit saja. Tidak peduli bahkan ketika perbuatannya dianggap kurang ajar. Tatapan tajam Clara sama sekali tidak membuatnya goyah.
"Ibu bekerja karena Ibu suka."
Tapi bukan itu yang kusuka.
"Ibu bukannya tidak percaya dengan Ayah, Ibu hanya ingin membantunya meringankan beban."
Beban? Apa bebannya? Aku?
"Karena itu Ibu ingin—"
Ck.
"Terserah." Esme menyela. Geram sendiri. "Memang seharusnya tidak usah dipaksakan mengobrol kalau memang ujungnya begini lagi."
Esme membuang wajah. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Buru-buru dia melewati Clara untuk turun lebih dulu. Ada beban luar biasa berat yang timbul menggelayuti hatinya-perasaan yang bernama serba salah dan dongkol.
Baginya, situasi ini tidak ada bedanya dengan mereka tinggal di Brooklyn ataupun London.
Esme hanya tidak tahu, dan dia tidak akan pernah ingin tahu seberapa besar terlukanya Clara mendengar gumaman lirih itu.
Sebutlah dia egois, tetapi, hei, bukankah memang begitu seharusnya?
Gadis remaja sepertinya, yang selama ini tutup mulut tentang betapa kesepian dirinya, hari ini mengutarakan perasaan itu bagaikan sesosok anak kecil merengek ingin permen-bukankah memang begitu seharusnya?
Tidakkah Esme diizinkan untuk egois sekali saja? Atau tanpa sadar dia sudah terlalu sering egois sampai kesempatannya habis?
Memangnya harus sampai kapan aku harus bilang 'aku bisa sendiri tanpa Ibu'?
Esme menarik napas panjang begitu dirasa keningnya berkerut. Tangannya bergerak mengusap kening sampai kerutan di sana sirna. Ditolehkan kepalanya ke arah bingkai foto yang terpajang di dinding sepanjang tangga, dan samar-samar dia temukan pantulan iris safirnya yang tampak padam di sana.
Mirip ikan mati.
"Aku benci orang dewasa," gumamnya.
"Yah, aku juga."
Esme berkedip, seketika kembali ke realita dan mendadak sadar bahwa dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Lantas dia menoleh, bersibobrok dengan seorang pemuda yang berdiri santai di bawah anak tangga. Bajunya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang dihantam musim dingin pada umumnya, rambutnya cokelat cerah, dan matanya pun sewarna kacang hazel. Benar-benar perawakan yang biasa saja.
Yang tidak biasa bagi Esme adalah keberadaan orang itu di dalam rumah Sonata.
"Mereka agak menyebalkan. Jika kita berbuat lain dari ekspektasi sedikit saja, secara tidak langsung kita menciptakan masalah baru yang lebih runyam. Karena terkadang kita menurut, terkadang kita membangkang. Mau bagaimana lagi, bukan? Usia remaja memang sedang labil-labilnya."
Esme mengangkat alis. Bertanya-tanya siapa orang ini tanpa suara.
"Oh, yang itu lucu." Pemuda itu maju selangkah, menunjuk salah satu objek di foto yang paling besar dan paling ramai. Objeknya adalah sosok gadis kecil manis yang cemberut dalam balutan mantel biru-putih cantik. Selaras dengan salju dan warna matanya. "Biar kutebak, kau yang ini?"
Tidak ingin menunjukkan ketidaksopanan saat pertama kali bertemu, Esme mengikuti arah telunjuknya berhenti. Sedikit mengapresiasi orang ini karena tahu yang mana sosoknya saat kecil. Padahal rata-rata anggota keluarga Sonata berambut pirang dan rata-rata memiliki mata safir yang sama. Wajahnya dengan Feodora saat kecil juga mirip.
"Iya, itu aku."
Pemuda itu mendengkus puas. Kembali mundur tanpa langsung pergi. "Penampilan Feodora pasti lebih semrawut, jadi bisa disimpulkan dengan mudah kalau yang anggun itu kau."
"Itu pujian, kurasa?"
"Tentu saja."
Esme bersedekap, bersandar pada bagian dinding yang kosong dari pigura foto. "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya."
"Aku juga belum pernah melihatmu," balas si pemuda. "Kau punya hubungan khusus dengan Feodora? Saudara tiri? Adik yang jarang dipublikasikan? Kembaran? Atau—"
"Sepupu," potong Esme tanpa permisi. "Aku sepupunya. Ayahnya bersaudara dengan ibuku."
"Aha. Itulah kenapa kalian mirip-mirip." Pemuda itu memberikan respons berupa anggukan mafhum. "Dari mana asalmu? Kau sedang berlibur ke sini atau bagaimana?"
Sebenarnya, Esme tidak punya kewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan itu, tetapi siapa sangka bahwa mengobrol dengan orang baru mampu sedikit mengobati perasaan atas masalah yang sebelum ini menimpanya?
"Aku-"
"Demi Tuhan! Kucari kau dari taman sampai ke dapur, tapi ternyata kau malah—oh."
Feodora, yang tadinya berjalan dengan langkah lebar-lebar dan semburat dialog penuh emosi, mendadak terdiam begitu disuguhi sebuah pemandangan baru di depannya. Bergantian dia tatap antara si pemuda jangkung dengan sepupunya yang berdiri di anak tangga. Kedua tangannya saling mengatup dan dia mengangkatnya sampai setinggi kepala. Dia tampak sedang merutuki kebodohannya karena telah muncul pada waktu yang salah.
"Maaf. Aku mengganggu. Silakan lan—"
"Hei, hei, tahan di sana," si pemuda menegur. Buru-buru menarik buntalan rambut Feodora sebelum gadis itu pergi dan menyebarkan rumor yang macam-macam. "Aku tahu isi kepalamu. Hentikan itu."
Feodora cemberut. Cepolannya berantakan. "Aku hanya ingin semua orang tahu kau pedofil."
"Kurang ajar."
Esme mengernyit was-was. "Temanmu, Fe?"
"Lebih dari teman, kupikir?" Feodora bertopang dagu di udara. Masih dalam keadaan cepolannya ditahan. "Seingatku dulu kami memang satu sekolah, sih. Tapi apa, ya? Memangnya ada 'teman' yang rutin datang ke rumah hanya setiap pada tahun baru? Gelar sahabat rasanya juga terlalu suci. Dia belum pantas mendapatkannya. Oh! Sepertinya lebih pas kalau disebut sebagai Tamu Langganan Oma saja."
"Itu jahat." Pemuda itu berjengit, melepas genggamannya dari cepolan rambut Feodora untuk pura-pura terluka. "Kau tahu, gadis cantik? Tamu Langganan Oma ini sering membantu Nona Feodora mengerjakan tugas sekolah sejak sekolah menengah."
Feodora tertawa hambar, berjalan memimpin ke ruang tengah. "Dasar pembohong andal."
"Coba kautanyakan pada buku matematikamu, Fe. Dia saksi bisu kenangan sekolah kita."
"Sudah kubakar setelah pulang dari upacara kelulusan. Omong-omong, kau ingin piza, Esme? Masih ada beberapa potong di meja sofa. Laki-laki pedofil itu membawanya ke sini."
Pemuda itu berdecak lidah. "Apa semua anggota keluarga Sonata bermulut tajam atau kau saja?"
"Oh, ini menandakan betapa tingginya harga diri kami."
Esme mendengkus. Diam-diam setuju dengan ucapan sepupunya. Akhirnya dia ikuti Feodora dan temannya itu ke sofa ruang tengah. Namun, sepupunya itu dengan cepat balik kanan dan berderap ke lantai atas sambil mengatakan, Ada yang tertinggal! Kalian duluan saja!
Masih dalam kondisi penasaran, gadis itu duduk pada sofa yang berbeda dan berkata, "Baik, Tamu Langganan Oma. Siapa namamu, kalau aku boleh tahu?"
Pemuda itu tersenyum, memeluk bantal sofa dengan nyaman seolah dia tuan rumahnya di sana. "Oliver."
Esme berkedip. Melirik matanya yang justru cokelat kemerahan. Alam bawah sadar menuntun mulutnya untuk mengatakan, "Matamu bilang namamu Hazel."
"Oh, aku lebih percaya kata akta kelahiranku dibanding kata mataku."
Esme mendengkus. Permainan katanya menarik dan menyebalkan di saat yang sama. "Nama belakang?"
"Theoderick." Pemuda itu mengangkat bahu. "Tenang, Sonata Kecil. Sampai kau bertanya bagaimana bentuk sidik jariku pun aku berani jamin kalau aku bukan orang jahat, apalagi pedofil."
Alis Esme menukik tajam. Air wajahnya terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak begitu menyukai panggilan sok akrab itu. Padahal tadinya dia ingin memuji betapa uniknya nama yang dia miliki.
"Kuhargai itu, tapi akan lebih baik kalau kau tidak memanggilku Sonata Kecil," Esme meraih potongan piza di atas meja, "karena Leonard lebih kecil dariku, asal kau tahu."
"Oh, ya. Aku tahu itu." Oliver mengangkat satu alisnya. "Kalau begitu Nona Sonata saja, bagaimana?"
Seseorang tolong ingatkan Esme bahwa menjadi tuan rumah haruslah bersikap sopan selama tamunya belum kurang ajar. Level tamu seperti Oliver belum mencapai kekurangajaran itu.
"Esme. Tidak lebih dan tidak kurang."
Oliver manggut-manggut. "Baiklah ...," katanya lambat-lambat. "Ketusnya tidak jauh berbeda denganmu seperti di awal tadi."
Salah satu alis Esme menukik sampai keningnya terasa ditarik. Kebingungan sesaat menyerangnya begitu Oliver berkata demikian. Ketika kepalanya mendongak ekstrem sampai surai pirangnya meluruh ke punggung, dia menemukan Peter lewat di belakang kepalanya dengan dua kaleng soda yang masih terbungkus rapat dan satu kaleng yang tampaknya sedang dia konsumsi sendiri. Sekarang barulah Esme paham kepada siapa pernyataan Oliver ditujukan.
Peter kemudian duduk di sebelah adiknya. Menyodorkan sekaleng minuman bersoda itu padanya, kemudian melempar yang satu lagi ke arah Oliver.
"Banyak yang bilang begitu. Mungkin genetika," jawab Peter sekenanya. Lalu dia menatap adiknya yang sedang membolak-balikkan kaleng soda. "Oma dalam perjalanan kemari. Ingin main tebak-tebakan tahun ini kau mendapat apa?"
Esme mengumpulkan segenap tenaga ke ujung ibu jarinya, kemudian membuka kaleng itu dengan mudah. "Semoga bukan boneka."
Peter menyeringai, dengan santai menyenggol adiknya sebelum duduk bersandar dengan kekuatan yang membuat gadis itu nyaris melepas pegangannya dari kaleng.
Oliver membuka serta tutup kalengnya. Dengan tenang mengucapkan, "Kalian akur untuk hitungan kakak beradik."
Esme mengambil potongan piza lagi. Bergumam, "Kau hanya belum melihatnya."
"Hah?"
Lalu Feodora datang membawa sekotak mainan. Leonard menyusul di belakangnya, berjoget-joget ria dalam pakaian yang berbeda dari yang sebelumnya. Hanya lewat gerakan aneh nan menggembirakan itu, Esme dapat menebak agenda kencan cinta monyetnya berjalan dengan baik.
"Sambil menunggu para orang dewasa," cetus Feodora, "ayo kita main stacko!"
Esme payah dalam permainan itu.
Tadinya dia enggan bergabung, tetapi Peter memaksanya dan mengancam tidak akan mengajaknya jalan-jalan selama liburan awal tahun baru. Sebuah ancaman yang sudah jelas ampuh untuk gadis yang suka pergi keluar rumah.
Oliver ikut bergabung, tetapi setelah dua ronde permainan dia mundur dan memilih untuk menonton saja. Sekali-dua kali membantu Esme—yang lemah dalam permainan itu—meskipun gadis itu sudah terang-terangan mendesis tidak suka diganggu.
Oliver mengerucutkan bibirnya seraya menggeser bokongnya lebih dekat dengan gadis pirang itu. "Aku membantumu, lho," ucapnya.
Esme mendorong wajah rupawan itu menjauh. "Dan aku tidak ingin dibantu."
"Oh, ya? Sekarang coba kau tarik yang itu."
Gadis itu spontan berdecak lidah. Kakaknya tahu dia payah dalam permainan ini. Feodora dan adiknya tidak tahu fakta itu sebelumnya dan sekarang mereka semua tahu kelemahan Esme. Suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak ingin orang-orang—selain Oliver, mungkin—tahu bahwa sebelumnya dia adu mulut dengan ibunya sendiri. Meskipun sering menyebalkan, Peter terlalu peka dalam urusan ini, hingga terkadang Esme berdoa semoga kepekaan kakaknya sedikit dikurangi.
Kali ini, tanpa saling bertemu atau bahkan kenal sebelumnya, Oliver dengan senang hati membantunya. Seolah-olah tahu bahwa terlalu lama larut dalam kekalahan, walau itu permainan sekalipun, akan membuat suasana hatinya jauh lebih buruk dibanding ini.
"Kau tidak ingin mencobanya?" Oliver berbisik. Kemudian tersenyum tipis begitu Esme benar-benar menatapnya tepat di mata kali ini.
Tidak ada salahnya dicoba. Suara kecil di kepalanya memberitahu dan Esme tidak pernah meragukan apa kata suara itu.
Maka Esme mulai menarik balok mainan itu pelan-pelan, tanpa sadar menahan napasnya. Anatomi di balik rongga dadanya berdetak keras hanya untuk membuatnya tidak tenang. Balok mainan itu sedikit demi sedikit bergerak dan entah bagaimana pada akhirnya tertarik keluar dari tempatnya.
Feodora heboh sendiri dan Peter bertepuk tangan dengan kalem begitu Esme berhasil menarik balok pertamanya. Di tengah keramaian sesaat, gadis itu terperangah. Terkejut sendiri melihat hasil perbuatannya. Begitu dia menoleh ke samping, dia temukan Oliver sedang tak kuasa menahan dengkus geli. Penyebabnya adalah ekspresi cerah Esme terbit hanya karena berhasil menarik balok stacko.
"Kau sesenang itu?"
Esme tidak mengelak. Itu bukan keahliannya. "Ini kemenangan sederhana pertamaku seumur hidup. Bukankah aneh jadinya kalau aku bersikap biasa saja?"
Oliver terkekeh, sedikit berhati-hati lebih merapat pada Esme. "Bagaimana? Kau ingin aku menjadi rekanmu lagi, Esme?"
Esme mengangguk dan kali ini dia tidak menghindar. "Mohon bantuannya, Oliver."[]

NOTES:
Halo! Aku ada sedikit teaser kecil karena kita telah bertemu dengan para pemain inti, nih.
Semoga suka!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top