- • New Year's Day • -
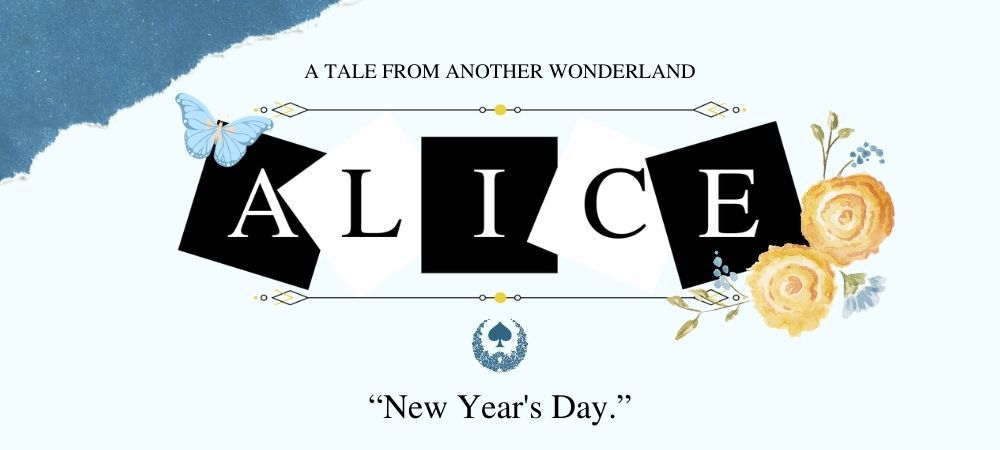
Untuk pertama kali dalam seumur hidup, Esme menanti kembang api perayaan tahun baru di dalam pesawat. Meskipun tidak masuk akal, dia berkali-kali menoleh ke jendela seolah ada kembang api yang menyasar tembus melewati awan, menyapa para penumpang di pesawat tanpa ada turbulensi berlebihan.
Tentu saja kembang api itu tidak ada.
Begitu tiba di bandara, Esme tetap berdiri bersisian dengan Peter saja. Tidak ada yang datang menyambut karena tidak ada satu pun dari mereka yang memberikan kabar. Isi pikiran mereka sama: Yang penting masih dibukakan pintu.
Esme juga bisa menduga bahwa tidak akan ada yang menyambut mereka dengan pesta meriah di rumah. Alasannya jelas karena perayaan besar-besarannya sudah terlewat sekitar dua jam—kecuali bila memang keluarga Sonata berniat untuk tidur ketika matahari terbit, atau tidak berniat melakukan apa pun di hari pertama tahun baru.
"Kau yakin ada yang membukakan pintu? Bahkan asisten Oma sepertinya masih tidur."
"Oh, adikku. Mentang-mentang asisten rumah tangga bukan berarti mereka yang paling nokturnal. Aku yakin pasti ada yang membukakan pintu."
Tadinya Esme berpikir datang bertamu subuh-subuh bukanlah hal yang baik.
Sampai kemudian kemunculan sang sepupu perempuan di ambang pintu merusak ekspektasinya.
Mereka kini berhadapan, dua lawan satu, sama-sama tak bersuara bahkan setelah bertatapan tiga detik. Wajah sepupunya tampak pias sekilas.
Esme berdeham. Menyikut pinggang kakaknya terang-terangan. Katakan sesuatu, katanya lewat gestur tubuh.
Peter mengusap tengkuknya dengan canggung. "Hai?"
Kata-kata itu bagai mantra pelepas sihir. Sepupunya itu terkesiap dan melotot, masih dengan sebuah mug bergambar beruang di tangan. Puas melotot selama dua detik, gadis bercepol berantakan itu lantas mendadak buru-buru meletakkan mug di tempat terdekat, kemudian melompat guna memeluk Esme dan Peter dalam pakaian tidurnya.
Rambutnya mencuat-cuat, lepas dari cepolannya yang asal-asalan. Esme sampai harus memejam kuat-kuat supaya matanya tidak tertusuk. Peter melakukan hal serupa—walaupun sudah dua kali dia tak sengaja memakan rambut sepupunya yang tinggi itu.
Ini dia. Salah satu sepupu favorit Esme, Feodora Jayde Sonata.
"Wow, Bung!" Feodora histeris, terbelalak begitu melepas pelukan dari Peter. "Lihatlah! Big Ben kalah tinggi darimu!"
Peter mengerling, membetulkan posisi ranselnya di pundak. "Becermin, Jayde."
"Aku selalu becermin lima kali dalam sehari, Adler. Oh, dan lihat dirimu, sepupu kecilku yang cantik, elegan, berkilau, dan sudah tidak semungil dulu"—ucapnya gemas dalam satu tarikan napas—"aku amat sangat merindukanmu! Saking rindunya, aku tidak tahu harus memberimu sepatu yang mana. Kau harus memilihnya sendiri nanti."
Esme berkedip, memintal senyum setenang yang dia bisa, walaupun hatinya menjerit tak jauh beda dengan Feodora.
"Kau. Memang. Yang. Terbaik," katanya sungguh-sungguh.
Mendengar itu, Feodora mengulum bibir. Sekali lagi memeluk Esme dengan kekuatan yang tidak main-main. Hanya dilihat dari gesturnya pun orang-orang akan tahu betapa gemas dan positifnya suasana yang disebarkan Feodora.
"Peter, ingin bertukar adik?" Feodora bertanya. "Kau boleh mengambil Leonard dan memperbudaknya sesukamu."
"Trims, tapi aku tidak berminat punya adik perjaka."
"Yah, sayang sekali. Padahal dia tampan."
"Aku tidak ingin punya adik yang menyaingi ketampananku."
"Lihat siapa yang bicara? Tinggi sekali kepercayaan dirinya." Feodora mencibir. "Omong-omong, kenapa kita masih di sini? Ayo masuk, dasar tamu. Setelah kau menginjak keramik pertama, rumah ini akan menjadi rumahmu juga."
Peter bersiul seraya menarik kopernya masuk. "Kata-kata sambutan yang mengharukan."
"Kau menyebalkan."
"Kau bilang begitu seakan ini pertama kalinya kau mengenalku."
Feodora tidak membalas lagi. Dia ambil kembali mug beruang yang tadi dia letakkan sembarangan sambil berjalan memimpin.
Seolah yakin anggota keluarga yang lain tidak terbangun, Feodora berseru, "Ma! Mereka sampai!"
Esme masuk mendahului Peter agar tidak kebagian menutup pintu. Dalam sekejap dia tertegun bahkan hanya karena menatap lantai. Terlalu mengilap. Rasanya dia harus melepas sepatu dan memastikan kakinya sudah dicuci bersih sebelum menginjak lantai itu.
Selanjutnya mata safir itu bergerak memindai. Esme mendadak kebingungan. Arsitekturnya, tiap sudutnya, luasnya, kehangatannya, suasananya yang tetap hidup walaupun sekarang pagi buta—apartemen termahal di Brooklyn tidak ada apa-apanya dibanding ini.
Kemudian gadis itu mendongak, tak luput melepas tatapan dari anak tangga yang berujung lenyap terhalang lantai dua. Pelan-pelan dia duduk di salah satu sofa. Hela napasnya terdengar jelas begitu dia sadar betapa dia membutuhkan sofa sejak tadi.
Belum ada lima detik Esme mendaratkan bokongnya, seorang wanita berlari menuruni tangga. Terburu-buru tanpa khawatir luput satu anak tangga atau bahkan jatuh terguling. Berlari di atas tangga terasa bagai berlari di lapangan landai baginya.
Elena di sana. Ma dari Feodora dan adiknya, sekaligus bibi dari Peter, Esme, dan keponakannya yang lain. Tatkala berhenti di akhir tangga, wajahnya amat cerah sampai sinarnya terasa membutakan. Dia terlihat amat bahagia.
Wanita itu mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Menampilkan gestur terharu.
"Ini kejutan terbaik seumur hidupku," lirihnya. "Oh, mendekat sini, anak-anak! Senang melihat kalian pulang!"
Peter buru-buru mengambil langkah mundur sebelum Elena menariknya ke dalam pelukan yang menyesakkan. Mata kepalanya menangkap jelas Esme yang terlambat sadar dan melotot horor begitu Elena berhasil memeluknya. Ketika adiknya menoleh paksa sebagai bentuk protes, Peter menyeringai.
Sialan kau, umpat Esme lewat gerak bibir.
Selamat berpelukan, balas Peter cerah ceria.
- • -
Tepat ketika jarum pendek berhenti di angka 8, seisi rumah bangun dari tidurnya. Bersama-sama mereka merayakan kedatangan Peter dan Esme dalam balutan piyama, juga bergantian mengucapkan ucapan selamat karena putri bungsu Clara telah menginjak angka usia-nyaris-legal. Yang mana artinya Esme sudah siap lepas dari pegangan orang tuanya kapan saja.
"Baru 17, belum 18," kilah James ketika mereka berkumpul di meja makan. "Mencari kaus kaki saja masih harus dibantu. Mana ada 'lepas dari pegangan orang tua'?"
Clara mengerling tak habis pikir mendengar aib putrinya dibongkar. Baginya, mencari kaus kaki dengan bala bantuan adalah hal lumrah. Dia malah pernah menemukan Peter duduk merenung di kamar apartemen setahun yang lalu karena baru menemukan satu kaus kaki. Padahal waktu itu putranya sudah masuk usia kepala dua.
Clara juga tahu, James bisa diam-diam frustrasi saat kehilangan kaus kaki atau dasi.
"Asal kau tahu, Paman James," Feodora menyela mengunyah roti panggang yang berkeriuk, "aku tinggal sendirian di apartemen saat usiaku 16. Kehilangan kaus kaki bukan penghalang kedewasaan."
"Ya, lalu dua bulan kemudian dia kembali ke sini karena keran air di wastafel apartemennya tidak bisa diam." Elena bicara dengan tenang, penuh senang hati membongkar aib putrinya sendiri.
Si kecil Leonard ikut-ikutan berkata, "Kau takut ada makhluk gaib yang iseng memainkan keranmu padahal itu hanya kebocoran biasa, Fe."
"Oh, tutup mulutmu, anak kecil. Aku tidak ingin mendengarnya darimu."
"Yang terpenting adalah kebersamaan."
Semua atensi teralih begitu wanita yang paling tua dan duduk di kepala meja angkat suara. Itulah Oma Mandalyn, kepala keluarga Sonata pengganti suaminya yang telah meninggal dunia.
Pelan-pelan dia menyeruput supnya yang masih mengepulkan asap. "Kembalinya Feodora saat itu adalah bukti bahwa dia tidak bisa lepas dari keluarganya. Begitu pula dengan Peter dan Esme. Pasti ada ikatan dan panggilan yang membawa mereka ke sini. Bukan begitu, cucu-cucuku?"
Esme memiringkan kepala guna mendekati telinga kakaknya. Berbisik-bisik, "Padahal kita ke sini karena pekerjaan Ayah."
Peter menginjak kakinya. "Anggukkan saja kepalamu. Itu tidak sulit."
Agak enggan, Esme tersenyum dan mengangguk begitu sang nenek menatapnya lurus-lurus.
Oma Mandalyn sudah berumur. Tidak heran hobinya adalah menyangkut-pautkan segala sesuatu dengan hal yang mistis atau penuh makna tersirat. Seolah-olah hidupnya selain menggambar model baju adalah sebagai motivator utama bagi anak-cucunya.
Peter paham betul tabiat manula. Sebagai cucu pertama, dia yang paling terlihat memuliakan Oma Mandalyn walau harus ditertawakan adik dan sepupu-sepupunya sendiri.
Meski begitu, Oma Mandalyn adalah orang yang penuh kasih.
Hanya lewat kerut halus di matanya ketika dia tersenyum, orang-orang akan tahu bahwa wanita tua itu amat menyayangi anak-cucunya.
"Tambah lagi, Esme," ucapnya hangat seraya menyendokkan semangkuk sup lagi. "Makanlah yang banyak. Kau harus tumbuh menjadi wanita cantik yang sehat."
Salah satu sifat yang dirutuki Esme adalah perasaan salah tingkah bila seseorang mendoakan kebaikan untuknya. Ketika gelisah, netranya akan melirik ke kanan dan kiri sampai tidak sengaja beradu pandang dengan seseorang. Kali ini, orang itu adalah Clara. Dua iris safir itu bertumbuk selama sepersekian detik.
Esme memutus kontak mata lebih dulu. Berdeham kecil dan meninggalkan senyum tanggung sebelum kembali menyantap sarapan.
Selepas sarapan, Esme berderap ke kamarnya di lantai dua. Tanpa merasa bersalah meninggalkan sesi bincang-bincang yang menghabiskan banyak waktu, bergerak membereskan barang semaunya, kemudian merebah di atas ranjang barunya.
Dalam hitungan detik yang panjang, dia beradu tatap dengan langit-langit kamarnya yang tinggi di atas sana. Sejenak dia merasa asing karena bentuk plafonnya saja sudah benar-benar berbeda dengan kamarnya di Brooklyn.
Oh, tentu saja, plafon kamarnya yang sekarang jauh lebih enak dipandang. Rasanya penuh nostalgia. Apartemen mewah sekalipun tidak ada tandingannya.
"Hei, cantik."
Esme mengernyit. Bergegas gadis itu menoleh ke ambang pintu. Dia mendengkus kemudian. Mudah saja menarik seringai begitu melihat siapa yang berdiri di sana.
Leonard, adik satu-satunya Feodora, bersandar pada daun pintu dalam kondisi rapi sehabis mandi. Wangi parfum menyengat menusuk hidung bangir Esme, sukses membuat gadis itu mengernyit selama tiga detik lamanya.
Apa-apaan wanginya itu?
"Catcalling yang bagus, Leonard. Sekarang cepat ganti parfummu kalau kau hendak pergi berkencan," cetus Esme. "Demi Tuhan, aromanya buruk sekali. Parfum Peter masih jauh lebih baik dibandingkan parfummu itu."
Leonard mengendus lengan bajunya. "Tapi ini parfum Ma."
"Lebih buruk lagi. Kau ingin pacarmu berpikir sedang mengencani siapa? Wanita beranak dua?"
Anak itu cemberut, terang-terangan menatap si kakak sepupu dengan sorot netra biru-kehijauan yang mampu memikat orang mana pun. Walau cantik dan tampak baik, terkadang Leonard lupa kalau mulut sepupunya itu kesulitan memilih kata-kata yang lebih halus.
"Padahal aku ke sini untuk pamer. Feo juga tidak pernah berkomentar tentang fesyenku. Kenapa kau yang bukan kakakku malah banyak berkomentar?" gerutunya pelan.
"Oh, Leo-ku sayang. Feo bilang begitu karena dia tidak peduli dengan kencanmu, sedangkan aku amat sangat peduli dengan kesuksesan kencanmu. Aku juga memperhatikan pengaruh fesyen hari ini untuk kencan kalian yang selanjutnya." Esme duduk bersilang kaki, mencoba untuk tampak anggun dalam balutan celana panjang loreng-lorengnya yang hangat. "Bukankah bagus mendapat saran dari orang yang lebih berpengalaman?"
Leonard mengangkat alis. "Kau pernah berkencan?"
"Tidak."
"Tadi kau bilang berpengalaman?"
"Aku tidak bilang 'berpengalaman dalam berkencan' secara spesifik."
Leonard terbungkam. Tiba-tiba bingung ingin membalas apa lagi. Memang benar hanya Oma Mandalyn yang mampu membalas segala ucapan Esme sampai salah satunya mati kutu.
Suara tepuk tangan perlahan datang mendekat. Muncul Feodora dari belakang adiknya, ikut bersandar di ambang pintu.
"Olahraga mulut yang luar biasa," katanya. "Kalau kau sudah tidak sibuk meladeni adikku yang tampan dan wangi walaupun menyengat ini, kau bisa ikut aku ke lantai tiga, Esme. Aku punya beberapa kotak yang harus kaubuka di loteng. Ini harimu."
Esme mengerjap, mendadak sumringah. Tanpa ragu kaki jenjangnya langsung melakukan aksi melompat bangun begitu insting fesyennya menajam.
Derap langkah Esme mengetuk permukaan lantai kayu. Di ujung lantai dua di mana kamarnya berada, ada sebuah tangga lagi menuju lantai berikutnya. Dia mendadak tidak peduli lagi dengan masalah Leonard dan wangi badannya. Berlarian di atas tangga untuk mencapai kamar sepupunya di atas sana adalah satu dari sekian banyak yang dia rindukan sebagai anak kecil.
Sampai sebuah pertanyaan melesat di kepalanya.
"Kenapa di loteng?" tanyanya.
Feodora menoleh sekilas, tak lupa mengulas senyum. "Karena aku suka di sana. Akan kutunjukkan mengapa."
Esme mengangkat alis. Penasaran, tetapi juga tidak terlalu. Dia pernah punya kenalan yang hobi menatap isi loker sendiri di sekolah. Kalaupun sepupunya hobi berkhayal di loteng, Esme tidak akan kaget atau heran lagi. Toh, dia sendiri hobi bengong menatap langit dari jendela kamar.
Feodora berhenti sejenak, lalu mengambil langkah ke arah deretan vas berisi bunga di ujung lantai tiga, tak jauh dari pintu kamarnya. Di belakang banyak vas, di bawah pigura foto yang tergantung rapi; gadis itu menarik keluar sebuah tongkat panjang. Cukup panjang untuk menusuk langit-langit di atas sana.
Esme diam di tempat. Menyaksikan sepupunya bersenandung ria sambil menggenggam tongkat dan mendongakkan kepala.
Tatkala gadis itu ikut mendongak, pahamlah dia apa fungsi tongkat yang diambil Feodora. "Pintu loteng?"
"Apa lagi?" Feodora mengangkat bahu, tersenyum geli. Lihai gerakan tangannya saat menyambar pengait di langit-langit dengan ujung tongkat.
Esme bertanya, "Kau sering bolak-balik ke sana, ya?"
"Yah, lumayan. Sebenarnya tidak juga, sih. Aku baru kembali ke atas sini begitu mendengar kau dan Peter sudah setengah jalan ke London. Sebelum itu aku lebih sibuk di kamar. Omong-omong, ini agak berat karena tangganya baru diganti lagi dengan bahan yang ... entah kayu atau plastik, yang jelas lebih kokoh. Tadinya aku suka menggunakan tangga yang ringan, tapi entah kenapa lama-lama guncangannya meresahkan. Yang jelas bukan karena berat badanku bertambah, semoga. Nah, selesai. Ayo naik."
Esme mundur satu langkah, membiarkan Feodora menapaki anak tangga lebih dulu sampai sepupunya itu lenyap ditelan loteng.
"Di atas sana aman?" tanyanya.
"Oh, tentu saja. Dalam dua jam yang kalap, aku berhasil membereskan sampah persiapan sebisaku. Aku bertaruh tidak akan ada tikus loteng." Kepala Feodora muncul, bibirnya tersenyum. "Kemari, Esme. Kau akan suka ini."
Gadis itu menyentuh tangga loteng, sekali lagi mendongak ke atas sana. Dengan sekali pembulatan tekad, dia angkat kakinya dan mulai memanjat ke atas. Rambut emasnya yang dia ikat kuat bergoyang-goyang lembut. Tadinya Esme ingin bersikap kalem saja, tetapi sebuah cahaya hangat yang tiba-tiba muncul di atas sana langsung menarik perhatiannya.
Loteng itu tidak terlihat suram.
Hanya karena gagasan itu, Esme langsung bergegas naik. Tidak sabar melihat seisi loteng dengan mata kepalanya sendiri. Nyaris kepalanya terantuk saking tidak sabarnya.
Begitu sampai di atas, kelopak matanya melebar dan iris safirnya berbinar. Loteng itu tidak sesuai dugaan awalnya. Memang sempit seperti loteng pada umumnya, tetapi Feodora merapikan dan menghiasnya dengan baik. Di detik itu juga, Esme bertekad untuk menjadikan loteng itu sebagai tempat pribadi keduanya selain kamar.
"Aku suka ini," desisnya.
Tentu saja Feodora terkekeh menang mendengarnya. "Aku tahu itu. Jadi di sudut sini kutambahkan rak kecil-kecilan kalau kau ingin menimbun buku bacaanmu dan menikmatinya di sini."
Esme berkedip cepat. "Tidak masalah?"
"Kenapa harus? Yang jadi masalah adalah tugas sekolah yang menggunung di kamar dan harus diselesaikan sebelum liburan musim dingin usai." Feodora duduk mengempaskan diri ke atas bean bag di dekat jendela loteng. "Aku memisahkan barang-barang berdebu di ujung sana. Jadi jangan khawatir menginjak benda keramat."
Esme menoleh ke sudut yang lain. Terpaku pada kotak-kotak dus yang bertumpuk dan sebuah benda tinggi yang dihalau sehelai kain putih super lebar. Rasa penasaran itu kembali datang.
"Yang ditutupi kain itu apa?"
"Cermin," jawab Feodora. "Kayunya masih bagus, tapi kacanya retak parah di ujung. Oma tidak suka itu karena katanya seperti sedang diawasi. Manula sering berfantasi, makanya dibawa ke sini karena Ma bilang sayang bila dibuang begitu saja."
Esme ikut duduk walau harus tanpa alas. "Masih bisa dipakai?"
"Masih. Buka saja kalau kau berani."
"Itu tidak terdengar seperti aku boleh membukanya."
"Yah, bukan tidak boleh. Hanya tidak menyarankan. Kau tahu pandangan orang-orang tua dan anak kecil terkadang benar adanya. Remaja dan orang dewasa fokus pada realita. Itulah kenapa seringkali kita tidak dapat memahami apa yang orang tua dan anak kecil maksud." Feodora meraih dua kotak berpita di bawah rak kecil-kecilan yang dia maksud. "Nah, ini dia. Dua kotak untuk satu orang."
Esme terperangah. Bersiap menerima keduanya, tetapi ragu bila harus berbagi dengan Peter. "Dua-duanya untukku?"
"Menurutmu apa? Harus berbagi dengan Peter?" tebak Feodora tepat sasaran. "Hadiah untuk Peter butuh tebal bungkusan sebesar lima kali lipat dari milikmu. Jadi, ya, mereka untukmu, Esme."
Esme mengulum senyum. Menahan diri untuk tidak menerjang Feodora dan menariknya ke dalam pelukan dramatis.
"Terima kasih, Feo," ucapnya tulus.
"Bukan masalah." Feodora menepuk-nepuk pundak sepupunya. Lantas tersenyum diplomatis. "Selamat Natal, Esme. Dan selamat ulang tahun."
Di loteng yang dingin, di bawah lampu hias yang hangat, dua gadis Sonata itu bertukar senyum. Sama-sama bersyukur karena kembali dipertemukan di tahun baru.
- • -
Cangkir itu masih sama di tempatnya. Tidak bergerak seinci pun karena belum disentuh sama sekali. Uap panas yang sebelumnya mengepul kini bahkan sudah hilang sepenuhnya. Temperatur yang semakin menurun setiap harinya membuat teh kamomil itu juga lebih cepat mendingin daripada biasanya.
Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Tidak terganggu dengan helaian rambutnya yang terus tertiup lembut angin malam. Tubuhnya tampak ramping menggunakan gaun hijau tanpa lengan, yang mana bahannya seolah-olah memantulkan cahaya bulan. Ada kain yang berwarna serupa yang melilit pinggangnya, diikat ke tengah dan jatuh menjuntai begitu saja. Pakaian luarnya pun sama—hijau, tipis, menyelimutinya seperti mantel tanpa lengan. Setiap kali dia bergerak, dia tampak seperti peri hutan yang amat rapuh dan gemulai gerakannya.
Wanita itu menatap secarik kertas di atas meja. Netranya bergerak, berusaha memahami di mana inti suratnya.
[... aku ingin kau segera menemukannya.]
Ah. Wanita itu tertegun. Barulah paham mengapa cangkir teh di atas meja tak kunjung disentuh.
Ini pasti tekanan baru untuknya, bukan?
Masih diterpa angin malam, dia tatap jendela yang terbuka tepat di belakang meja kerja tuannya. Di ujung meja, ada sebuah jubah mantel hitam terbaring tak terlipat. Sebuah gagasan sederhana muncul di kepalanya: surat di atas meja pastilah penyebab sang penerima memutuskan untuk keluar dan mendinginkan kepala.
Perlahan, wanita itu mengusap lengannya sendiri begitu dinginnya angin mulai menggigit kulit. Negeri ini mulai kedatangan musim dingin.
"Setidaknya kenakan pakaian hangat sebelum keluar, Tuan."[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top