- • Lost and Found • -
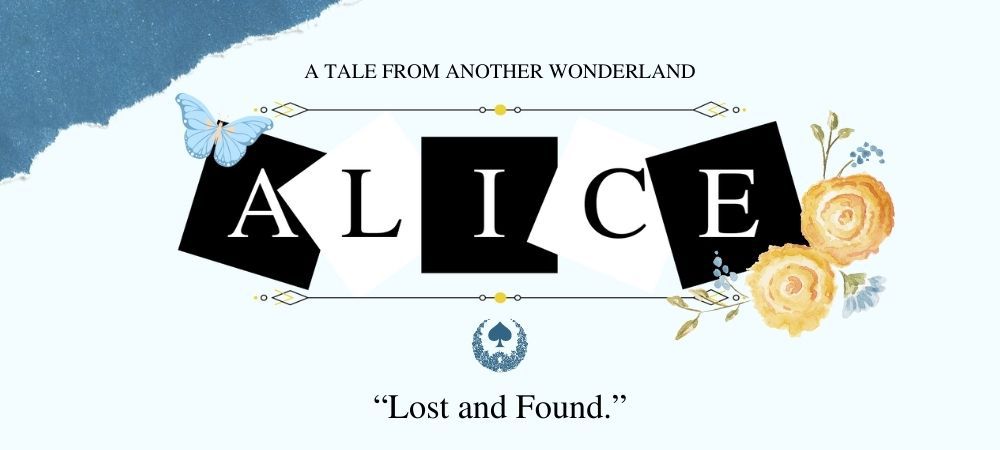
Peter menggertakkan gigi untuk yang kesekian kali. Dia jarang berdiri diam di tempat dengan perasaan campur aduk, dan kali ini dia melakukannya karena sang adik tak kunjung mengangkat telepon. Dalam lubuk hati yang paling dalam, Peter masih bisa memaklumi kenapa telepon dari ibunya "agak sulit" untuk diangkat Esme, tetapi kalau sampai teleponnya tidak diangkat juga tandanya sudah gawat.
Selain Peter dan ibunya, ada Feodora yang duduk di sebelah Clara. Mencoba untuk membantu lewat usapan lembut pada lengan bibinya itu.
Resah karena melihat Peter terus-menerus mencoba sambungan ulang, Feodora akhirnya bertanya, "Masih tidak ada jawaban?"
"Jangankan dijawab, tersambung saja tidak," decak Peter. Lagi-lagi mendengar pesan bahwa nomor yang dituju tidak aktif. Penuh kegusaran dia menyugar rambut pirangnya ke atas, kemudian berakhir dengan berkacak pinggang. Tatapannya kini lurus ke arah jendela yang sedang dihantam hujan salju berangin. "Tidak ada cara lain selain memeriksanya langsung."
"Jangan coba-coba." Feodora mendesis. Tidak terlihat senang sedikit pun. "Aku tidak ingin sepupuku menghilang karena mencari sepupuku lainnya yang hilang."
"Fe, kau tidak bisa selamanya mengandalkan polisi."
"Justru kau harus mengandalkan polisi. Itu pekerjaan mereka. Kau pikir mereka dibayar untuk apa? Makan donat sambil membayangkan adegan kejar-kejaran tapi malas melakukan aksi nyatanya setiap hari?"
Peter menghela napas berat. Bernegosiasi dengan orang yang sedang kalut memang bukan hal yang mudah. Clara yang tangannya diusap, tetapi malah Feodora yang berkoar-koar. Entah siapa yang sebenarnya khawatir di sini.
Hanya lewat ekor matanya, Peter tahu bahwa ibunya tengah menatapnya lamat-lamat. "Peter."
"Bu, aku tidak bilang—"
"Menyerahkan dirimu ke tengah cuaca buruk juga bukan rencana yang akan ibumu ini setujui," tekan Clara.
Peter harus menahan diri untuk tidak berdecak lidah karena dia bisa mendengar getaran pada suara ibunya yang sedang mencoba kuat. Oh, siapa pun tolong jangan salahkan Peter yang sekarang mengerling jengkel. Percayalah, dia sudah tidak tahan lagi.
"Bu, ponselnya mati." Peter menarik napas panjang. Tidak sempat terpikir olehnya bahwa kata-kata itu terasa menyakitkan untuk diucapkan. "Esme selalu membawa bank dayanya ke mana-mana. Kalau baterai ponselnya habis, seharusnya dia bisa mengisinya segera. Kalau sampai ponselnya mati karena dingin, berarti ...."
"Berarti antara jatuh di tengah jalan, atau dia sedang berada di tempat yang terlalu dingin." Feodora menambahkan, lirih suaranya.
Di bawah tatapan tegar merangkap rapuh ibunya, Peter menyugar rambutnya lagi. Kali ini dia memutuskan untuk duduk di sofa yang kosong, tepat di sebelah ibunya. Tadinya dia berniat untuk duduk di sebelah Feodora saja, tetapi sepertinya yang lebih membutuhkan dukungan emosional adalah Clara.
Oh, andai Peter bisa membaca pikiran Feodora—sepupunya itu berpikir bahwa Peter sendirilah yang paling membutuhkan dukungan emosional saat ini.
Sekali lagi Peter menghela napas, mencoba untuk tenang.
Bila ditawarkan antara diam di rumah atau berpakaian tebal mengarungi badai salju, tentu Peter akan memilih opsi pertama. Bila Esme ada di posisinya, barangkali gadis itu akan memilih hal yang sama. Karena, toh, memang ada orang-orang di luar sana yang bertugas untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini.
Namun, Peter ingin melakukannya.
Dia ingin mencari adiknya, menemukannya, lalu menjitak keningnya sampai penyok (paling tidak memar sedikit). Peter akan melakukannya sebagai kakak, sebagai cucu pertama, juga sebagai satu-satunya laki-laki di rumah ini.
Leonard dikabarkan sedang asyik meminum cokelat panas di rumah temannya, James terjebak di kantor, Paman Willem—suami Elena—bekerja jauh di luar kota sejak pertengahan musim gugur dan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda akan pulang ke London. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab mencari Esme saat ini. Bahkan mendiang Opa Nicholas tidak bisa melakukan apa-apa di atas sana.
Hanya dia satu-satunya.
Ah, sebenarnya ada lagi. Satu lagi sosok seseorang yang entah kenapa rasanya mengambang di ingatan Peter saat ini. Antara ada dan tiada, antara kenalan atau orang asing. Rasanya janggal. Seolah jawabannya ada di kepala, tetapi sulit untuk menyebutkannya keras-keras.
Pikirkan yang lain, Peter. Jangan buang-buang tenaga untuk hal yang sia-sia.
Peter membuka mulut, hendak menyampaikan gagasan lain terkait rencana pencarian adiknya, tetapi tiba-tiba suara bantingan pintu depan menahan kata-katanya dan spontan membuat si pemilik mata safir itu duduk tegak. Dia beradu tatap dengan sepupunya dalam hitungan yang seirama. Lalu keduanya melesat ke lorong pintu depan.
Nahas, dugaan bahwa Esme pulang dengan selamat pupus begitu saja, lantaran ternyata yang berhasil menerjang badai salju sampai ke rumah adalah Elena.
Sama seperti kedua sepupu yang kaget dan bingung, Elena yang bersandar lemas ke daun pintu juga sama bingungnya.
"Ada apa ini? Kalian menungguku?" tanyanya sembari tak henti menepuk-nepuk mantelnya dari butiran salju. Napasnya memburu. "Kalau kalian berpikir aku membawa kue seperti biasanya, kali ini aku benar-benar minta maaf ... Oh, astaga. Nakal sekali benda putih kecil ini. Mantelku yang malang."
Peter dan Feodora bertukar tatapan sejenak, kemudian sepupu perempuannya itu bergegas mendekati ibunya yang kerepotan.
"Biar kubantu, Ma," dia berkata.
Peter menyimpan ponselnya ke saku celana sebelum mendekati mereka. Mencoba untuk membantu dengan cara membawakan barang atau sekadar memungut sepatu bot hangat bibinya.
"Apa ... Bibi bertemu Esme di luar?" Peter bertanya, sangat berhati-hati.
"Esme?" Elena mengangkat wajah bundarnya, kemudian menekuk kedua alisnya serempak. Siapa pun bisa melihat wajahnya yang memerah karena kedinginan itu hanya menunjukkan ekspresi bingung semata. Setelah diam tiga detik lamanya, wanita itu akhirnya menggeleng. "Tidak. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Orang-orang menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat. Bahkan mereka bilang ada satu kedai makanan di taman sampai rubuh karena angin."
Kedua bahu Peter merosot. Kecewa.
Elena menangkap gerakan kecil itu dengan baik. Maka dia menoleh ke arah Feodora dan bertanya, "Apa ada masalah serius?"
"Esme pergi keluar tadi pagi tak lama setelah Ma berangkat, tapi sampai sekarang dia belum kembali," jawab Feodora seraya menggantung mantel. "Bibi Clara sudah menghubunginya beberapa kali sebelum cuacanya memburuk, dan tidak ada jawaban. Barusan Peter juga mencoba untuk menelepon, tapi sekarang nomornya tidak aktif."
"Ya Tuhan ...," Elena bergumam lirih. Mendadak khawatir dengan keadaan keponakan kecilnya yang baru beranjak ke puncak remaja. "Atau mungkin dia pergi ke rumah temannya? Sama seperti kebiasaan Leon—oh, benar juga, ke mana anak itu?"
"Di rumah temannya. Yah, Ma, maksudku kau tahu," Feodora meringis, "Esme tidak punya yang ... seperti itu di sini."
Mata cokelat Elena melebar perlahan. Keterkejutan datang kemudian disusul oleh keprihatinan.
"Itu agak mengejutkan," gumamnya.
Diam-diam Peter mendengkus. Sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Selama tinggal di apartemen kecil, adiknya memang memiliki beberapa teman sebelum resmi menjadi bagian dari salah satu siswa di taman kanak-kanak London. Namun, pertemanan itu tidak bertahan lama karena ayah mereka dipindahtugaskan ke Brooklyn dan ibu mereka tidak bisa mengurus dua anak kecil sekaligus sendirian.
Sejak dulu Peter berpikir kenapa mereka tidak langsung ke rumah besar Sonata daripada harus ikut mengepak barang dan terbang ke Brooklyn? Kenapa baru sekarang mereka memutuskan untuk tinggal bersama anggota keluarga lainnya?
Kalau jawabannya karena keegoisan orang dewasa, aku tidak akan kaget, batinnya.
Peter diam di tempat. Tak kunjung menyusul Elena yang melangkah lebih dulu ke ruang tengah untuk menghambur ke Clara. Raganya diam membeku di lorong. Sibuk mendengarkan deru angin di balik pintu.
Lamunan Peter buyar ketika Feodora menyenggol lengannya keras-keras. Mata sepupunya yang sebiru laut dalam itu menatapnya lamat-lamat, seolah tengah menyampaikan kata-kata positif tanpa bersuara.
Peter menyadari satu hal: Feodora cantik—sangat cantik. Meskipun rambut pirang bergelombangnya hampir cokelat karena gen dari Elena dan mata birunya tidak seberkilau Esme, Clara, atau bahkan Oma Mandalyn, gadis itu bersinar dengan caranya sendiri. Siapa sangka bahwa gadis yang dulunya kesepian lantaran tidak punya sepupu perempuan kini sedang mencoba tenang saat sepupu perempuan pertamanya hilang?
"Kalau kau butuh sedikit hiburan, aku akan mencoba membayangkan diriku menjadi Esme," kata Feodora. "Tempat mana yang akan kukunjungi, alasan kenapa tidak mengangkat telepon ... semua itu sedang kubayangkan di kepala saat ini."
Peter mengintip ke ruang tengah, menyaksikan bibinya tengah memberikan usapan penyemangat untuk sang ibu. "Dan kau dapat jawabannya?"
"Tidak." Feodora mengakui. "Aku lupa kalau anak itu agak sulit ditebak. Walaupun dia berjalan-jalan ke taman, tidak ada yang tahu dia berjalan-jalan ke bagian mananya. Bisa jadi ke seberang danau. Atau berenang di dalamnya."
Peter mendengkus. Kembali mencoba menghubungi adiknya meskipun dia tahu usahanya sia-sia.
"Tidak ada yang bisa ke seberang danau saat musim dingin. Akses jalannya ditutup," ucapnya, lalu terdiam. Sebuah kesadaran baru menimpa kepalanya bagai bom di saat itu juga. Genggamannya pada ponsel sejenak melemah, kemudian menguat. "Danau ...."
Di sebelahnya, Feodora mengerutkan kening dan mengarahkan tatapan bertanya-tanya. Tak butuh waktu lama tatapan bertanya itu berubah menjadi tatapan curiga.
"Kau tidak berpikir bahwa Esme—"
"Tidak, bukan, bukan itu." Peter bergegas melangkah ke ruang tengah.
Feodora menyusul di belakangnya dengan sejuta benang terputus yang saling menyambung di kepalanya. Mereka panik, dan mereka tahu bahwa sebelum menentukan langkah selanjutnya harus ada kepastian.
"Bu," Peter memanggil. "Apa dia bilang pada Ibu ke mana dia akan pergi? Setelah sarapan?"
Clara mengerjap, mencoba mengingat-ingat. Netra safirnya berkedip lembut dan itu membuat Peter semakin teringat adiknya yang sering berbuat serupa.
Kemudian Clara tersentak. "Taman St. James."
"Taman St. James?" Elena melotot. Bersiap untuk membuka mulut untuk menceritakan tentang kedai rubuh yang dia dengar dari orang-orang, tetapi Feodora berhasil membungkamnya lewat pelototan di balik bahu Peter.
Jangan beritahu Bibi, begitu kata tatapan putrinya.
Kalaupun Clara menangkap sinyal Feodora, wanita itu tidak menunjukkannya lewat ekspresi. Wajah teguh Peter lebih menarik untuk dilihat. Netra safirnya menatap Peter lurus-lurus, seolah tengah memberikan sebuah peringatan.
Peter menangkap sinyal itu, tentu saja. Dia sadar bahwa dia lelaki yang peka.
"Oke, Bu. Dengarkan aku. Aku tidak akan pergi keluar di tengah cuaca buruk, dan aku akan menelepon polisi nanti," sela Peter. Seolah tahu betul apa maksud ibunya. Lalu, setelah menarik napas berulang kali dia berkata lirih, "Tapi tolong, Bu, izinkan aku pergi mencari Esme juga."
- • -
Tak jauh berbeda dari Dunia Atas, Negeri Ajaib pun sama kacaunya. Salju di mana-mana, beku mulai merambat, dan beberapa anak mulai dilarang untuk bermain di luar. Perintah hibernasi mutlak turun, dan Caleb masih tak habis pikir ke mana si penanggung jawab cuaca kali ini pergi.
Di atas sofa ruang kerjanya yang empuk, seorang gadis dengan rambutnya yang pendek duduk menekuk kaki sambil berlilitkan selimut tebal. Potongan terusan kuning pekat yang menyimbolkan keceriaan musim panas sama sekali kalah di tengah putihnya salju. Di depan perapian, ujung-ujung kaki telanjangnya yang pucat bergerak-gerak agar tetap hangat. Bukan sekali dua kali gadis itu melihat pria berambut putih di sana berdiri resah ke arah jendela. Pita hitam yang mengikat surai putih itu sudah berulang kali dipasang ulang.
Alasannya sama: kelakuan si Warden bungsu hobi membuat Warden lain senam jantung.
"Kupikir dia kerepotan," kata si gadis.
"Dan seharusnya dia melakukan ini sebelum dia kerepotan. Aku selalu bertanya-tanya apakah memang dia sumber masalahnya atau mungkin memang Alice-nya yang salah." Caleb menghela napas kasar, lalu mengalihkan pandangannya dari jendela. "Ini melelahkan. Memang lebih baik kalau aku mencari kesibukan saja."
"Ya, karena musim panas selanjutnya masih lama, kau harus mencari kesibukan yang baru. Ingat kataku kemarin? Jangan lupa menulis surat balasan untuk petinggi. Pertemuannya tidak lama lagi." Si gadis mengerucutkan bibirnya seraya menyapukan tangan ke arah api. Mata sewarna batu ambarnya berkilat-kilat. "Itu mengingatkanku satu hal; Melv juga belum membawa Alice barunya ke sini."
"Masih ada waktu satu setengah bulan sebelum musim semi, Anya. Dia tidak perlu terburu-buru."
"Itu kalau Alice yang dia bawa tidak serealistis milik Ruviane. Bagaimana kalau keras kepala juga? Atau bahkan lebih parah?" Si gadis berasumsi macam-macam. "Sekarang aku penasaran, kenapa Alice yang dibawa Ruviane seringkali keras kepala? Apa itu karma karena dia playboy? Makanya dia ditugaskan menjaga gadis yang keras?"
Caleb mengangkat kedua bahunya serempak. Lengan bajunya dia tarik sedikit sebelum memulai pekerjaan baru. Meskipun ucapan nonanya patut untuk dijadikan bahan renungan, Caleb tidak memiliki waktu seluang itu.
Yah, kalau dipikir-pikir, Caleb mulai merenung sambil bekerja, mungkin itu juga menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa anak itu sering sial di awal pertemuan dengan Alice-nya selama ini.
"Coba kau tanya Mad Hatter. Mungkin dia tahu sesuatu tentang karma semacam itu."
"Oh, ya, Mad Hatter si segalanya. Mad Hatter begini, Mad Hatter begitu—ayolah! Kalian terlalu memuja Mad Hatter. Tidak ada habisnya." Gadis itu, Anya, mengerling jengkel. Tidak ada kerjaan meniup poni panjangnya yang meluruh. "Apa jangan-jangan dulu aku juga merepotkanmu seperti itu?"
Mendengar itu, mau tidak mau Caleb terkekeh. Pada dasarnya, semua Alice itu merepotkan, jawabnya di dalam hati, yang mustahil dia berani ucapkan keras-keras di depan seorang Alice.
Akhirnya dia memutuskan untuk sibuk, membuka laci mejanya, mencari-cari alat tulis. "Tidak ada pekerjaan yang tidak merepotkan. Mudah atau tidaknya tergantung pada orang yang melakukannya," tuturnya bijak.
Anya mendengkus, lalu tersenyum pahit. Bara api di depannya bergerak-gerak. "Kuharap kau tidak bosan denganku," gumamnya lirih.
Gerakan tangan Caleb berhenti seketika. Matanya berpindah melirik si gadis berselimut tebal di depan perapian. Dari jarak yang cukup jauh pun dia bisa melihat ada kemuraman di sana. Pantulan muram yang seolah mengatakan bahwa gadis itu terpaksa bertahan karena tidak tahu harus ke mana.
Memang ada Alice yang seperti itu setiap periodenya. Beberapa dari mereka berpikir bahwa tidak ada lagi yang menginginkan keberadaan mereka selain Negeri Ajaib. Sehingga dengan senyum seberat apa pun, selama para penduduk Negeri Ajaib masih menerima keberadaannya, para gadis itu akan melakukan tugas mereka sebagai Alice sebaik mungkin.
Anya McDough sudah berada di Negeri Ajaib selama dua musim panas lebih beberapa bulan. Musim panas yang berikutnya akan menggenapkan hitungan tinggalnya dia di negeri khayalan menjadi tiga kali musim panas.
Tentu saja Caleb pernah bertanya apakah gadis itu memiliki keinginan untuk pulang atau tidak. Nahas, Anya selalu mengukir senyum pahit setiap topik itu diangkat. Dan sekarang senyum pahit itu muncul lagi bahkan ketika Caleb tidak mengarahkan topik pembicaraan ke sana.
Alihkan dengan mulus, Caleb. Alihkan dengan mulus.
"Kenapa aku harus bosan dengan pencinta anjing yang baik hati?" tanyanya retoris. Lembut dan tenang di balik meja kerja. "Selama kau terus menjadi matahari orang-orang, sebanyak apa pun musim panas yang datang akan kulewati bersamamu dengan senang hati, Nona McDough. Tidak perlu berpikir yang buruk-buruk."
Anya mengisut hidungnya yang bangir. Sekilas dia menoleh ke arah Caleb untuk memberikan senyum. "Kau yang terbaik, Cal."
"Senang mendengarnya."
Anya terkekeh, setelah itu dia mendongak, beradu tatap dengan langit-langit. Begitu mata ambarnya melirik ke samping untuk melihat kegiatan Warden-nya lagi, sebuah kilatan cahaya lewat secepat angin di luar jendela. Dalam sekejap gadis itu tertegun. Dadanya berdebar, senyumnya lenyap.
"Cal."
Caleb barangkali menangkap nada yang janggal dari panggilan nonanya. Karena itu dia rela menghentikan kegiatannya sejenak untuk memberikan atensi penuh. "Ya?"
"... Mereka datang." Getaran kecil merambat pada tiap kata yang dilontarkan Anya. Gadis itu kemudian melompat bangun tanpa melepas selimut. Rasa suntuk yang tadi menderanya lenyap seketika. Euforia baru kini memeluknya dengan erat. "Demi topi-topi aneh Mad Hatter! Mereka datang! Aku bisa merasakannya! Oh, astaga! Aku harus cepat!"
Di bawah tatapan penasaran Caleb, Anya meraih kaus kaki, sepatu pantofel hitamnya yang berhak rendah, dan mengenakan semua benda itu dengan cepat. Setelah bimbang sepersekian detik, akhirnya selimut tebal dilempar ke sofa dan dia beralih kepada mantel jubahnya. Selesai bersiap, Anya langsung berderap ke arah pintu. Gerakannya kalap. Bahkan Caleb sampai mengernyit was-was ketika gadis itu nyaris jatuh tersungkur akibat tersandung daun pintu.
"Pelan-pelan!" Caleb menegur.
"Tidak bisa! Ini darurat!" Anya berseru. Suaranya bergema di sepenjuru lorong ketika dia menambahkan, "Aku harus memastikan Aletta juga merasakan hal yang sama!"
Diiringi pintu yang berayun menutup perlahan, Caleb geleng-geleng kepala. Semaksimal mungkin berusaha untuk fokus menuliskan surat balasan untuk petinggi, tetapi ketukan ringan pada daun pintu menginterupsinya lagi. Kali ini dia melihat Melv, rekannya sesama Warden, tengah bersandar gamang pada tepi pintu sembari melihat ke arah kejauhan; arah ke mana Anya pergi.
Caleb mengangkat alisnya lantaran pemuda di ambang pintu tak kunjung masuk.
"Ada yang mengganggumu, Tuan Melv da Luz?"
Melv akhirnya mengalihkan netra emasnya dari arah lorong. "Kenapa Anya berteriak? Ada tamu penting yang datang?"
"Katanya memang begitu, tapi mari kita tunggu kabar berikutnya. Nanti dia akan kembali. Tunggu saja."
Melv berjalan masuk, menutup pintu, kemudian duduk di atas sofa. Tidak terkejut karena bukan Caleb namanya kalau tidak bijak setiap saat.
Sejenak yang dia lakukan adalah melakukan observasi sederhana pada ruang kerja Caleb. Setiap sudut dindingnya, pigura foto yang terletak di atas perapian, rak-rak buku menepi—betapa susunan yang klasik. Hal yang membedakan ruangan itu dengan ruang kerjanya sendiri hanyalah nama yang tertulis pada setiap kertas di atas meja, juga ukiran logo yang berbeda di permukaan depan daun pintu.
Pemuda itu menghela napas sebelum berkata, "Petinggi A memberiku peringatan tentang Alice-ku yang berikutnya."
"Oh, ya? Tuan petinggi yang satu itu memang hobi memberikan peringatan."
"Katanya jangan sampai terlalu mengulur waktu," ucap Melv pelan dan hati-hati. "Jangan sampai kau melakukan seperti apa yang dilakukan rekanmu, tepatnya dia bilang begitu."
Caleb melirik si tamu sebentar, lalu mengedikkan bahu seolah-olah yang diucapkan Melv sebenarnya tidak sesakral itu sampai harus diucapkan dengan lirih segala.
"Rekan yang mana, persisnya?" tanya Caleb santai. "Jangan beritahu aku kalau sang petinggi pura-pura tidak tahu tentang semua Warden selalu suka yang namanya mengulur waktu, bahkan Saccan sekalipun."
Melv bergumam-gumam. "Kecuali Rowell."
Caleb membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Batal menyangkal. "Kecuali Rowell. Ya."
Kali ini Melv menghela napas. Punggungnya bersandar lemas ke sofa. "Kau tahu kalau yang dimaksud Petinggi A itu Ruviane, bukan?"
"Semua orang tahu kalau si bungsu itu kurang disukai di kalangan petinggi."
"Ah, andai mereka tahu sebenarnya aku ingin seperti Ruviane .... Maksudku, bukan dari sisi hobinya yang suka menyeringai nakal sampai karismanya tumpah ruah di hadapan para gadis, tapi semacam ketidakpeduliannya."
Samar-samar Caleb bisa mendengar suara Anya yang tengah heboh entah di mana. Barangkali sudah bertemu dengan Aletta. Insting hewaninya—kalau dia boleh bilang—tidak bisa diam bila sang nona pergi jauh-jauh. Terlebih lagi saat nonanya pergi mengunjungi Aletta yang sebenarnya tidak boleh dikunjungi sembarangan. Namun, apalah daya, tidak ada yang bisa menghentikan seorang Alice membangun relasi dengan orang lain.
Rambut putih Caleb yang panjangnya mencapai bawah leher tampaknya memang sudah dirancang untuk tidak mengalami perubahan warna akibat repot menjaga gadis hiperaktif selama beberapa musim panas. Atau mungkin juga agar orang-orang tidak bisa melihat betapa lelahnya dia ketika berhadapan dengan Melv dan bahan-bahan gosip yang hanya memperburuk kepercayaan diri si pemuda kucing malang.
Tidak heran para petinggi selalu mencekokimu dengan rumor buruk, Melv. Mereka menikmati kelemahanmu, pikirnya penuh rasa simpati.
"Dia bukannya tidak peduli, dia hanya pintar dengan caranya sendiri yang sering membuat orang sebal padanya." Caleb berdecak lidah, menatap ujung kertas yang terlipat kecil. "Karena itu belajarlah untuk menjadi keras kepala yang sopan sepertiku, Melv. Tengah-tengah. Jangan terlalu menurut atau hidupmu akan seteratur si gagak kesayangan para petinggi. Dan jangan sekeras kepala si kelinci juga atau reputasimu akan seburuk miliknya di mata para petinggi."
Melv menoleh, menyaksikan Caleb yang secara ajaib masih bisa fokus menulis surat selama memberinya ceramah. "Kau terdengar seperti penjilat," komentarnya tanpa berpikir dua kali.
Harus Caleb akui, meskipun kepercayaan dirinya agak cetek dibandingkan Warden yang lain, Melv punya mulut tertajam nomor dua setelah Ruviane.
"Bukan penjilat, Melv. Tapi cara pintar agar dirimu tetap berada di garis aman."
"Garis aman apanya," gumam Melv lagi. Kali ini sungguhan sambil bermalas-malasan di ruang kerja orang. Kaki kanannya dia tekuk, sedangkan kaki kirinya dijadikan tumpuan. Kedua tangannya terentang di atas sandaran sofa selama kepalanya menengadah ke belakang. Santai betul gelagatnya seakan-akan di ruangan sendiri.
Caleb tidak tertarik untuk mengusirnya, jadi dia membiarkan pemuda itu memejamkan mata di sana—selama tidak mengganggunya.
Dalam beberapa saat ketenangan mengalir ke dalam ruangan itu. Hanya diisi oleh riuhnya salju di luar jendela dan dilengkapi oleh suara kayu bakar yang bergemeretak.
Sampai tiba-tiba jeritan Anya—yang Caleb kenali sebagai pertanda aman, persisnya bukan baik atau buruk—masuk ke pendengarannya lagi.
Tepat sedetik setelah jeritan heboh Anya, Melv di atas sofa terbangun dengan mata kuning emas yang nyalang. Entah karena dikejutkan jeritan nonanya atau terbangun karena hal lain, Caleb tidak tertarik untuk mencari tahu.
"Caleb."
"Ya?" Ini kedua kalinya Caleb dipanggil dengan intonasi yang aneh. Entah harus seperti apa pria itu bereaksi. "Merasakan sesuatu, kucing besar?"
Melv berganti posisi; duduk membungkuk, menatap sepatunya yang hitam mengilap. "Langkah kaki Ruviane," lirihnya.
Kali ini Caleb tertarik.
"Sungguh?"
"Dan bunyi gemerincing Isabel."
Akhirnya. "Bagus. Sepertinya dialah tamu pentingnya karena aku mendengar Anya tidak berhenti berseru girang."
Melv melotot. "Itu ... apa itu artinya gadis baru Ruviane juga datang?"
"Bisa jadi. Oh, tunggu dulu. Ada aroma baru juga selain kamomil." Caleb berdiri, mengenakan setelan jas hitamnya, dan diakhiri dengan mengambil topi tinggi berwarna serupa dari gantungan. Langkahnya melambat begitu tengah mengendus udara kosong, mencoba mengenali aroma orang baru. "Tercium seperti ... jeruk nipis—ah, bukan, itu Carol. Siapa yang satu lagi?"
Melv duduk diam menunggu Caleb yang masih mencoba mengendus udara.
"Oh," tukas Caleb kemudian. "Wangi anyelir."
"Anyelir ...." Melv bergumam, kemudian terkekeh geli saat membayangkan sesuatu. Dia mendongak ketika Caleb lewat di belakangnya. "Kau serius? Setelah Ruviane berbau kamomil, Alice-nya berbau anyelir? Apa-apaan mereka? Aromaterapi?"
"Jangan remehkan indra penciuman anjing penjaga." Caleb menyeringai sebelum mengenakan topi tingginya. "Ayo keluar, Melv. Waktunya menyambut pasangan aromaterapi yang satu ini. Lalu setelah itu kita harus berterima kasih karena tidak akan ada lagi dari kita yang merasakan stres, sebab wangi mereka akan menjadi obat penenang berjalan kita."
Alih-alih menyusul, Melv justru terbahak keras di atas sofa.
- • -
"Uh-oh. Itu tidak terlihat bagus."
"Aku setuju. Nona, kakimu."
"Sedang kucoba." Esme mengerang, berusaha membebaskan kakinya dari jeratan salju. Sesekali gadis itu meringis, kemudian dilanjutkan dengan sumpah serapah. Kerepotan sendiri dengan setelan musim dingin, tetapi masih sadar diri karena tanpa setelan itu dia tahu bahwa sekujur tubuhnya bisa terancam mati rasa.
Setiap orang memiliki pengalaman yang memalukan, begitu pula Esme. Hal yang memalukan pun tak selamanya muluk-muluk. Hal yang sederhana pun bisa menjadi hal yang memalukan dalam hidup.
Misalnya saat ini.
Di bawah tatapan Ruviane dan Carol, Esme berusaha mengeluarkan kakinya yang satu lagi ketika kaki satunya justru baik-baik saja. Apalah arti dari sebuah sepatu bot bagus sebagai hadiah ulang tahun bila akhirnya membuatmu tersangkut di salju. Satu-satunya hal yang Esme syukuri hanyalah tidak adanya Feodora yang sudah pasti terbahak keras melihatnya menderita. Sudah banyak cara dia lakukan secara individu, tetapi semuanya berujung tergelincir sampai wajahnya terjerembap masuk ke dalam tumpukan salju.
Esme tidak tahu persis di mana kakinya tersangkut, tetapi dia punya asumsi bahwa yang menjebaknya saat ini adalah semak-semak yang tidak memiliki belukar, atau mungkin tersangkut di tempat yang awalnya berupa lubang di tengah jalan dan sekarang menjadi gundukan bukit salju.
Gadis itu mengerang, mencoba menarik diri lagi, tetapi nahas, dia tetap bergeming. Carol harus membalikkan tubuh untuk menyembunyikan semburan tahan tawa—kedua bahunya yang berguncang menjadi saksi bisu, tentu saja.
Sambil menahan malu, Esme mengangkat wajah. Hendak meminta pertolongan kepada Ruviane yang menyeringai geli melihat gelagatnya sejak tadi.
"Butuh bantuan?" tanyanya.
Paham bahwa itu ejekan ringan, Esme mengerang, menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangan lalu menunduk dalam-dalam. "Aku ingin pulang."
"Kita baru sampai, Nona. Ayo kuatkan dirimu." Ruviane melangkah mendekat ke belakangnya, melihat posisi Esme sejenak sebelum mengaitkan tangannya ke bawah lengan Esme dan bersiap mengangkatnya seperti anak-anak. "Sebelumnya maafkan aku bila posisinya tidak menyenangkan. Nah, sekarang relakan dulu sepatumu di dalam sana, luruskan kaki, dan ayo tarik dirimu juga dalam satu, dua, tiga—wah, gadis pintar. Lihat? Ini mudah."
"Berhenti menyebutku begitu," sungut Esme sambil menarik bokongnya mundur. Kini dia cemberut melihat kakinya yang bebas kini hanya beralaskan kaus kaki. Sepatu bot dari Feodora masih tersangkut di dalam.
"Sudah kuduga, bukan hanya aku yang tidak suka panggilan semacam itu." Carol masuk ke dalam obrolan. "Kutebak rasanya seperti peliharaan, bukan? Rasanya kau ingin bilang, Aku memang pintar sejak dulu, dasar tukang gombal."
"Sayangnya, Carol, aku bukan tukang gombal." Ruviane menjulurkan tangannya ke dalam lubang salju, kemudian menarik keluar sepatu bot Esme dari dalam sana. Berulang kali dia guncangkan sepatu itu untuk menjatuhkan salju dan memastikan bahwa bentuknya masih sama seperti yang dia lihat tadi pagi. Setelah yakin aman, dia arahkan sepatu itu ke arah kaki nonanya yang bebas.
Esme memang diajari untuk berperilaku sopan dan santun kepada orang asing. Setelah dibantu keluar dari tumpukan salju dengan sepatu yang selamat, dia akan mengenakan sepatunya sendiri lalu berterima kasih.
Namun, perilaku Ruviane entah bagaimana memancing refleksnya untuk menjulurkan kaki dan membiarkan pemuda itu mengenakannya sepatu bot.
Begitu sepatu sudah masuk setengah jalan, gadis itu baru mengerjap ditampar realita.
Esmephia Sonata, kau baru saja melakukan pemanfaatan SDM secara ilegal, pikirnya seraya mencoba untuk bangkit berdiri. Ada niat di dalam hatinya untuk meminta maaf yang sopan, tetapi yang keluar dari mulutnya justru, "Di mana kita?"
"Taman bunga Istana Putih. Letaknya di samping istana. Bisa kau lihat dari bentuk pintu yang tidak begitu megah di depan sana." Ruviane menjawab, menawarkan lengannya sebagai tumpuan agar Esme berdiri dengan lebih mudah. "Ada banyak penjaga di halaman depan, para petinggi juga hobi pamer wajah di sana, agaknya bahaya. Kalau kita mendarat langsung di ruang kerjaku, habis berantakan semuanya."
Esme ber-oh panjang. Manggut-manggut tanda paham.
"Omong-omong, terima kasih atas bantuanmu, Carol. Entah apa yang terjadi bila kami tidak mampir ke tempatmu," ucap Ruviane. Kali ini tulus.
"Tidak, aku yang seharusnya berterima kasih. Yang sebelumnya itu mengejutkan, tapi tidak membuatku heran. Sekarang aku punya impian untuk mendepak kepala anak sialan itu. Entah kapan persisnya, tapi doakan saja semoga lebih cepat." Wanita itu mengangguk sopan, seolah tengah berhadapan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. "Kalau begitu, sekarang aku pamit. Berkunjunglah ke tempatku saat kau senggang, Esme. Tidak perlu mengajak kelincimu. Oke?"
Apa aku akan jadi sibuk di sini? Esme berkedip cepat seraya melepaskan pegangan dari lengan Ruviane. Walaupun masih tidak begitu paham dengan apa yang terjadi, dia tetap mengangguk karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan merendahkan pemuda di sampingnya itu dengan percuma.
"Akan kulakukan," katanya menyanggupi.
"Hei, itu jahat."
Tentu saja Esme mengabaikannya. "Hati-hati di jalan, Carol."
Carol tersenyum miring. Selanjutnya dia menarik napas, menjentikkan jarinya keras-keras, dan ledakan kecil seketika terdengar dengan bunyi POOF! yang lucu. Asap putih bercampur hijau dan ungu datang, sosok Carol menghilang. Lenyap tak bersisa bagai atraksi sulap yang pernah Esme lihat di televisi.
Kali ini Esme yang menarik napas panjang. Berdoa sungguh-sungguh di dalam hati semoga cepat terbiasa dengan sebaran anomali yang baru.
"Ayo?" ajak Ruviane, sekali lagi menawarkan lengan. "Tadinya aku ingin menyembunyikanmu di ruanganku, tapi sepertinya beberapa orang telah menyadari kedatangan kita lebih dulu."
Esme tidak ingin berpegangan lagi, tetapi dia menolak untuk jatuh ke lubang yang sama. Jadi dia cukup menjumput lengan jas Ruviane sambil belajar seimbang sendiri.
Perasaannya mendadak khawatir ketika melihat beberapa orang sudah berdiri agak jauh di depan mereka. Tidak terlihat seperti penjaga, tetapi auranya membuat siapa pun segan mendekat dengan penampilan berantakan.
"Apa itu kabar buruk?" Esme bertanya.
Ruviane bergumam panjang sebelum akhirnya menoleh dan membiarkan netra rubinya bersibobrok dengan mata safir Esme. "Tidak juga," jawabnya. "Baik atau buruknya akan kubiarkan kau yang menilai mereka sendiri. Yang jelas mereka kawan, bukan lawan."
Esme mengernyit. Terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak ingin kebingungan sendiri. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melangkah pelan-pelan sambil menata rambut sebisanya dengan satu tangan.
Ah, betapa menyedihkannya dia sekarang. Pita birunya hilang, kepangannya lepas, dan sekarang rambut pirang bergelombangnya pasti tampak berantakan. Syal dan tas selempangnya hilang entah ke mana. Mungkin tertinggal di antara puing-puing kedai makanan Carol. Benda yang melekat padanya tersisa mantel kusam, sweter, celana panjang sewarna langit malam, kaus kaki tebal, dan sepasang sepatu bot.
Sebelumnya Esme mengira bahwa Ruviane tampak aneh karena bersebelahan dengannya yang berpakaian kasual. Sekarang gadis itu merasa bahwa dirinyalah yang terlihat aneh.
Di antara orang-orang itu, dua lelaki di antaranya mengenakan jas yang sama (dan bahkan topinya pun sama!), sedangkan dua gadis di sebelah mereka mengenakan potongan pakaian yang anggun. Mirip gaun, tetapi terlihat lebih kasual. Mantel jubah yang para gadis itu kenakan tampak mengesankan. Motif rumit yang menghiasinya membuat Esme berpikir bahwa dia sungguhan jatuh ke negeri dongeng yang fantastis.
Si gadis berambut pendek menerjang maju. Hampir tergelincir tepat setelah pria berambut putih menyerukan, "Pelan-pelan, Anya!"
Esme mengerjap. Pandangannya seketika tertarik pada simbol keriting kecil yang sering dia lihat pada kartu remi, terletak tepat pada tulang pipi sebelah kiri si gadis manis. Senyum lebarnya yang cerah menawan membuat Esme secara instan berpikir bahwa dia gadis baik.
"Oh, astaga. Kau benar-benar secantik musim dingin. Persis seperti yang dikatakan Aletta," selorohnya girang sampai tertawa-tawa. "Selamat datang di Negeri Ajaib! Senang melihatmu tiba!"[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top