- • Another Rabbit Hole • -
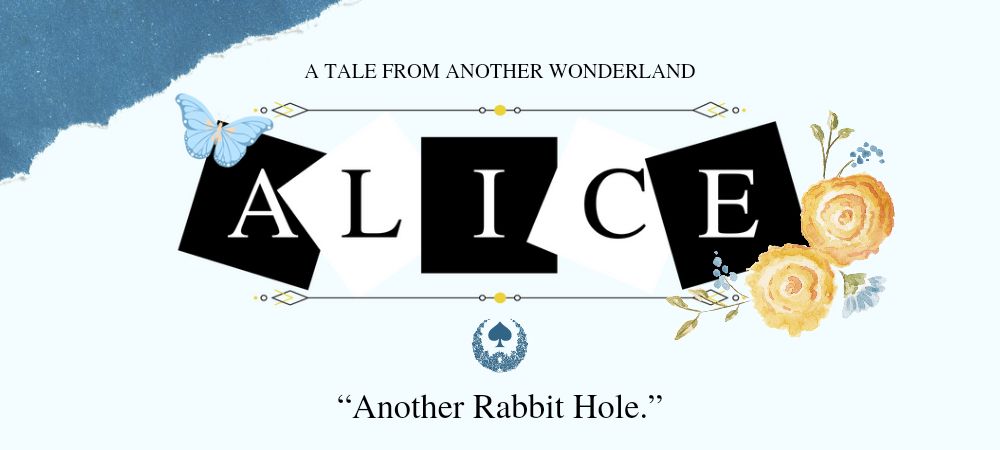
Esme mengangkat kedua alisnya serempak ketika Momma Primrose berlari tergopoh-gopoh keluar dari dapur. Ketika dia melihat beliau mengambil sebuah kotak—berani taruhan isinya obat-obatan—kemudian berderap ke dapur lagi, suasana di ruang tamu rumah keluarga Anshumant seketika menjadi tidak beres.
Jangan bilang kalau anak itu terluka serius? Esme mengulum bibir. Gelisah karena terlambat peka terhadap kesulitan tuan rumah.
Isabel tampaknya menangkap gelagat itu. Buktinya kini dia tersenyum kecil dengan tenang ketika mata safir Esme terarah kepadanya.
"Tenang, Nona. Saya yakin tidak ada masalah serius di dapur. Ini hanya tentang tata krama."
Namun, Esme kesulitan untuk berhenti melirik dapur.
"Tetap tidak terdengar bagus di telingaku," gumamnya.
Isabel terkekeh seraya berpangku tangan. "Kalau saya berada di posisi mereka, sudah pasti saya juga akan melakukan hal serupa—menumpahkan teh, misalnya."
Mustahil adalah kata pertama yang timbul di benak Esme.
Makhluk hidup seaneh apa pun di Negeri Ajaib pasti akan setuju bahwa sosok Isabel yang suka sekali warna hijau itu adalah contoh nyata dari pribadi elok tanpa cela.
Menumpahkan teh adalah hal mendasar yang amat mustahil Isabel lakukan.
"Isabel menumpahkan teh adalah salah satu keajaiban di dunia. Aku akan melotot selama sepuluh menit kalau sampai itu terjadi," kelakar Esme. Keresahannya menyurut. "Terima kasih. Aku sedikit terhibur."
Dan sekarang aku juga menyadari banyak hal. Esme bersandar pada sofa, menunduk menekuri renda kemeja seiring pikirannya mengembara.
Tentang sesi ramah tamah di halaman sebelumnya, pelayanan secepat kilat, bahkan sampai repot-repot memanggil anak-anak dari lantai atas hanya untung menyiapkan minuman; Momma Primrose tahu betul dengan siapa dia berhadapan.
Alice Musim Dingin adalah sebutannya—mungkin.
Berdasarkan sebutan "Alice Musim Panas" yang pernah ditujukan Ruviane kepada Anya McDough, sudah pasti sebutan untuk Esme tak jauh berbeda dari itu.
Datang ke negeri orang di antah-berantah dan menjadi sosok yang diagung-agungkan nan dinantikan; Esme tiba-tiba merasa beban imajiner yang bertengger di bahunya bertambah berat.
Apa yang akan dan harus kulakukan selama menjabat titel aneh itu? Gadis itu bergumam-gumam, kini iseng mengetuk-ngetuk permukaan korset. Mengatur cuaca? Membuat stok minuman dingin setiap ada acara? Belajar sihir es? Menjaga suhu musim dingin tetap waras?
"Nona." Isabel memanggil, terkekeh lagi. Jari telunjuknya mengarah ke keningnya sendiri. "Kening Anda kusut lagi."
Esme mengerjap. Sambil diliputi rasa malu dia mengusap keningnya perlahan. "Kau tahu, ada banyak pertanyaan aneh di kepalaku."
Mendengar nonanya berkata demikian, Isabel segera menggeser posisi duduk. Posturnya mendadak sempurna bak orang bangsawan. Segala gesturnya alami. Benar-benar alami. Saking alaminya, Esme bertekad akan menanyakan silsilah keluarganya kepada Ruviane nanti.
Masih dengan keelokan dan tatapan teduh, Isabel berkata, "Silakan, Nona. Saya mendengarkan."
Esme turut mengubah posisi duduknya, mencoba untuk mengikuti cara Isabel walau tak seberapa.
"Oke," dia memulai. "Kalau aku sudah resmi menjadi Alice, apa yang harus kulakukan?"
Alih-alih menjawab seperti yang dijanjikan, Isabel justru memilih untuk mengangkat alis. Dari segi mana pun dia jelas tampak terkejut.
"Apa ... Tuan tidak menjelaskan soal itu?"
Netra safir Esme melirik ke sembarang arah. Gadis itu tengah mencoba mengingat-ingat. Sudah resah dengan kedua anak tuan rumah yang sedang kacau di dapur, kini bertambah pula beban pikirannya dengan pertanyaan Isabel.
Apalagi bentuk pertanyaannya terdengar seolah hal itu tidak sepatutnya terjadi.
Kedua alis Esme kini menukik tajam, hampir-hampir bertaut. Pada awalnya dia memaklumi segudang informasi yang pemuda itu rahasiakan. Hubungan mereka sebelum hari ini memang masih luar biasa asing.
Namun, bila kondisinya sudah seperti sekarang—Esme berhasil dibawa ke negeri asing tanpa memberontak, tetapi tidak diberikan informasi yang sepadan—namanya sudah keterlaluan.
Apalagi ketika ditilik lagi berbagai kemungkinan buruk bila Esme tidak datang ke sini; rasa-rasanya Esme telah dirugikan.
Lalu dengan inikah pemuda itu membayarnya? Dengan segudang tanda tanya?
Ruviane de Anshumant, Esme mengulas senyum sinis, tunggu sampai aku kembali lalu akan kuhajar kau di ulu hati.
Bila ternyata jauh di sana Ruviane mendadak bersin atau bulu roma di tengkuk lehernya tiba-tiba berdiri, Esme tidak akan peduli.
"Hoh, hampir semua Alice yang berada di bawah tanggung jawabnya kebingungan sepertimu. Sifatnya yang satu itu memang sedikit merepotkan." Momma Primrose datang membawa senampan sajian. Aroma manis menguar bersamaan dengan melayangnya kepulan uap di cangkir. "Maaf karena aku tidak bisa menyiapkan sajian yang lebih layak dari ini. Toko-toko mulai lebih sering tutup sejak cuaca semakin memburuk."
Sepiring biskuit diturunkan dari nampan. Tiga cangkir diperlakukan serupa. Esme menatap cangkir dan dalam sekejap wajahnya berubah sumringah.
Cokelat panas!
"Kau terlihat senang. Syukurlah." Momma Primrose tergelak sebelum mengambil cangkir terdekat. "Tadinya aku ingin menghidangkan teh, tapi sepertinya Ruv-Ruv sudah memberimu setangki penuh di tempat kerjanya."
Ada sekelebat perasaan ingin melindungi harga diri Ruviane dalam gejolak batin Esme, tetapi tidak.
Esme harus melakukan yang sebaliknya. Dia harus memperluas relasinya agar tidak selalu menempel dan tanpa sadar hidupnya malah ketergantungan dengan pemuda itu.
Harus.
"Dia meminumnya seakan tidak ada hari esok." Esme berkata sedih. "Ginjalku menangis."
"Hoh, demi wortel!" Momma Primrose berseru keras, mulai tertawa-tawa. "Aku sudah pernah mengatakan ini padanya, tapi tolong tegur dia bila porsi tehnya dalam sehari mulai tidak waras. Teh memang menenangkan, tapi kalau diminum berlebihan akan menjadi sumber stres juga."
Esme manggut-manggut. Dia baru tahu soal itu, tetapi dia memegang prinsip segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
"Eh, kenapa kalian masih diam saja?" Kedua mata besar Momma Primrose berkedip lucu. "Silakan nikmati minumannya selagi masih hangat. Ayo, Nona Muda. Kau juga, Isabel. Katakan saja padaku kalau kalian ingin tambah."
Diawali dengan senyum sopan, Esme meraih cangkir bagiannya perlahan, diikuti oleh Isabel yang sama sekali tidak terlihat kaku dengan tata krama bertamu. Sambil membawa cangkir mendekati bibir, Esme tidak bisa menahan diri untuk melirik ke sekitar.
Di saat itulah, kedua anak yang sebelumnya ribut di dapur perlahan-lahan keluar tanpa suara.
Si anak laki-laki berjalan lebih dulu. Menunjukkan kepada dunia tentang mata kelamnya—yang nyaris sewarna arang—memiliki intensitas yang kuat ketika menatap sesuatu. Siapa pun dapat melihat binar-binar kecerdikan di sana. Rambutnya yang kecokelatan terlihat tebal meskipun dari jauh.
Setelah dilihat-lihat, perawakannya memang seperti anak yang baru menginjak usia remaja belum puber. Hanya saja anak itu lebih tinggi dan lebih tegap dengan kulit sawo matangnya. Kalau saja sekarang bukan musim dingin, barangkali dia akan mengenakan pakaian yang lebih menonjolkan kaki panjang itu.
"Hoh, akhirnya."
Esme spontan melirik Momma Primrose yang tampak lega atas kedatangan dua anak itu.
"Bagaimana tanganmu?" Momma Primrose bertanya.
Si anak laki-laki tak kunjung membuka mulut, tetapi terdengar jawaban, "Baik-baik saja, Momma."
Penasaran, Esme menelengkan kepala, mencari-cari sumber suara. Sahutan kecil itu mengalun pelan, bak seruling yang ditiup ragu-ragu. Mustahil seorang anak laki-laki gagah begini memiliki suara sehalus seruling ....
Oh, itukah dia?
Di belakang si anak laki-laki, seorang anak perempuan mencuri-curi pandang ke arah para tamu di atas sofa. Dikarenakan tingginya yang hanya mencapai telinga si anak laki-laki, dia bisa bersembunyi di balik punggung saudaranya dengan leluasa.
Namun, seleluasa apa pun dia dapat bersembunyi di sana, warna rambutnya yang putih keperakan tampaknya sulit untuk diajak bekerja sama. Dia terlihat amat mencolok. Begitu dia mengintip dari bahu si anak laki-laki, mata safir Esme bertemu dengan mata birunya yang sebening lapisan kaca. Sedetik tampak mengerikan, di detik selanjutnya tampak luar biasa indah.
"Kami minta maaf atas keributan tadi," ucap si anak laki-laki seraya membungkuk sopan dengan luwes.
Masih membungkuk, dia sempatkan diri untuk menyenggol si anak perempuan di belakangnya menggunakan siku.
Maka terlonjaklah anak perempuan itu, tanpa pikir panjang langsung buru-buru pindah ke sebelah saudaranya untuk turut membungkuk. Kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuh, dengan salah satunya berbalut perban. Gerakannya tampak dua kali lebih kikuk.
"Maafkan kami," cicitnya.
Esme mengulas senyum dua makna: merasa lucu karena kelakuan dua anak yang tidak dia kenal, sekaligus merasa senang karena akhirnya dia menenggak cokelat panas.
"Tidak perlu sampai begitu," katanya. Tanpa dapat ditahan, matanya melirik tangan si anak perempuan yang berbalut perban. "Apa tanganmu baik-baik saja?"
Si anak perempuan sontak berdiri tegap. Ketegangan melintas di wajahnya. Entah apa persisnya isi pikiran anak itu. Mungkin takut bersikap tidak sopan, atau mungkin takut dihajar oleh tangan kosong tamunya karena telah gagal menyeduh cokelat panas. Mata besarnya mengerjap cepat, tak terhitung berapa tepatnya. Berkali-kali dia melirik anak laki-laki di sebelahnya, bak meminta pertolongan tanpa suara.
"Tangannya baik-baik saja." Si anak laki-laki angkat suara penuh percaya diri. "Terima kasih sudah bertanya. Sekarang kami—"
"Ekhm." Momma Primrose berdeham. "Anak-anak. Perkenalan?"
Si anak laki-laki bergegas tutup mulut hingga bibirnya tinggal segaris, sedangkan si anak perempuan mendadak resah di tempat.
Mampus kita—kurang lebih begitulah kata-kata bisu yang terpancar dari wajah mereka.
Bertolak belakang dengan Esme; gadis itu justru tersenyum lebar sampai kedua ujung matanya ikut tertarik. Senyumannya terlihat tenang, ramah, dan profesional. Padahal isi kepalanya sedang terpingkal hingga terjungkal.
Esme paham betul perasaan kedua anak ini. Dia dan Peter sering berada di momen yang sama ketika ayah atau ibunya kedatangan tamu.
"K-kami benar-benar minta maaf!" Kali ini si anak perempuan yang angkat suara lebih dulu. Keberanian di dalam dirinya terpantik setelah melihat tamu mereka tersenyum lebar. "Namaku Jeremiah. Silakan panggil aku Remi. Dan ini Tidore."
Anak laki-laki itu mengangguk kecil. "Suatu kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan Anda."
Esme mengayunkan telapak tangannya naik-turun. Dia ingin mengatakan, Bung, aku masih kesulitan mencari pasangan kaus kakiku sendiri di hari Senin yang cerah. Aku bukan orang terhormat. Tidak usah terlalu formal begitu.
Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Aku Esme. Senang bertemu dengan kalian."
Remi mengangkat tangan. Esme menatapnya.
"Boleh aku memanggilmu 'kakak'?"
Tetaplah tersenyum meskipun kebingungan, kata hati Esme. "Boleh, kurasa?"
Agak tidak terduga, Remi tersenyum amat lebar sebagai respons. Tubuhnya yang manis mungil bergoyang pelan, menyenggol-nyenggol sosok tinggi Dore yang tetap bergeming di sebelahnya.
Esme kemudian menoleh ke arah Isabel. Bertanya-tanya tentang apa yang harus dia lakukan sekarang.
Kurang-dari-satu-detik kemudian, mata cerah Isabel menyadari tatapan bertanya itu. Bak seorang profesional, tak butuh waktu lama baginya untuk segera mengerti apa maksud sang nona.
Isabel berdeham sampai atensi kedua anak itu beralih kepadanya. "Sudah lama sekali tidak bertemu kalian. Apa kabar? Terakhir kali kuingat tinggi Dore masih sampai mata Remi."
Remi melirik sinis ketika Dore menyeringai kepadanya. "Yeah, itu karena belakangan ini dia diam-diam sering menghabiskan sebotol sus—"
"Maksud Remi adalah kabar kami sangat baik." Dore buru-buru menyela dengan senyum sopan. "Ah, ya, setelah ini kami akan pergi ke rubanah. Sudah waktunya untuk bersih-bersih."
Sudah susah payah Isabel mengubah topik dan mencairkan suasana, Esme malah kembali mengambil alih. Kedua alisnya terangkat serempak. Air wajahnya sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia tertarik.
"Ada rubanah?" tanyanya antusias.
Dore hanya menatapnya lurus-lurus—seolah tengah melakukan penilaian, sedangkan Remi mengangguk bersemangat.
Di atas sofa, Momma Primrose menarik senyum dengan kedua tangan terlipat di pangkuan. "Kau boleh ikut dengan mereka kalau kau ingin. Di bawah sana memang agak dingin, tapi anak-anak akan memberitahumu cara untuk tetap hangat. Hoh, percayalah. Mereka ahlinya."
Mata safir Esme berkedip cepat. Dia benar-benar antusias. "Isabel, kau ikut?"
Isabel menjawab pertanyaan itu dengan gelengan. Sejenak tatapannya jatuh ke arah Momma Primrose. Seolah-olah ada sesuatu yang sudah dia rencanakan sebelumnya.
"Sayangnya ada yang harus saya bicarakan dengan Momma Primrose, kalau Nona tidak keberatan."
Meskipun sedikit kecewa, Esme tidak menunjukkannya terang-terangan.
Pasti tentang sesuatu yang tidak kumengerti. Mengulum bibirnya, Esme mengangguk takzim. Yah, lagipula aku datang ke tempat ini untuk bersantai.
Begitu pergulatan batinnya berakhir, Esme beralih kepada dua anak yang masih berdiri menanti keputusan. Sekali lagi dia tatap bolak-balik kedua anak itu, lalu barulah Esme bangkit dari sofa.
"Baiklah," katanya penuh semangat. "Satu hal yang harus kalian ketahui, aku suka petualangan."
- • -
"Apa Kakak datang dari Dunia Atas? Bagian mana?"
Sebutlah nilai Esme di mata pelajaran geografi selalu memuaskan, tetapi bagaimana caranya menjelaskan detail suatu tempat yang bahkan tidak ada di peta negeri ini?
Yah, kujawab sejujurnya saja, deh. "London. Pernah mendengarnya?"
"Oh, ya!" Di luar dugaan, Remi menyahut girang. "Aku memang belum pernah ke sana, tapi Ruv-Ruv bilang kalau London adalah jantungnya Negeri Ajaib."
Mendengar itu, Esme tertegun. Hampir-hampir melamun.
Sepertinya hari ini adalah hari di mana dia memahami banyak hal.
Alasan mengapa tampilan fisik Anya tampak lain, juga mengapa cara bicaranya mengharuskan Esme untuk diam dan mendengarkan dengan saksama agar dapat memahami kalimat yang terucap—itu karena dia bukan berasal dari London.
London hanyalah "jantung". Itu berarti masih ada banyak "organ" lain.
Apa pun asal negara mereka; seorang Alice tidak dipilih berdasarkan kategori tersebut. Ada hal yang lebih diperhatikan dalam memilih Alice untuk setiap musim, dan Esme belum mendapat gambaran sama sekali.
Harus tanya Ruviane walaupun dia menyebalkan, kata hati kecilnya.
"Kalau diizinkan," Esme bertekad, "besok-besok aku akan membawamu ke London."
Remi tertawa. Tidak menyangkal ataupun bersorak setuju.
Hanya ada beberapa bagian dari rumah keluarga Anshumant yang lantai kayunya dilapisi karpet. Yang baru Esme lihat adalah lorong utama yang mengarah ke pintu depan, ruang tamu, dan tangga utama.
Esme memiliki dua dugaan tentang hal itu. Pertama, karpet hanya digunakan sebagai formalitas ketika menerima tamu. Kedua, karpet memang sengaja tidak tersebar di mana-mana karena mungkin ada banyak anak-anak yang senang berlarian ke sana kemari.
Untuk poin kedua, Esme membagi kemungkinan alasannya lagi.
Alasan pertama: dapat membahayakan anak-anak karena khawatir tergelincir. Alasan kedua: karpet terancam cepat kotor.
Sebagai anak bungsu dari dua bersaudara yang dulu hobi berlarian sampai ribut, Esme yakin alasan nomor dua lebih besar keakuratannya.
Namun, selain tiga lokasi yang disebutkan di atas, siapa sangka bahwa ternyata lantai dapur—pada bagian bak cuci piring dan kompor beserta deretan laci—juga berlapiskan karpet?
"Pintu rubanah itu," netra safir Esme terpaku ke arah karpet, "apa ada di bawah sana?"
Alih-alih menjawab, Remi justru terkikik, sedangkan Dore mendengkus geli.
"Yah, semua orang pasti berpikir begitu, tapi sebenarnya bukan," jawab Remi. "Itulah kenapa Momma meletakan karpetnya di sana, untuk mengecoh tamu tak diundang yang berniat mengganggu kami. Terkadang mereka datang tiba-tiba, apalagi kalau Momma sedang di luar."
Kening Esme berkerut. Mengganggu mereka?
"Belakangan ini cuacanya terlalu dingin. Banyak tumbuhan yang mati membeku, sehingga rantai makanan berantakan." Dore mengambil alih penjelasan. Masih sambil berjalan memimpin ke arah meja makan. "Memang tidak banyak hewan buas yang benar-benar memakan daging di Negeri Ajaib, tapi kebanyakan makhluk besar mulai kelaparan karena krisis pangan dan akhirnya makhluk kecil seperti kami—kelinci, malah kena imbasnya."
Remi mengekor di belakangnya sambil mengangguk-angguk merana. "Kami bukan benar-benar manusia, juga bukan benar-benar hewan. Terkadang ada masanya salah satu insting kami lebih dominan. Demi bertahan hidup."
Esme bersedekap. Mendadak merenung setelah mendengar fakta pahit dari penduduk negerinya secara langsung.
Entah kenapa kedengarannya suram sekali, pikirnya.
Ketika Remi berhenti di belakang punggung Dore, Esme turut menahan langkah. Dia saksikan anak laki-laki itu membungkuk ke kolong meja makan dengan kedua alis terangkat tinggi.
Remi tiba-tiba mendongak. Tampak seperti hendak memeriksa ekspresi tamu hari ini. Sekarang mata biru jernihnya menatap Esme dengan jenaka. Sorot mata gundah gulananya hilang entah ke mana. Jelas sekali dia merasa bersemangat untuk menjelaskan hal unik tentang rumahnya.
"Itu adalah pintu untuk ke rubanah," dia memulai.
Esme mengangkat alis. Diam tertarik menyaksikan Dore mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan irama konstan.
"Kenapa harus diketuk?" tanyanya kepada Remi. "Apa pintunya tidak bisa dibuka dari luar?"
"Ada dua pintu untuk ke sana," celetuk Dore. "Biasanya kami menggunakan pintu yang ada di luar—di halaman belakang."
Remi mengangguk penuh semangat. "Ini pintu cadangan, untuk kondisi darurat. Hanya bisa dibuka menggunakan kunci dan ...." Anak itu menggantung kalimatnya dengan intonasi meninggi. Sengaja betul memancing Dore untuk melanjutkan.
"Dan sekarang kuncinya ada di dalam." Dore akhirnya menyahut.
Sekali lagi Remi mengangguk setelah saudaranya berbicara. Dia tampak amat puas.
Esme justru kebalikannya. Penjelasan si kembar entah kenapa terdengar kurang memuaskan. Seperti ada hal yang sengaja dibiarkan menjadi misteri dan tugas Esme adalah menebaknya dengan tepat.
Tatapan gadis itu perlahan-lahan berpindah ke Remi. Dua pasang netra biru akhirnya saling bertumbuk, diam membisu, sampai kemudian Remi lebih dulu memutuskan kontak begitu Esme mulai terperangah—tersadar.
"Dan tidak ada anak-anak yang terlihat selain kalian berdua di sini." Gadis itu mendesis gemas seiring pemahaman baru perlahan-lahan muncul di kepalanya. Jantungnya berdebar-debar. Bersemangat. "Jangan katakan padaku—"
"Tapi kami harus mengatakannya!" Remi tertawa kencang di atas parasnya yang lemah lembut. "Tepat seperti dugaan Kakak, anak-anak kelinci yang lain ada di bawah sana. Jumlahnya tidak banyak-banyak amat, tapi tetap bisa mengakibatkan sakit kepala kalau Kakak tidak terbiasa. Apalagi kalau mereka sudah berubah wujud menjadi manusia dan mulai memberondong Kakak dengan banyak pertanyaan ... oh, lihat! Pintunya terbuka! Bagus! Dore, aku masuk duluan, dong!"
Dore bergeser dengan tenang, mempersilakan saudarinya mengambil ancang-ancang sebelum turun.
Diiringi sorakan heboh, Remi melompat tinggi ke udara. Suara POOF! lucu beserta kepulan asap putih muncul entah dari mana. Sosok Remi seketika berganti menjadi seekor anak kelinci berbulu putih.
Sekali lagi, Esme diam terpaku menyaksikan fenomena lubang kelinci. Satu hal yang membedakan dengan yang pertama adalah lubang kelinci yang satu ini benar-benar digunakan oleh para kelinci. Dibandingkan dengan yang Esme lalui sebelum tiba di Negeri Ajaib, lubang yang satu ini tidak terlihat magis sama sekali.
Begitu Remi benar-benar lenyap ditelan lantai, Esme mengalihkan tatapan penuh tanya ke arah Dore—yang dibalas dengan tatapan serupa.
"... Apa?" tanya Dore skeptis.
Esme melipat bibir. Berusaha meneguhkan hati ketika melihat lubang pada lantai bukan main gelapnya. Hanya ada tiga anak tangga yang terlihat jelas dan dua anak tangga seperti di ambang terang dan gelap. Setelah itu sisanya ditelan kegelapan. Berapa total jumlah persisnya; Esme tidak tahu.
Momen itu sejenak mengingatkan Esme pada apa yang terjadi pada lantai loteng rumahnya tempo hari.
Juga sedikit mengingatkannya pada Oliver.
Serta Feodora, Leonard ... dan juga Peter.
Gawat. Esme tersenyum miring. Sepertinya aku merindukan kalian.
Namun, yah, petualangan harus terealisasikan. Esme bertekad dia tidak akan pulang sebelum dia puas.
Penuh hati-hati gadis itu menjulurkan kepala ke tepi lubang, berusaha mencari dasar atau anak tangga berikutnya. Namun, gelap total. Tidak terlihat apa pun. Pelan-pelan Esme menarik diri. Duduk diam di tepi lubang.
Di dekatnya, Dore tak kunjung melepaskan tatapan.
"Ada masalah?"
"Ya, dan itu kau." Gadis bersurai pirang itu melancarkan kalimat tajam dadakan tanpa disaring. "Apa ini hanya perasaanku atau para lelaki Anshumant memang hobi menatap wanita lekat-lekat?"
Dore menyipitkan mata. "Aku begitu?" Anak itu bergumam, terdiam sebentar, lalu menambahkan, "Dia begitu?"
"Oh, kau harus melihatnya langsung, Sayang. Dia menatapku begitu. Setiap saat." Dengkusan pendek keluar dari hidung bangir Esme. "Katakan padaku, apa ada anak tangga lagi di bawah sana atau aku harus melompat dan berubah menjadi kelinci seperti saudarimu tadi?"
"Dasarnya tidak jauh." Dore menjawab tenang. "Kelihatannya mungkin mengerikan, tapi nanti kakimu akan langsung menemukan tempat berpijak. Total anak tangganya ada tujuh. Kalau kau merasa tidak yakin, silakan melompat terjun. Sungguh, hak sepatumu tidak akan patah hanya karena terjun sejauh itu."
Esme terperangah. "Wow, kau pintar bicara, ya."
Dore melengos. "Lepas saja sepatunya kalau masih khawatir."
Oh, sungguh, tidak ada perasaan yang lebih memuaskan daripada melihat orang yang menjengkelkan akhirnya jengkel juga dengan sikap lawannya. Lihatlah. Esme terkekeh puas melihat Dore jengkel setengah mati.
"Tidak, trims," tolak Esme penuh percaya diri. "Aku yakin sepatu buatan Negeri Ajaib pasti anti patah."
"... Aku tidak bilang begitu."
"Aku yang bilang begitu. Sudah. Hus. Diamlah sebentar."
Maka Esme mulai mengangkat sedikit roknya, berhati-hati menapaki anak tangga, tak lupa seraya merapal doa dan berhitung di dalam hati.
Satu, dua ....
Esme menarik napas. Bersiap menyambut kegelapan.
Tiga, empat ....
Keningnya berkerut-kerut.
Lima, enam ....
Astaga. Ini tidak sehat untuk jantung Oma. Esme merapatkan bibir, mulai khawatir. Tujuh, delap—oh?
"Kenapa kau menutup mata, Kak?"
Pertanyaan itu memancing Esme untuk membuka mata, dan itulah yang dia lakukan. Meskipun remang—nyaris gelap, harus Esme akui—dia tetap dapat melihat terangnya mata biru Remi tengah menatapnya penuh tanya.
Tatapan Esme kemudian turun kepada kedua kakinya yang sukses memijak permukaan kayu. Sesaat dia tenggelam dalam pikiran lucunya. Ada perasaan bodoh dan lega yang lewat sekilas.
Wah, benar-benar tujuh anak tangga.
Barulah setelah itu bunyi ketukan langkah terdengar dari atas. Kaki jenjang Dore muncul. Esme menyingkir. Dengan senang hati memberikan tempat agar dia dapat mendarat dengan benar.
Sebelum benar-benar tiba di permukaan rubanah, anak itu meraih lantai kayu di atas sana (atau Esme harus menyebutnya 'pintu'?) dan menutupnya kembali sampai rapat. Di tengah gulita, terdengar bunyi kunci diputar bersamaan dengan bunyi tombol ditekan.
Ruangan itu seketika terang benderang, menampilkan Remi tengah berdiri tepat di sebelah sakelar lampu.
Esme mengerjap-ngerjapkan mata safirnya dan terperangahlah dia pada akhirnya. Terpana dengan suasana ruangan di depan sana—di ujung lorong pintu kedua ini—yang terlihat modern, tetapi juga terlihat kuno.
Karpet bermotif digelar di tengah ruangan, ditimpa oleh dua sofa tunggal yang bahkan dari jauh pun terlihat super tebal dan empuk. Ada banyak bantal di sana. Bertebaran di lantai bersama mainan dan buku-buku bersampul kulit. Di tepi ruangan, berjajar rak buku dan kotak mainan. Begitu Esme mengambil beberapa langkah lebih maju, dia dapat melihat sebuah meja lingkaran dengan beberapa kursi di sisi lain ruangan yang tadi terhalang dinding lorong. Benar apa kata Momma, suhu di tempat itu lebih rendah daripada di atas. Tidak ada perapian, tidak ada penghangat ruangan.
Mungkin karena mereka kelinci. Begitulah kepala pintar Esme menyimpulkan.
"Apa kau siap bertemu dengan anak-anak yang lain, Kak?" Remi tersenyum lebar sampai deret gigi atasnya tampak jelas. "Aku dan Dore yang paling tua di sini. Jadi kau harus menyiapkan mental dan fisik sebelum berhadapan dengan yang lain. Beberapa pendiam, tapi yang cerewet itu mendominasi."
Esme tertegun. Teringat lagi olehnya beragam kasak-kusuk di beberapa sudut ruangan dan galian lubang tak beraturan yang tersebar sembarangan di pekarangan.
Ini tidak buruk, batinnya berdoa sungguh-sungguh. Semoga mereka lucu-lucu.
"Katakan padaku," Esme menatap si kembar bergantian, "berapa jumlah mereka?"
Dore mengangkat bahu, sedangkan Remi cengar-cengir tanpa suara.
Alih-alih langsung menjawab pertanyaan, gadis kecil itu malah berdiri tegap di depan sang tamu dengan penuh semangat dan percaya diri. Antusiasmenya tumpah ruah sampai-sampai Esme mulai merasa ketularan.
Setelah memantapkan posisi kaki, Remi menarik napas dalam-dalam, membawa jarinya mendekati mulut, lalu sebuah siulan melengking di udara.
Awalnya hening sesaat, kemudian kasak-kusuk itu terdengar.
Dari berbagai sudut ruangan—di balik sofa-sofa kecil, tumpukan bantal dan selimut, lemari buku, penghangat ruangan, dan bahkan dari tumpukan kotak kayu yang entah apa isinya—muncul banyak puncak kepala anak-anak. Mereka diam di tempat, asyik mengintip dan bertanya-tanya siapa yang dibawa oleh kedua kakak mereka.
Remi mendengkus puas, lalu berbalik menghadap Esme. "Sudah selesai menghitungnya, Kak?" tanyanya jenaka.
"Tiga belas ...," gumam Esme takjub. Mata birunya diam-diam bergerak melirik ke arah si kembar yang berdiri mengawalnya. "Lima belas."
Tawa Remi meledak begitu bersitatap dengan sorot kagum dan ngeri yang terpantul amat jelas di mata Esme. Dore tampaknya memang tidak seekspresif Remi, alhasil anak itu hanya mengulas senyum dua makna: bangga atau mengejek.
"Ini belum semua. Masih ada yang di atas. Mereka masih terlalu kecil untuk tidur sendiri, jadi Momma fokus menjaga mereka," ucap Remi, kembali membeberkan informasi.
Puas diam membatu, kekehan Esme akhirnya lolos dari mulut. Pemandangan yang terhampar di depannya entah kenapa terasa lucu.
Sulit membayangkan ada berapa banyak jumlah sesi adu mulut dengan saudara sebanyak ini dalam satu rumah. Jangankan berlima belas—atau mungkin lebih—Esme dan Peter yang hanya berdua saja sudah mampu membuat gempar tetangga apartemennya.
Tidak heran. Esme bersedekap, masih tersenyum-senyum sendiri. Itulah kenapa rumah besar ini jauh dari keramaian pasar dan jauh dari rumah penduduk yang lain.
Hanya dengan membayangkan dia memiliki tetangga yang beranak banyak saja rasanya sudah mengerikan. Lebih-lebih lagi saat fajar mulai menyingsing menyambut hari baru—kokok ayam barangkali kalah dengan suara gaduh lima belas anak.
Saat itu, lagi-lagi Dore menatap Esme dengan lekat.
"Sedikit terkejut, sepertinya?" Anak itu bertanya—dan Esme bersumpah, semakin lama gelagatnya semakin mirip Ruviane.
"Ah, tidak juga." Esme menarik-narik lengan bajunya ke atas lalu berkacak pinggang, menolak lemah di depan Dore karena anak itu sepertinya terverifikasi titisan Ruviane. Sekali lagi Esme tersenyum penuh semangat. Siap untuk menghadapi pertempuran. "Aku siap. Bawa aku ke hadapan mereka."[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top