[Sin 8]
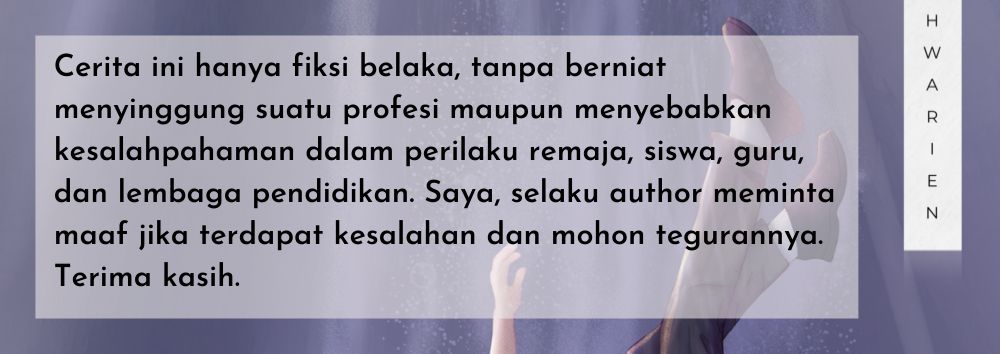

Lelaki yang menatap lantai masih mengentak-entakkan kaki, menunggu sosok yang dapat menjawab seluruh pertanyaannya. Sesekali ia berjalan mondar-mandir, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, lalu menggebraknya tanpa alasan. Telepon dari rekan rahasia--dan istimewa--membuatnya berpikir negatif, meski itu pada anaknya sendiri. Pram tetaplah sama, menomorsatukan segala hal sebelum Doni.
Sebelumnya, Fauzan, kepala sekolah SMA Kemuning mengirim pesan singkat yang ia respons lewat panggilan. Berbicara secara langsung akan lebih rapi dibanding membincangkannya dalam deretan tulisan.
"Maksudnya bagaimana, Pak?" tanyanya tanpa salam.
"Tadi siang saya melihat Doni ngobrol sama Ari. Sebentar sebenarnya, Pak, tapi Pak Pram bisa mengonfirmasi ini ke anaknya nanti."
"Ari? Mau apa lagi anak itu?" Pram refleks menendang kaki meja di sampingnya.
"Dia sedang magang di sini, Pak. Saya pikir nggak ada masalah, selama anak-anak bisa diajak kompromi."
Pram mengusap rambutnya lalu mengangguk. "Baiklah. Nanti saya tanyakan."
Panggilan itu tak berjalan lama. Pram tak pernah berbasa-basi dengan orang yang juga menuntunnya ke kursi kementerian nanti. Selama urusannya selesai dan masalah mereka--kali ini ia juga terlibat--tertutup dengan baik, semua akan baik-baik saja.
Ia pun kembali duduk, meredakan gemetar pada tangan dan kakinya. Kemudian ia menopang dagu dan mencoba mencari jawaban sendiri. Sayang, pemikiran Doni terlalu abu-abu untuk diselami. Tak jarang ia juga harus mengambil alih keputusan lelaki itu. Bahkan, saat Doni ingin meluruskan semuanya, Pram terpaksa ikut campur.
Bunyi suara mobil yang familier sontak mengaburkan lamunan. Pram lekas keluar ruang kerjanya dan berjalan ke ruang tamu. Ia lantas duduk, menyilang kaki dan bersedekap. Tatapannya tertuju ke ambang pintu, memperhatikan anaknya yang menyeret tas asal-asalan.
Doni menelan ludah. Tidak biasanya sang ayah menunggu pulangnya seperti ini. Ia mencoba tak acuh dan (berniat) langsung naik ke lantai dua. Namun, panggilan Pram menghentikan langkahnya. Ia pun menoleh dan menunduk sekilas, sebelum menghampiri ayahnya yang kini menegapkan tubuh.
"Ada yang mau kamu jelaskan ke Papa?"
Pram memancing, tetapi Doni tak lekas mengangkat wajah. Ia pun beranjak dan menekan sang anak untuk duduk. Doni hanya terdiam dan bertanya-tanya dalam hati. Ingin meminta penjelasan pun buat apa, ayahnya lebih ingin mendengarkan penjelasannya--yang ia sendiri belum tahu tentang apa.
"Maksud Papa apa?"
Doni kembali mengingat apa saja yang ia lakukan hari ini. Seketika memorinya berhenti saat sang kepala sekolah mendapatinya tengah berbicara dengan Ari. Sontak ia menatap ayahnya dan menggeleng berulang kali. Tidak, tidak seperti yang dipikirkan, batinnya terkunci. Ia belum berani untuk membuka suara.
"Kamu dekat dengan Ari?"
"Nggak, Pa. Nggak sama sekali. Buat apa Doni dekat dengan dia?"
"Terus, apa yang kalian bicarakan tadi siang?"
Doni menggigit bibir. Matanya mulai bergerak menghindari tatapan Pram. Namun, ia masih memaksakan diri agar terlihat baik, untuk sekarang.
"Dia nanya masalah adiknya dan Doni nggak bilang apa-apa, seperti yang Papa mau."
Pram menautkan alisnya. Sorot yang kian tajam perlahan menggetarkan lelaki di depannya. Akan tetapi, detik berikutnya ia memalingkan wajah dan menjauh dari putranya. Masih bersedekap, ia bersandar pada sofa dan mendengkus. Doni pun menelan ludah, lagi.
"Bagus, kamu boleh ke kamar. Mandi, terus belajar."
"Iya, Pa."
Doni berbalik, meninggalkan ayahnya yang masih bergeming, seolah memikirkan kebohongan yang coba ia tutupi. Meski goyah, langkahnya tampak yakin, menaiki anak tangga tanpa getar sedikit pun. Makin jauh ia dari sang ayah, makin lega pula degup jantungnya. Berkali-kali ia menghela napas setelah keluar tanpa luka.
Lain dengan Pram yang mengerutkan kening. Batinnya masih gusar, belum puas dengan pernyataan Doni. Ia pun mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Dengan cepat ia mencari sebuah nama dalam kontak, lalu menelponnya. Tak membutuhkan waktu lama, panggilan itu dijawab empunya.
"Besok bisa bicara sebentar?"
Pram beranjak dan mengambil secarik kertas dan bolpoin. Ia mencatat alamat yang disebutkan dengan baik, tanpa terlewati. Senyum tipis pun muncul setelah sebuah salam menutup perbincangan mereka.
🍃
Hunian yang tak seberapa besar terasa sunyi. Salah satu penghuninya memang telah tiada, tetapi dua lainnya yang ikut pergi tanpa pamit juga mengambil peran. Ari mengembuskan napas panjang saat tak mendapati siapa pun di dalam rumah, tanpa catatan apa pun di pintu kulkas. Ia lantas duduk di kursi dapur, menatap tudung saji yang menutupi makan malamnya.
Lelaki itu lekas beranjak, berniat membersihkan diri sebelum makan dan istirahat. Namun, kamar sebelah yang sedikit terbuka memanggilnya untuk masuk. Semula, Ari hanya ingin menutup pintu, tetapi saat melihat komputer ibunya, ia terpanggil lalu mendekat.
"Bu, Ari pinjam, ya," ucapnya pada angin, mengingat tidak ada siapa pun di sana.
Ari kemudian duduk dan menyalakan komputer. Yes, serunya lirih ketika ibunya tak memakai password untuk menjaga keamanan data. Aneh, memang, tetapi Ari tak mau tahu. Jelasnya, kini ia bisa berselancar dengan lancar.
Ia segera menuju fitur search dan mengetikkan kata asing yang sedari kemarin mengganggu pikiran. Ari tidak peduli dengan alasan yang bisa saja tak masuk akal dan mengecewakan usahanya. Ia sudah bertekad. Sekecil apa pun penemuannya, ia akan menyelidiki tanpa cela. Barangkali, hal itu dapat ia harapkan.
Notable
Klik. Ari menautkan kedua tangan, memejamkan mata dan merapal doa. Perlahan, ia mengintip dengan mata yang menyipit. Belum ada apa-apa, batinnya. Ia kembali menutup mata, sebelum akhirnya membukanya untuk terakhir kali. Benar saja, ibunya tahu-menahu masalah ini.
Satu folder berisi puluhan fail bernama sama dan disertai angka memenuhi layar. Ia langsung membuka salah satunya. Namun, bukannya paham, yang Ari lihat hanya nama-nama murid yang tidak ia hafal. Lantas, ia menjelajah ke angka yang ia tahu.
Tahun angkatannya. Kelasnya.
"Lah, gue nggak ada."
Ari makin mengernyit. Kesal, ia mengacak rambutnya tak karuan. Namun, ia tidak menyerah. Untuk kali kedua, ia membaca layar di depannya lekat-lekat. Barangkali, ada sesuatu yang bisa dipahami otaknya.
"Ri?"
Suara dari depan membuat Ari terperanjat dan jatuh dari kursi. Ia mengaduh, mengusap pantat yang mendarat tanpa alas. Ia segera berdiri dan mengusapnya perlahan, sebelum keluar ruangan dan menyambut ibunya. Nahas, wanita itu sudah terlebih dulu muncul di depannya.
"Kamu ngapain di sini?"
Mampus, Ari mengumpat dalam hati. Setelah ini, ia akan memohon maaf karena telah berkata kasar pada ibunya. Sejenak ia lupa dengan komputer Ani, bahkan ia belum sempat mematikannya. Ari benar-benar terjebak dalam masalah yang ia ciptakan sendiri.
"Minjem komputer Ibu, laptop Ari layarnya bergaris. Butuh servis."
Bodohnya, sekarang ia harus meminta maaf karena berbohong. Ari mendengkus dan mencoba menyunggingkan senyum.
"Ooh, ya udah. Selesai itu langsung ke dapur, ya. Kita makan bareng."
"O-oke, Bu."
Tanpa menaruh curiga, Ani menepuk pundak sang putra dan meninggalkan ruang kerjanya. Seketika rasa bersalah Ari meningkat berkali-kali lipat. Seharusnya, ia tidak perlu menutupi apa pun. Benar, ia harus jujur bahwa ia menemukan data yang sama--dengan milih Ihsan di BK sekolah--di komputer ibunya. Ia pun menghela napas dan kembali ke depan meja, menyalin fail yang belum ia pahami ke dalam USB.
"Lo harus berguna buat hidup Rey."

DAY 10
13 Januari 2022
1107 Kata


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top