[Sin 3]
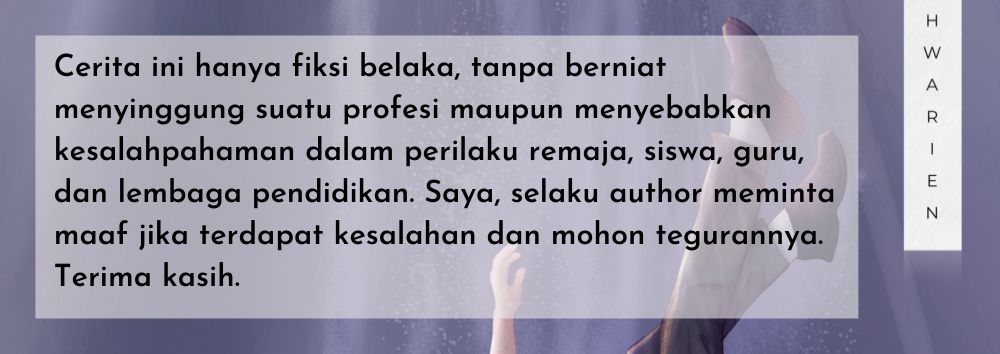

Kalau bukan berkat denting sendok dan garpu, ruang makan malam ini--dan malam-malam lainnya--tidak akan bernyawa. Tiga orang dewasa yang mengelilingi meja hanya menatap makanannya, tanpa berniat menyelingi momen itu dengan berbasa-basi. Sesekali Ari melirik ayah dan ibunya, lalu kembali mendengkus. Kehangatan yang pernah ia rasakan dulu ikut lenyap bersama kematian Rey. Entah bagaimana caranya, Ari masih berusaha menemukan jalan pulang. Dunianya perlu dikembalikan seperti semula.
Kecanggungan itu berlangsung cukup lama hingga piring menyisakan separuh porsi. Perayaan yang harusnya diiringi kebahagiaan nyatanya tak semegah yang dikira. Ani perlahan mengusap punggung tangan putranya, membuat Ari mendongak dan tersenyum tipis. Mereka pun saling pandang, seolah memiliki dunia sendiri tanpa kehadiran Galis.
"Gimana magangnya?" tanya Ani lembut.
Ari memandangi ayahnya. Meski tampak tak acuh, Galis ikut menyimak percakapan tersebut. Ia tidak tertarik, memang, tetapi izin yang diberikannya pada Ari bukan tanpa alasan. Orang tua mana yang sudi melihat anaknya kembali menginjak tempat laknat itu? Galis tidak bodoh, hanya sedang memberi kesempatan.
"Nggak gimana-gimana, kok, Bu. Masih gitu-gitu aja. Kelas yang Ari pegang juga belum ganti," Lelaki berkulit kuning langsat itu memucat dan menelan ludah, "masih di kelas Rey."
Ani tak tahu-menahu soal keberanian Ari malam ini. Jelasnya, ia cukup gelagapan saat sang putra tiba-tiba menyebut nama yang terbilang 'haram' di sini. Ia makin tak berkutik saat Galis menghentikan makannya, lalu membawa piring ke dapur. Ingin kakinya menyusul, tetapi sorot mata Ari ketika melihat kepergian ayahnya jauh lebih penting.
Sejak hari itu, Galis terasa jauh. Dulu, Ari masih memakluminya karena ia juga terluka. Entah lebih besar atau kecil, ia tidak peduli. Rasa yang mereka miliki harusnya sama. Namun, jarak yang hadir di antata mereka makin membentang seiring berjalannya waktu. Bahkan, kian menjadi-jadi saat Ari mengajukan proposal magang di SMA-nya.
"Ibu lega kalau kamu nggak kenapa-napa. Nggak kesulitan atau apa gitu. Pak Ihsan tadi mengirim pesan, katanya kamu disambut baik di sana."
"Iya, syukurlah. Lagian, apa yang mau mereka lakukan ke Ari? Gini-gini, Ari sempat jadi aset mereka, kan?"
Ani terdiam sejenak lalu tersenyum dan mengangguk. "Ibu cuma pengin kamu berjaga-jaga. Siapa tahu nanti--"
"Bu," Ari memotong dengan nada yang memelas, "Ari nggak akan berakhir seperti Rey. Ibu nggak perlu khawatir."
"Mustahil meminta seorang ibu untuk berhenti khawatir dengan anaknya. Kamu tahu itu, Ri."
"Oke, oke. Ari minta maaf, tapi bisa, kan, kalau kita sekarang makan layaknya keluarga normal? Yang nggak harus mikirin dampak masa lalu ke masa sekarang kayak gimana?"
Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Ani. Ia justru makin menunduk setelah menghabiskan segelas air putih miliknya. Sorot berkaca-kaca yang mencoba disembunyikan membuat Ari menjadi pendosa besar sekarang. Lelaki itu refleks mengacak rambut sebelum akhirnya meraih tangan ibunya.
"Ari udah ketemu Rama," ucapnya berusaha mengalihkan pembicaraan.
"Iya?" Perlahan Ani mengangkat wajahnya. "Gimana kabarnya?"
"Baik, kok. Kita tukeran nomor WhatsApp, tapi sampai sekarang chat Ari belum dibales. Telpon juga nggak diangkat."
Ani menghela napas. "Dia baik aja udah cukup. Ibu merasa anak itu punya semacam trauma saat bertengkar dengan adikmu dulu, dan entah apa yang dia rasakan setelah tahu adikmu memilih mengakhiri hidup seperti itu. Kata rekan Ibu di BK, waktu itu Rama hampir seminggu nggak masuk sekolah."
Sejujurnya, ini bukan kali pertama Ari mendengar kisah Rama, tetapi ia tetap diam, membiarkan ibunya meluapkan apa pun isi kepalanya. Kalau tidak salah ingat, Ari bolak-balik sampai tiga kali ke rumah lelaki itu. Hanya untuk menyapa dan menanyakan kebenaran yang tertulis di diari Rey. Misal Rama lebih berbaik hati lagi, ia tak keberatan jika diberi alasan di balik kebohongannya tempo lalu. Sayang, baik Rama maupun orang tuanya, tidak ada yang menerima kedatangan Ari.
"Andai Ibu masih mengajar, Ibu pengin ngobrol berdua dengannya karena hanya dengan itulah Ibu punya wewenang."
"Mulai, deh. Ari nggak suka kalau Ibu berandai-andai begitu."
"Yang Ibu bisa cuma itu. Nggak bakal terjadi juga."
Ari bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju tempat duduk Ani. Ia memeluk dari belakang dan meletakkan dagunya di atas bahu ibunya. Wanita itu lantas membelai rambut putranya dengan lembut dan tanpa sadar turut menyandarkan kepalanya pada sang anak.
"Ibu jangan pernah merasa gagal, ya. Entah sebagai guru Rama atau ibu Ari dan Rey. Semua masih bisa diperbaiki."
Air mata yang sejak tadi berusaha dibendung pun jatuh. Ani tak berniat untuk kembali bersedih akan nasib ini. Namun, erat dekapan dan hangat suara Ari membuatnya seolah mendapat ketenangan untuk menumpahkan segalanya. Wanita itu berbalik lalu merentangkan tangan, memeluk Ari yang sibuk mengelus punggungnya.
"Makasih, ya."
🍃
Jarum jam hampir menunjuk angka sepuluh. Sosok yang menyeret ransel lalu melemparnya ke atas sofa lekas berjalan menuju dapur. Asisten rumah tangga yang sudah hafal dengan tabiat anak majikannya segera menyiapkan makan malam. Ruang makan yang cukup besar itu tak pernah terisi penuh. Mau terlambat atau tepat waktu sekalipun, Doni akan tetap sendirian.
"Mau sama apa, Mas?"
"Saya bisa ambil sendiri. Mbok ke belakang aja. Terima kasih."
"Baik."
Dingin. Intonasi Doni dan aura rumah ini tak jauh berbeda. Megah, memang, tetapi lelaki berumur tujuh belas tahun itu selalu merasakan kekosongan. Di sela makan malamnya, yang bisa ia lihat hanya bayangan ayahnya di ruang kerja, tepatnya di sisi kanan anak tangga--cukup jauh dari ruang makan. Ia bisa melihatnya jika duduk di paling ujung, seperti sekarang.
Pram, ayahnya tak pernah mempermasalahkan jam pulang Doni. Hanya sekali, ketika dulu ia membuat onar di lantai empat SMA Kemuning. Persoalan yang bisa selesai dalam sekejap--itu yang ia tahu. Meski sempat diawasi berminggu-minggu, kini ia bisa bebas berlalu-lalang lagi.
Aksi makannya terhenti saat suara kenop pintu terdengar. Doni mencoba melirik, mengecek apakah ayahnya meninggalkan ruangan dan benar saja. Lelaki berkemeja itu juga berjalan ke arahnya, membuat Doni tunduk tak berkutik. Ia hanya menelan ludah dan menunggu.
"Baru pulang, dari mana?"
"Nge-game sama anak-anak."
"Gimana sekolahmu?" tanya Pram sambil membenahi jas tebalnya.
Doni tak segera menjawab. Kelas dua belas baru dimulai dan yang ia lakukan hanya belajar dan belajar. Latihan soal tambahan ini dan itu di kelas membuatnya hampir meletup sampai tanding game di warnet klubnya pun menjadi pelarian. Doni tahu, ayahnya tak akan menyukai fakta itu.
"Papa nggak masalah kalau kamu mabar sampai malam, asal belajarnya jangan lupa. Ingat, kamu harus lulus dengan nilai bagus, meski non akademikmu jauh di atas rata-rata teman-temanmu yang lain."
Lelaki yang kini memainkan nasinya itu menggigit bibir. Sudah ratusan kali ia mendengar nasihat yang sama. Pram terus-menerus menekankan hal itu di setiap percakapan mereka.
"Kalau bukan karena sokongan Papa, lombamu kemarin nggak bakal diadakan. Kamu nggak bakal bisa main dan nggak bakal jadi juara juga. Artinya, sampai sekarang pun sebenarnya belum ada yang bisa dibanggakan dari kamu."
Dengan santai Pram mengatakan itu. Ia bahkan mengambil alih minuman putranya yang masih utuh dan menenggaknya hingga tandas. Ayah tunggal yang sibuk di kementerian itu pun mendekat dan menepuk pundak sang anak dengan pelan.
"Papa pernah bilang, kan, kamu nggak boleh bikin malu nama Papa? Tahun ini, anak Papa harus masuk Petra lagi. Ngerti, Don?"
Sang empunya nama masih bergeming. Ia mendengar, tetapi tak mengerti. Ia tidak akan pernah mau mencoba memahami pemikiran ayahnya. Pemikiran yang memaksanya untuk masuk ke universitas yang tidak ia inginkan, di jurusan yang tak pernah ia pertimbangkan pula. Doni berusaha menggeleng sekuat mungkin, tetapi raut wajah Pram yang berada tepat di sampingnya membuat nyali yang terkumpul langsung tersungkur.
"Kamu ngerti, kan?" ulang Pram.
Lelaki itu meremas pundak Doni hingga merintih. Sakit yang tiba-tiba datang dan menyebar ke sekujur tubuh itu membuatnya menggeliat. Sayang, sang ayah tak segera melepaskan cengkeramannya. Ingin Doni menghindar atau sekadar menampik tangan Pram, tetapi ia belum ingin dipecut.
"I-iya, Pa. Doni ngerti."
"Baguslah. Kalau gitu, Papa pergi dulu. Ada urusan mendadak."
Napas yang terasa mencekik kini bisa diembus tanpa halangan. Setelah bayangan Pram hilang dari pandangan, Doni lekas menggebrak meja dan melempar piringnya ke sembarang arah. Ia berteriak, melampiaskan amarah yang sedari tadi ditahan. Para ART yang mendengar pun mendekat, mencoba menenangkan lelaki itu.
Namun, bukan Doni kalau ia berhenti begitu saja. Ia masih mengacak-acak makanan di depannya sebelum menendangi meja dan kursi. Lelaki itu bahkan tak merasa bersalah saat salah satu mbok-nya jatuh menghantam dinginnya lantai. Hanya satu yang ia pikirkan sekarang, lari dari tempat ini.
Doni segera berlari menaiki tangga, meninggalkan kerusuhan yang ia perbuat. Ia pun masuk kamar dan mengunci pintu. Kemudian bergegas ke kamar mandi dan menyalakan air hingga suaranya memenuhi ruangan.
"Bego! Tolol! Kenapa lo harus muncul di hidup gue? Kenapa lo harus mati di samping gue? Kenapa gue harus jadi alasan kematian lo?"
Teriakan dari dalam harusnya bisa mengundang perhatian siapa pun. Sayangnya, tidak ada yang mengetuk pintu Doni malam ini. Tidak ada yang berusaha menenangkannya. Tidak ada juga yang menanyakan perasaannya. Lelaki itu menghabiskan waktu hingga kulitnya berkeriput--terlalu lama terkena air.
Ia baru keluar saat ponsel yang ada di dalam tas terus berdering. Sepertinya, salah satu ART telah mengantar ransel hitam kebanggaannya itu ke kamar. Doni pun meraih handuk di kapstok dan mengeringkan tubuh. Ia juga mengganti pakaian sebelum mengangkat panggilan.
"Nomor siapa?" gumamnya saat nomor tak dikenal tertera pada layar. "Halo?"
"Doni?"
Nggak mungkin
Secepat kilat lelaki itu menutup telepon. Matanya terbelalak dan napasnya sontak terengah-engah, seperti tengah dikejar sesuatu. Ia mencengkeram handuk dan ponselnya bersamaan, menatap kosong ke bawah dan menebak-nebak. Firasat bisa saja salah, tetapi hal ini jauh lebih nyata dari dugaannya.
Saat itu pula ia tahu, hati-hati dalam berlari pun, ia akan terjatuh.

DAY 3
6 Januari 2022
1561 Kata


Yeay, tiga bab pertama done 🥳
Semoga suka, yaaa.
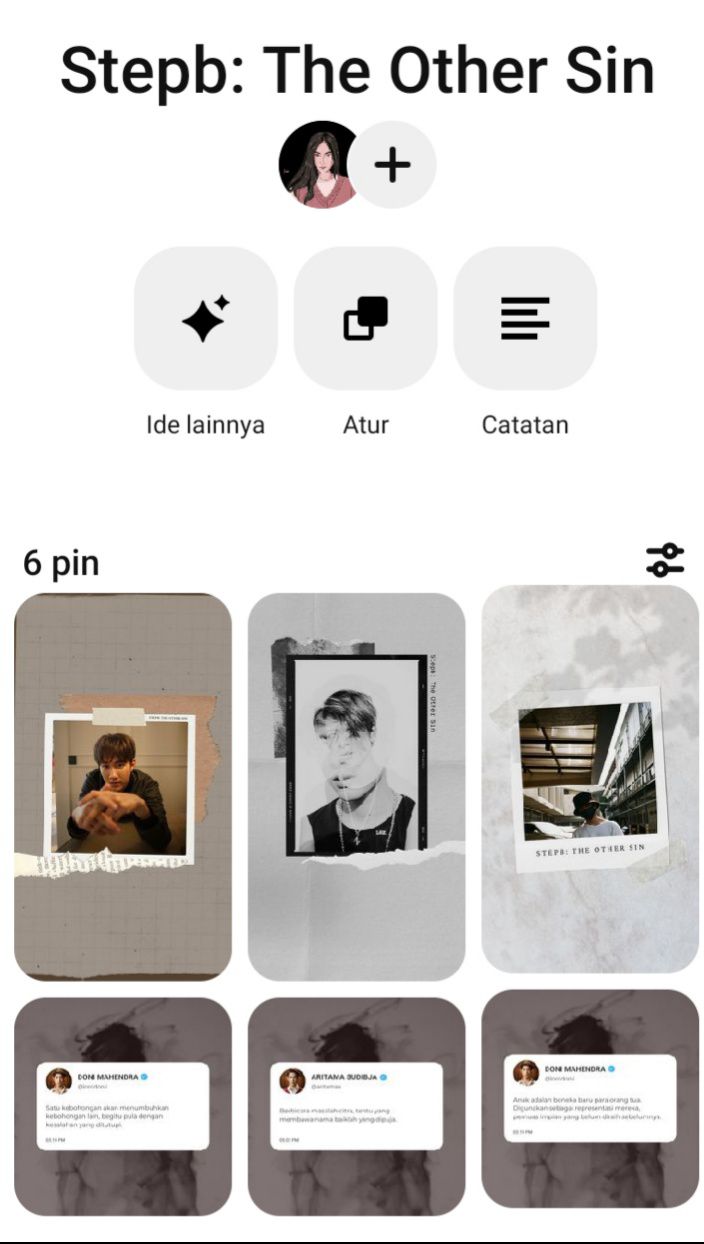
Quotes dan Wallpaper Stepb: The Other Sin juga bisa diunduh di pinterest, ya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top