[Sin 21]
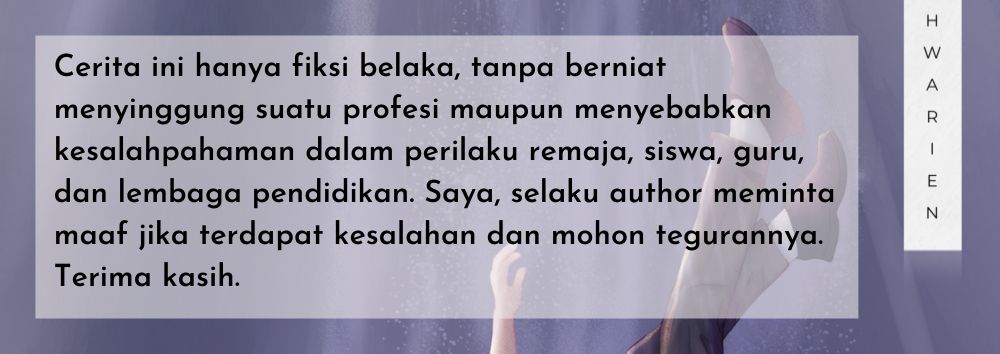

Dunia memang tidak adil, kata Ari. Ia peduli jika setelah ini Tuhan akan melaknatnya. Namun, ia tidak dapat menahan kekesalan yang sejak tadi tersirat di kerutan keningnya. Setelah kejadian di ruang guru, ia diberhentikan dari magangnya, bahkan pihak universitas mencabut beasiswa yang seharusnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang ia buat. Kini, yang ia lakukan hanya termangu di depan layar TV, menunggu hasil penyelidikan pertama pada Fauzan. Lambat, memang, butuh lebih dari seminggu untuk mencapai titik ini.
"Assalamualaikum."
Lelaki yang telah menanggalkan perban di kepalanya itu menoleh, menatap sang ibu yang berjalan gontai menghampirinya. Ia pun bangkit dan mengambil alih tas kecil Ani, menuntunnya untuk duduk, lalu menawarkan segelas air putih yang belum diminum sama sekali. Karena kegaduhan yang disebabkan sebelumnya saat bersaksi, Ari dilarang datang ke pengadilan dan wanita yang berambut lepek plus berkeringat itu harus susah payah menggantikannya--sesuai yang Ari mau.
"Gimana hasilnya, Bu?"
Ari lekas mengecilkan volume TV yang belum menayangkan berita apa pun. Ia menggenggam tangan ibunya yang gemetaran. Seketika kelembapan yang dingin dan kelam pun ia rasakan, seolah harap yang sempat digenggam sebelumnya telah runtuh dan musnah. Ani lantas menghela napas dan mengangkat dagu. Ia menatap putranya yang menautkan alis dan berkedip konstan. Antusias dalam binar matanya membuat wanita itu gusar dan kembali deg-degan.
"Pak Fauzan nggak ditetapkan sebagai tersangka."
"Kok bisa?"
"Masalah notable nggak dianggap sebagai penyelewengan. Mereka hanya meminta SMA Kemuning untuk meniadakan program itu dan ke depannya nggak boleh ada perlakuan spesial lagi."
"Terus? Kolusi yang selama ini terjadi, gimana? Nggak dihukum sama sekali?"
Ani menggeleng. "SMA Kemuning dijatuhi denda yang Ibu sendiri kurang tau nominalnya. Pak Fauzan nggak bisa serta-merta dihukum karena notable udah ada jauh sebelum dia menjabat, semacam tradisi baik yang disalahartikan. Jadi, sementara penyidik membebaskan beliau dan akan menyelidiki ini lebih jauh."
"Masalah Rama?"
"Diselesaikan secara kekeluargaan."
"Hah? Tapi--"
"Kamu bisa tanyakan itu ke Rama, Ri," Ani mengusap rambut putranya lembut, "tapi pelan-pelan, ya. Dia juga sama sakitnya kayak kamu."
"Kenapa gini, Bu? Kalau Pak Fauzan dibebasin gitu aja, kita nggak bisa lihat benangnya."
"Ibu tau, tapi melawan orang yang berkuasa emang nggak mudah, Ri."
Ck, Ari berdecak. Ia mengusap wajah dan mengacak rambutnya. Pembalasan yang ia tata baik-baik ternyata belum cukup untuk melawan kedudukan yang tak tergapai. Ia kemudian mengambil ponsel yang tergeletak di meja dan membuka media sosial tempatnya mengadu. Sontak nama kepala sekolah SMA Kemuning memenuhi laman pencarian dan berbagai portal berita. Sayangnya, tidak banyak ujaran negatif yang tertera di sana. Hanya sekilas tentang pernyataan penyidik dan kekuatan pasal yang menuntut. Warganet yang mengikuti kasus ini pun turut bertanya-tanya akan hasil yang tak mengherankan.
Ani beranjak setelah mendapati Galis berjalan ke dapur. Ia meninggalkan putranya yang masih sibuk membaca unggahan beberapa akun yang kebingungan. Ada yang menyayangkan pembebasan tanpa pengusutan lebih dalam, ada pula yang menganggap kaum kontra melebih-lebihkan keadaan. Sungguh tidak sedikit yang menilai notable sebagai cara unik Kemuning untuk bersinar, tanpa menilai keanehan yang telah disebutkan.
"Tolol," komen Ari kasar. Rautnya memerah saat mengatakannya.
Lelaki itu mengakhiri penjelajahannya. Ia segera mencari nomor telepon Rama dan menghubunginya. Perlu tiga kali sampai akhirnya panggilan tersebut diterima. Ari refleks berdiri dan berkacak pinggang.
"Halo--"
"Maaf, Bang. Maaf."
Ari mendengkus. "Lo pasti punya alasan. Mau cerita?"
"Gue nggak bisa nolak permintaan Ibu, Bang."
"Ibu lo yang minta damai?"
"Iya," jawab Rama dengan suara bergetar. "Ibu diminta ibunya Luis buat nggak memperpanjang masalah ini."
Di luar dugaan, ternyata Fauzan juga memakai tangan orang lain untuk membungkam mulut seseorang. Ari menggeleng, tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Ia refleks berjalan mondar-mandir. Tanpa sadar pula, ia menggigiti kuku tangannya berkali-kali.
"Sekarang lo di mana?" tanyanya sebab tak menemukan jalan.
"Di sekolah, Bang. Di perpustakaan."
"Pak Fauzan di situ?"
"Iya, sama Pak Pram juga."
Alis Ari sontak bertaut, lagi. "Hah? Ngapain dia di situ?"
"Ng-nggak tau. Bang, lo bisa ke sini, nggak? Gue takut mereka nyariin."
"Oke, gue ke sana sekarang. Lo tenang aja, ya. Ada gue."
Rama tak menanggapi lagi. Ia mematikan telepon secara sepihak. Ari lekas mengambil dompet dan megafon organisasinya di kamar, lalu pergi tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan catatan di ruang tamu sebelum berangkat ke SMA Kemuning menggunakan ojek daring.
Sesampainya di sana, ia sempat kucing-kucingan dengan satpam. Ia takut mereka diberi perintah untuk menghalanginya masuk. Syukurlah, gerbang Kemuning aman dilewati dan dia bisa leluasa menuju ruang guru. Tak seperti yang ia duga, suasana di dalam sana dipenuhi kehangatan. Mungkin, ucapan selamatlah yang menggema dari satu ke satu lainnya. Ia makin geram hingga mencengkeram celana saat melihat senyum Pram yang amat lebar.
Ari berjalan ke tengah lapangan. Ia menyalakan megafonnya lalu mengedarkan pandangan. Bunyi nyaring yang mengganggu telinga sontak menyita perhatian. Siswa yang duduk-duduk di teras lekas menatapnya, juga yang berdiri di sekitar lorong ikut memperhatikan. Namun, yang paling penting adalah para elitis di ruang guru. Ia tersenyum riang saat mendapati mereka mengintip melalui jendela.
"Fauzan-Pram bangsat! Keluar lo!"
Suara lantang tersebut tak bermaksud memanggil Doni dan kedua kawannya. Namun, tiga siswa kelas dua belas itu refleks keluar kelas dan menyimak di depan pintu. Mereka tak berani mendekat, tak berani menyela, tak berani mengusik pula. Terutama Doni, yang menggigit bibir saat mengetahui sang ayah masih berada di sekolahnya.
"Bisa-bisanya, ya, lo bebas gitu aja setelah apa yang terjadi sampai detik ini. Gue udah main seadil mungkin, tapi lo malah mainan duit lagi? Cemen lo, tai!"
Pram masih terdiam di tempatnya. Ia tidak mau menanggapi seekor lalat yang berusaha hinggap dan mengotori segala hal. Biarkan orang merasa Ari frustrasi dan gila. Ia hanya akan mengamati dan membiarkan Fauzan mengarahkan satpamnya untuk mengusir lelaki itu dari Kemuning.
Ari belum menyerah, meski di belakangnya ada dua pria berbadan tambun berlari ke arahnya. Ia menoleh ke kelas Doni dan memperhatikan lelaki itu lekat-lekat.
"Lihat! Lihat, Pram! Anak lo nggak bisa ngapa-ngapain. Mau merasa bersalah juga gimana, lo yang bikin dia kayak gitu! Lo yang nyuruh dia ngasih pelajaran dan bully adik gue. Bahkan saat adik gue kecelakaan di lantai empat dan meninggal, lo nyuruh anak lo buat tutup mulut. Lo nyuruh dia buat nyogok anak kelasnya biar seolah adik gue bunuh diri, persis yang lo lakuin di kasusnya Rama kemarin. Lo peralat anak lo sendiri biar jejak keluarga dan karier lo bersih! Biadab! Lepas!"
Empat tangan kekar telah memegangi Ari dan menyeretnya keluar dari lapangan. Mau sekuat apa pun tenaganya, Ari tidak bisa melawan. Sekeras-kerasnya ia memberontak, dua satpam di kiri-kanannya tak henti membalas. Justru ia makin ditarik dan dicengkeram kuat-kuat.
Lelaki itu pun pasrah. Ia lantas memandangi sekitarnya yang sibuk merekam kejadian. Dalam hati, ia bersyukur dan berdoa, berharap tangan-tangan tersebut tergerak untuk mengunggah ke media sosial. Meski kemungkinannya begitu kecil, Ari tetap berharap.
"Sudah, Pak. Lepasin teman saya. Saya yang akan membawanya pergi."
"Toni?" Ari menoleh.
"Ayo, ikut gue."
Satpam yang tak asing dengan mahasiswa magang itu lekas membiarkan Toni mengambil alih lengan Ari. Ia segera keluar sekolah dan membawa kawannya menjauh dari gerbang. Doni yang melihat hal itu lekas mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan, sedangkan Sam dan Luis masih bergeming di tempatnya.
Toni membawa Ari belok ke gang kecil yang mengarah ke gerbang belakang sekolah. Mereka terus berjalan hingga menembus kantin. Lelaki berkemeja batik itu lekas mendudukkan Ari dan berdiri di depannya dengan tangan bersedekap.
"Ngapain lo bawa gue ke sini?"
Alih-alih menjawab, Toni justru membuka ponselnya yang terus bergetar. Ari pun mendongak dan mendengkus, mengamati sosok kawannya dari ujung ke ujung. Sontak ia berdecak dan menyeringai, menertawakan diri sendiri yang mau-mau saja dibawa ke sini.
"Harusnya gue yang nanya, lo ngapain teriak-teriak kayak tadi? Itu bukan lo banget, Ri. Lo bukan orang yang ngomong sembarangan tanpa bukti."
"Menurut lo, apa yang bisa gue lakuin kalau kebenaran nggak bisa ditegakkan hanya karena bukti?"
"Ri--"
"Lo ngomong kayak gini karena nggak mau nerima kenyataan masalah ayah angkat lo, kan?"
"M-maksudnya?"
"Udahlah, Ton. Nggak usah mengelak atau main rahasia-rahasiaan lagi."
"Sejak kapan lo tau?"
"Mahasiswa baru."
"Jadi selama ini lo jadiin gue temen karena--"
"Gue berteman sama lo tulus, tapi iya, gue sempet manfaatin keadaan. Gue pernah ngambil nomor Doni dari hape lo. Itu aja. Nggak lebih."
"Sialan!" Toni meraih kerah Ari dan mengangkat tubuh lelaki itu.
Ari tidak berniat berpura-pura. Namun, kawannya memang tidak terbuka. Ia sangat berhati-hati dengan Toni, bahkan tak membicarakan rencananya sama sekali serta menghindari tanggapan yang selalu diminta, semata-mata agar tidak dipermainkan. Ia biarkan lelaki di depannya itu meluapkan emosi yang sebenarnya tak seberapa besar dibanding dengannya.
"Gue jujur karena gue temen lo, Ton. Apa yang terjadi ke adik gue emang ulah bokap dan adik lo. Gue bisa buktiin itu kalau lo mau."
Bukti yang cuma bisa kita nikmati sendiri, tanpa bisa dijadikan alat untuk menyerang orang lain.
Toni terdiam. Ia tidak menjawab, tidak juga bertanya. Matanya berkaca-kaca, seakan mengatakan ketidakpercayaan. Namun, di satu sisi, ia merasa semua ini berjalan di jalur yang sesungguhnya. Geram, hawa panas yang mengungkung tubuh kian menjadi-jadi. Ia pun melampiaskannya dengan mendorong Ari dan memukulinya tanpa henti.
Rahang kiri. Rahang kanan. Sudut bibir yang terkena tamparan berkali-kali pun terkoyak. Ari memejamkan mata, menikmati sensasi perih di sekitar wajahnya. Ia jadikan itu sebagai pengalih rasa yang menyesakkan di dada. Berharap, setelah ini kawannya dapat tersadar dan mau mengikuti permainannya.
"Kak! Cukup!"
Teriakan dari kejauhan mengusik aksi Toni. Ari lekas membuka mata dan mendapati Doni sudah di dekatnya. Lelaki berseragam putih abu-abu itu tengah menarik kakaknya agar menjauh darinya. Kemudian mereka berlari, meninggalkan Ari yang terbatuk dan mencoba bangkit.
Di sela napasnya yang kembang-kempis, Ari menatap bayangan yang perlahan menghilang dari kantin. Ia lantas menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Selagi ingat, ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi Rama, lalu keluar dari sana.
"Besok kita main di tempat terakhir."

DAY 23
26 Januari 2022
1622 Kata
Besok tamat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top