[Sin 20]
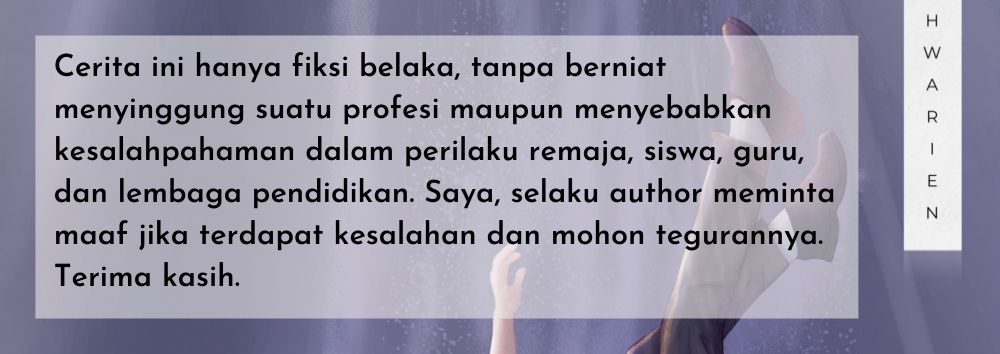

Sosok yang memijat pelipis tampak terkantuk-kantuk. Tubuhnya sesekali terhuyung ke samping, meski sudah berkali-kali menampar diri. Ia pun mendengkus, kembali meminum segelas air yang tersedia di atas nakas, lalu menuangkannya sedikit di telapak tangan. Ia memercikkan air tersebut ke wajah, berharap sensasi dingin yang berpadu dengan suhu AC dapat menyadarkan.
"Nyalakan saja TV-nya, Bu."
Ani mengangguk. Sebenarnya, ia tidak mau mengganggu tidur Ari. Ia takut membuat gaduh dan mengusik lelap putranya. Namun, berhubung kedua mata lelaki itu sudah lama tertutup rapat, ia lantas berubah pikiran. Barangkali, hal ini dapat memancingnya untuk bangun dan mendengarkan cerita yang menyenangkan.
Masih teringat betapa terkejutnya ia tadi saat dihubungi Ihsan. Ari, putranya yang sangat jarang demam sekalipun, dilarikan ke rumah sakit terdekat--dari SMA Kemuning--karena terluka cukup parah di kepalanya. Mereka tak menjelaskan detail lebih lanjut, ia pun tidak menanyakan apa-apa. Jangankan bertanya, berpikir jernih saja Ani tidak mampu. Belenggu khawatir lebih dulu menguasainya.
Syukurlah, dokter mengatakan gegar otak Ari tergolong ringan. Meski begitu, sementara waktu ia harus dirawat dulu untuk melihat perkembangannya. Ani hanya menurut dan memesan kamar VIP agar putranya bisa leluasa sendiri. Ia juga sempat menolak tawaran sekolah--yang diberikan lewat Ihsan--perihal biaya perawatan Ari. Buat apa? Ia tidak ingin gegabah dan membiarkan usaha putranya sia-sia hanya karena budi.
"Ganti ke saluran berita, Bu." Galis yang duduk menyilangkan kaki lekas bersandar pada pinggiran sofa.
"Beritanya mulai naik, ya?"
"Iya, di mana-mana bahas itu. Dari tadi banyak pesan masuk nanyain bener atau enggak, sama nanya keadaan Ari."
Ani tersenyum tipis lalu membelai rambut putranya lembut. "Ke Ibu juga, tapi udah berhenti. Hapenya mati."
Galis mengembuskan napas panjang. Ia tidak tahu harus merespons apa lagi. Pandangannya terlalu fokus dengan profil kepala sekolah SMA Kemuning yang dipaparkan media, mulai dari latar belakang pendidikannya sampai berbagai prestasi yang pernah diraih. Bahkan, posisi kementerian yang digadang-gadang akan diisi beliau juga terpampang di layar. Kabar buruk yang harusnya diiringi dengan kejanggalan-kejanggalan yang bisa saja ditemukan, justru ditimbun dengan hal-hal yang dapat memakluminya.
Kenapa … negeri ini lebih suka menyanjung seorang kriminal dengan kedok menyayangkan pencapaiannya?
"Ari?"
Ani beralih menatap putranya saat merasakan gerakan tangan kiri Ari yang ada di dekatnya. Sontak Galis mengurangi volume TV lalu mendekat, menarik kursi di samping kasur dan duduk secepat kilat. Meski sempat mengernyit dan merintih, lelaki yang terbaring lemas itu perlahan membuka mata.
"Syukurlah, akhirnya kamu bangun juga."
"Aku panggil dokter dulu, ya."
Hanya anggukan yang Ani berikan. Ia masih sibuk mengusap pipi dingin Ari. Mata yang sedari tadi berkaca-kaca lantas menitikkan air yang sudah susah payah dibendung. Perlahan, Ari mengangkat tangannya dan menghapus tangis sang ibu. Ia tersenyum, seolah mengatakan kalau semuanya masih baik-baik saja.
"Kamu ingat kenapa bisa di sini?"
Ari bergeming, menatap langit-langit kamar sembari menerawang memorinya. Hal yang ia ingat hanya saat Fauzan memukul kepalanya menggunakan vas bunga. Lebih dari itu, Ari tidak tahu-menahu. Ani segera mengangguk dan mengucap syukur. Putranya telah melakukan yang terbaik.
Layar TV yang masih menayangkan berita Fauzan langsung menyita perhatian Ari. Ia bahkan memiringkan kepalanya agar dapat melihat secara jelas karena sisi kiri ditutupi ibunya. Lekat, ia mengamati sambil mendengarkan dengan cermat. Tipis, ia menyunggingkan senyum lalu menghela napas lega. Tidak terlalu buruk, pikirnya.
Ani ingin berbicara. Namun, sebelum itu terjadi, dokter terlebih dulu datang dan memeriksa Ari. Setelah selesai--tidak memakan waktu lama, barulah ia, Ari dan Galis yang tersisa di ruang rawat. Ia pun membantu sang anak duduk bersandar untuk memudahkan komunikasi.
"Jadi gimana, Bu?" tanya Ari tanpa basa-basi. Galis telah mematikan televisi.
"Pak Fauzan dipanggil kejaksaan atas semua yang terjadi, khususnya masalah notable dan bullying pada Rama. Kalau kamu mau, Ibu dan Ayah akan melaporkan apa yang sudah dia lakukan hari ini, Ri."
Ari menatap kedua orang tuanya lalu menggeleng. "Itu aja cukup, kok, Bu. Ari nggak apa-apa."
"Pihak pengadilan juga udah tau kalau kamu pelaku penyebaran info di media sosial, Ri."
"Terus, apa tanggapan mereka, Yah?"
"Ayah juga belum tau. Yang jelas, kamu akan dijadikan salah satu saksi di kasus ini. Juga nggak menutup kemungkinan nanti sekolah menuntutmu atas pencemaran nama baik."
"Ari nggak masalah, toh hukumannya nggak seberapa."
"Itu nggak baik untuk kariermu, Ri." Galis tak henti menasihati.
"Aku nggak peduli, Yah."
Ani mengusap wajah. Kemudian ia menepuk-nepuk lengan Ari dan memijatnya pelan. Ia juga menatap sang suami dan menggeleng kecil, berusaha memberi isyarat untuk tak melanjutkan percakapan--lebih mirip dengan perdebatan. Galis pun diam, lalu beranjak kembali ke sofa.
"Yang penting sekarang kamu istirahat dulu. Masalah Pak Fauzan, biar pihak berwenang yang menyelesaikannya."
"Tapi Ari nggak tenang, Bu. Bisa aja mereka main kotor lagi di belakang. Tanpa sepengetahuan Ari, Ibu, Ayah, semuanya."
"Emangnya kalau keluar dari rumah sakit sekarang, kamu bisa mencegah itu?"
Ari menelan ludah. Tentu tidak, mau dari mana ia mendapat akses demikian? Namun, setidaknya ia jauh lebih nyaman jika bisa bergerak cepat saat mendapati hal yang tidak beres. Ia hanya takut terlambat bertindak kalau harus menunggu tetesan infus yang menggantung di atasnya habis tak bersisa.
"Udah, Ri. Sekarang yang penting kamu sehat dulu. Kalau nggak prima, kamu nggak bisa totalitas melawan mereka. Percayalah, jika ternyata sesuatu benar-benar terjadi, pasti bisa diperbaiki. Belum ketinggalan jauh, kan? Setiap dosa memiliki jejak, Nak."
Tak bisa berkata-kata lagi, Ari pun mengangguk. Ia biarkan sang ibu mendekapnya erat, menepuk-nepuk punggungnya, tak lupa mengusap lembut pula. Sejenak, ia merasa damai dan terlindungi. Namun, detik berikutnya ia ingat bahwa hari ini tidak berlaku selamanya.
"Permisi?"
Bunyi ketukan pintu sontak membuat penghuni kamar saling pandang. Ketiganya mengangkat bahu, tidak memiliki pandangan siapa pengunjung yang tak lekas masuk. Ani pun beranjak dan membukakan pintu. Seketika ia terbelalak melihat sosok yang sudah lama tak ia temui.
"Rama?"
"Sore, Bu. Saya mau menjenguk Bang Ari. Boleh?"
Ani lekas mencubit pahanya agar cepat sadar. "Bo-boleh, boleh. Ayo masuk."
Galis segera membenahi duduknya dan mempersilakan Rama untuk duduk di sampingnya. Lelaki yang belum menanggalkan seragamnya itu sesekali menunduk. Kedua tangannya tampak bertaut dan kakinya terus-menerus mengentak-entak lantai. Paham akan situasi, Galis memilih keluar ruangan dan menuju kantin rumah sakit, sedangkan Ani mengambil air minum dan meletakkannya di meja--tepat di depan Rama.
"Gimana kabar lo, Bang?" tanya Rama sambil menatap Ari, menghindari tatapan Ani.
"Tinggal puyeng doang. Kok lo tau gue di sini?"
"Tadi Pak Ihsan cerita. Gue minta nomor ruangan ini dari beliau juga."
"Lo ke sini sendiri?"
Rama mengangguk. "Naik angkot."
"Nanti pulangnya sama Bu Ani aja, ya? Gimana? Kebetulan mau ngambil baju ganti, nih, buat Bang Ari."
Lembut suara Ani justru membuat Rama panas-dingin. Ia menggigit bibir, sedikit menggeser duduknya agar menjauh. Ia tidak risi. Ia juga tidak jijik. Ia hanya merasa tidak pantas mendapat perlakuan semanis itu. Rama lekas menggeleng, menolak tawaran yang sebenarnya bisa menghemat uang bulanannya.
"Kenapa? Rumah kita searah, kan? Atau Rama masih takut sama Ibu?"
Takut? Rama segera menyanggahnya, "Enggak, Bu."
"Kalau begitu, nggak apa-apa, kan? Bentar lagi gelap, lho."
Ari masih menyimak. Senyumnya mengembang saat melihat ibunya berbicara dengan Rama. Kekeringan yang dua tahun melanda hatinya seolah mereda perlahan-lahan, berganti semilir angin yang menenangkan relung.
Rama tak kuasa mengangkat dagu. Ia ingin jujur, tetapi binar mata Ani terlalu tulus untuk seseorang sepertinya. Ia pun menoleh, menatap Ari yang tersenyum dan mengangguk, seakan mencoba meyakinkannya. Lelaki itu lantas mengalihkan pandangan dan meraih tangan kanan Ani, menciumnya cukup lama hingga tanpa sadar, air matanya menetes di atasnya.
"Rama?" panggil Ani lembut. Ia spontan mengusap punggung siswanya yang sedang setengah membungkuk itu.
"Maaf, ya, Bu. Atas semua yang sudah terjadi pada Rey dan juga Bang Ari."
Ani menyentuh pundak Rama dan mendorong pelan lelaki itu agar bisa bangkit. Ia lantas menatap lekat dengan senyum yang tak luntur sedikit pun. Kemudian ia mengacak rambut Rama gemas dan mencubit pipinya yang lumayan tembam.
"Kamu ngapain minta maaf? Udah, ya. Ibu nggak mau ada drama gini-gini lagi. Yang salah tetap orang tua, kamu hanya berusaha melakukan yang terbaik versi seorang anak. Oke?"
"Tapi--"
"Nggak perlu ada 'tapi'. Itu cuma membawamu ke penyesalan yang nggak berarti. Intinya, sekarang kamu udah berubah. Itu saja cukup."
"Makasih, ya, Bu."
Rama pun memeluk Ani yang dibalas erat oleh wanita itu. Ia menumpahkan seluruh tangis yang tertahan sejak dua tahun lalu. Mulai saat menuduh Rey, melihatnya jatuh dari lantai empat, tidak mengunjungi sahabatnya sendiri di pemakaman, dan bungkam atas permasalahan yang ia ketahui. Ia keluarkan seluruh perasaan bersalah dan hina itu sejadi-jadinya.
Dalam senyumnya, Ani menyimpan sejuta rasa lain yang lebih sakit. Ia menelan ludah dan menghela napas, mencoba baik-baik saja karena di antara mereka harus ada yang lebih tegar untuk menyeimbangkan keadaan. Ia tak henti mengusap punggung Rama sampai lelaki itu berhenti terisak. Ari yang melihat hal itu turut berkaca-kaca sampai kepalanya kembali pening. Ia lekas berbaring miring agar tetap bisa menyaksikan pemandangan langka di depannya.
"Udah, ya, nangisnya. Nanti kalau ibumu tau, ntar dikiranya Ibu ngapa-ngapain kamu." Ani melepas pelukannya.
Rama tertawa kecil. "Ibu kerja, biasanya baru pulang tengah malam."
"Jadi, gimana tawaran Ibu? Mau, ya?"
"Iya, Bu. Terima kasih."
"Gimana kalau nanti kita sekalian mampir ke makam Rey? Kamu kangen, kan, sama dia?"
"Bo-boleh?"
Ani mengangguk semangat. "Boleh, dong."
Tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan perasaan Rama saat ini. Untuk kali pertama setelah sekian lamanya, ia tersenyum manis dan bertahan cukup lama. Lagi, ia memeluk Ani dan berulang kali mengucap terima kasih. Kini, salah satu bebannya telah diangkat dan terdapat kelegaan di hatinya.

DAY 22
25 Januari 2022
1560 Kata
Kurang dikit lagi 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top