[Bersalah]
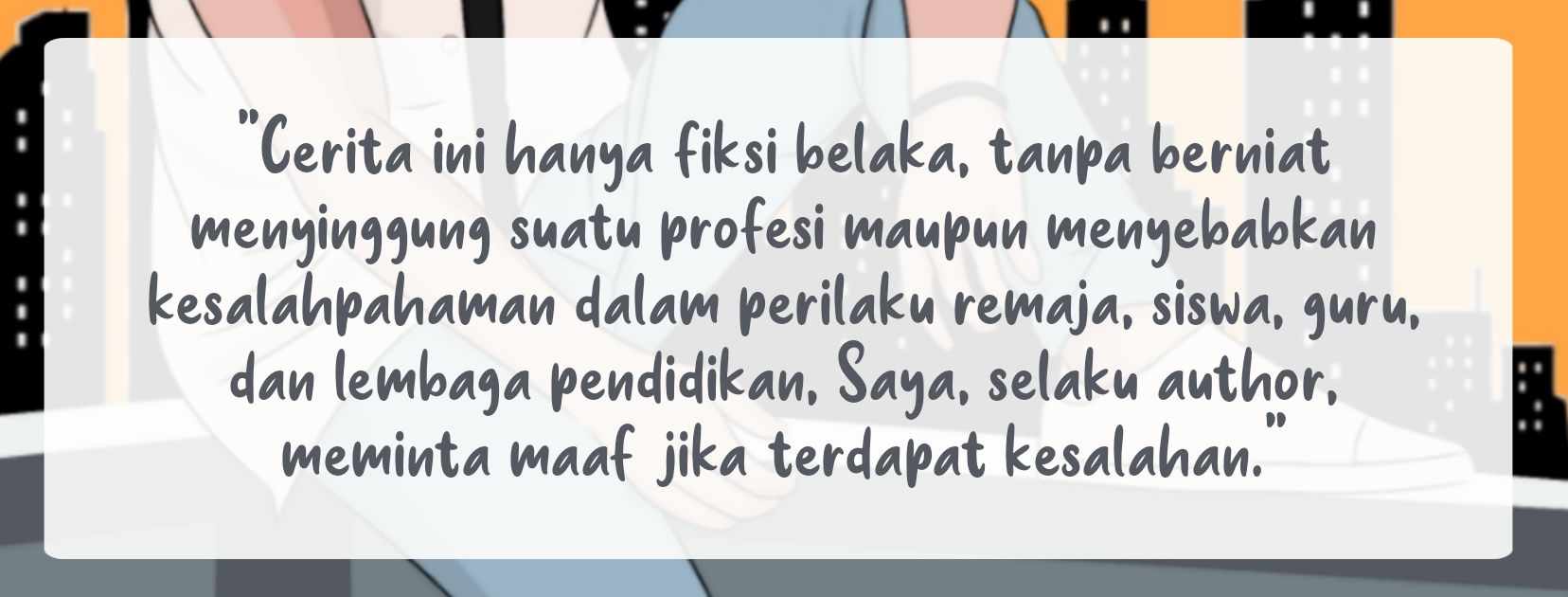
Perih. Doni mencengkeram pahanya seraya menunduk. Serpihan USB yang telah hancur berkeping-keping di atas meja mencuri fokus dan mengalihkan rasa sakit. Mulai dari sudut bibir, rahang, tulang pipi, hingga pelipisnya memerah berkat tamparan dan pukulan dari sosok yang berkacak pinggang.
Hunian tiga lantai itu tampak sepi. Hanya seruan bertubi-tubi dari sang ayahlah yang mengisi ruangan. Lelaki berjas hitam yang mengerutkan kening itu tak henti mengentakkan kaki. Nyali Doni menciut saat tatapan tajam yang tertuju padanya kian menguat. Ia pun menunduk, tak sanggup 'tuk mengangkat dagu.
"Saya mau Bapak mengatasi masalah ini tanpa menambah masalah lain."
Doni memalingkan wajah. Ponsel pemberian mendiang ibunya turut remuk sebab kemarahan ayahnya. Kalau saja ia tidak jujur, mungkin senja sore ini masih terang dan menenangkan. Namun, ia tak dapat pungkiri, tidak ada seorang pun yang bisa memusnahkan kejadian ini.
Kaki dan tangannya masih dingin dan bergetar. Bahkan rona wajahnya pun belum pulih. Tetap pucat, meski setitik darah muncul dari luka-luka kecil yang menyebar.
Anak itu mengembuskan napas panjang. Bayangan tangan Rey yang mengulur padanya masih memenuhi memori. Datar rautnya kala memejamkan mata dan membentur tanah tak segera enyah. Sekuat apa pun Doni mengusap wajah sampai rambut, rumput yang berubah warna itu tetap bertahan di pikirannya.
"Mati karena bunuh diri lebih baik daripada kasus bullying."
Doni menoleh, tak terima akan label yang disematkan sang ayah. Ia bukanlah perundung. Ia hanya memberi pelajaran yang setimpal. Lagi pula, ia melakukannya karena para tetua itu tak mungkin tinggal diam atas ulah Rey. Seharusnya, mereka bangga, bukan?
Namun, sebesar apa pun gertakan yang ia sajikan, Rey tetap melaju. Doni tentu menerimanya dengan senang hati. Ia benar-benar tidak menyangka permainan ini akan berujung kekalahan nan seri. Ini semua di luar kehendaknya. Alhasil, tak ada sedikit tawa pun yang mengakhiri.
"Masalah media itu gampang. Kasih pengalihan isu sedikit juga beres. Bapak gak perlu khawatir soal citra sekolah, humas saya akan membantu pemulihan branding. Semua biaya saya yang tanggung."
Doni menyandarkan kepalanya pada sofa, memandang lampu gantung ruang tengah dengan tatapan kosong. Lama-lama ia muak mendengarkan negosiasi yang sudah berjalan setengah jam tersebut. Ia bosan, entah telah berapa kali kepala sekolahnya berbincang dengan sang ayah.
"Ingat, Pak, Bapak masih bisa menyelamatkan masa depan anak-anak lain dengan mengiakan saran ini. Atau Bapak mau, kasus kecurangan dan …."
Kalimat itu menggantung, membuat Doni menegapkan tubuh dan mencengkeram bantalan sofa. Ia menelan ludah dan menggigit bibir, menatap lelaki yang mengangguk pelan seraya tersenyum. Perlahan, debar jantungnya kian melambat dan teratur.
Laki-laki yang mematikan panggilan itu melempar ponselnya ke samping Doni. Ia mendekat dan menarik kerah sang anak yang tak lagi rapi.
Ia pun berbisik sebelum kembali menampar Doni dan meninggalkan rumah, "Hubungi teman-temanmu. Masalah sudah selesai. Hapus kejadian hari ini dari hidup kalian. Kalau sampai kamu masih berbuat ulah, Ayah akan mengirimmu ke panti."
¶
Tubuh nan ringan itu jatuh, terbawa angin sekian detik sebelum menyapa bumi. Ia membentur bebatuan serta tanah hingga menimbulkan suara hantaman yang cukup keras. Sekujur badan yang baik-baik saja lantas hancur dari dalam. Hanya bentuk kaki yang tak lagi normal dan genangan darah dari pelipis yang terlihat jelas. Anak yang telungkup itu memejam erat dan tak berkutik lagi.
Kedua mata Galis tak berhenti menitikkan air. Bayang-bayang tak menentu yang berkeliaran di otaknya terus mencabik, mengoyak, dan memporak-porandakan hati. Hanya dengan memikirkannya saja ia tak sanggup.
Dunia Galis runtuh seruntuh-runtuhnya. Tangis pun tak dapat melampiaskan sakit nan menghujam. Erat genggaman Ani yang duduk di samping juga tak dapat mengurangi apa-apa.
Mata laki-laki itu tak berhenti menatap lampu ruang operasi yang berwarna merah. Kakinya terus bergetar. Ia tak tenang, benar-benar tak tenang.
Sepulang kerja tadi sore, bahkan melepas penat pun belum sempat, Galis dikejutkan oleh panggilan telepon dari sekolah. Mereka memberi kabar bahwa Rey tengah di rumah sakit dengan kondisi kritis, sebab diduga jatuh dari lantai empat.
Bak tersambar petir, Galis beserta istri sontak luruh tak berdaya. Mereka--dan juga Ari--segera menemui pihak sekolah yang menghubungi. Hingga kini, hanya wali kelas Rey yang menetap dan berdiri cemas bersamanya. Meski hanya menghitung detik yang berlalu, dukungan itu tetaplah perlu. Mau tidak mau, Galis ingin mendengar penjelasan akan hal ini.
"Selamat malam, Pak, Bu."
Laki-laki yang mengusap wajah itu lekas mendongak dan berdiri. Dua sosok berseragam yang menenteng plastik hitam besar itu mendekat seraya membungkuk. Galis pun membalas dengan anggukan.
"Kami dari pihak kepolisian yang baru saja dari TKP."
"Anak saya masih di dalam. Saya belum ingin mendengar penjelasan apa pun. Bapak bisa kembali lagi nanti."
"Mas …."
Ani mengusap punggung suaminya. Ia mencoba menenangkan dan mengikuti proses yang berjalan. Senyuman tipis ia bubuhkan sebagai permohonan maaf.
"Ini … tas sekolah anak Bapak dan Ibu yang ditinggal di lantai empat. Baik di atap maupun di bawah, kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada surat peninggalan juga. Namun, dugaan sementara, korban melakukan bunuh di--"
"Apa maksud Anda?"
Amarah Galis tersulut. Ia lantas meraih kerah polisi tersebut dan menatapnya tajam. Sontak Ani, Ari, serta petugas yang lain mencegah lelaki tersebut dengan menarik tangannya, sedangkan wali kelas Rey hanya terpaku dan menutup mulut. Namun, emosi Galis sungguh berapi-api sampai ketiga tenaga itu tidak dapat menghentikannya.
"Bapak tenang dulu, itu masih dugaan kami."
"Jadi maksud Anda anak saya mengakhiri hidupnya sendiri? Begitu?"
"Tenang, Mas, sabar."
Galis terus menggeleng, menolak alasan tersebut secara mentah-mentah. Sejauh apa pun hubungannya dengan Rey, darah yang mengalir di tubuh anak itu tetaplah darinya. Ia tetaplah dekat sedekat nadi. Batinnya tentu menjerit, tak mau mengiakan untaian kalimat konyol itu.
Ia tidak mudah melepaskan cengkeramannya sampai lampu operasi berubah hijau. Galis segera meraih tangan Ani dan mendekati pintu ruangan tersebut. Ari yang melangkah hati-hati juga mengikuti orang tuanya.
Seorang dokter yang menurunkan maskernya menghampiri dengan raut menekuk. Ia membungkuk 45° sebelum mengabarkan hasil usahanya. Melihat hal itu, genggaman Galis semakin menguat dan bergetar.
"Maaf, Pak, pasien tidak dapat kami selamatkan."
Cukup satu kalimat. Hanya satu kalimat. Benar-benar dengan kalimat itu saja Galis terduduk lemas. Pandangannya sungguh kosong juga datar. Air mata yang telah habis ditumpahkan perlahan terisi dan kembali menetes tanpa permisi, membasahi lantai dingin rumah sakit.
Ani yang meluruh di samping Galis hanya bisa menunduk, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk sang suami dengan erat, seakan bila terlepas ia 'kan kembali kehilangan.
Tak ingin memperburuk situasi, dokter dan petugas polisi pun meninggalkan keluarga tersebut. Berbeda dengan wali kelas yang memilih berdiri menjauh kemudian menelepon sekolah untuk memberi kabar.
Ari masih menutup telinga dan menggeleng cepat di tempatnya. Isak tangis Ani membuatnya kian percaya dengan apa yang didengar. Akan tetapi, jauh di dasar lubuk hatinya, ia meminta keajaiban dan kesempatan kedua. Sayang, waktu diciptakan untuk mengalir ke depan.
Anak itu pun memeluk ayah dan ibunya dari belakang. Ia lekas menyembunyikan wajah di balik lelah punggung sang ayah. Sesak, dada Ari bak tertumpuk ribuan perasaan bersalah.
Ketiga orang itu refleks berdiri saat suara brankar mendekati pintu, menampakkan kain putih yang menutupi sekujur tubuh sosok yang terbaring. Galis pun mendekat, meminta petugas medis untuk berhenti sejenak. Ia lantas membuka penutup yang menghalangi wajah Rey.
"Nak …."
Tenang. Raut nan putih dan dingin itu terlihat damai tanpa beban. Galis tak berhenti mengusap wajah sang anak, meski jari-jarinya membeku dan gemetaran.
"Maafin Ayah, maafin Ayah …."
Hanya kata itu yang bisa Galis lantunkan. Sesak yang memenuhi benak membuat lidahnya kelu. Ia tak mampu berkata-kata, anak yang tadi pagi masih tersenyum di meja makan telah menutup mata tanpa mengucap selamat tinggal.
"Kamu istirahat yang tenang, ya."
Kalimat itu mengakhiri pertemuan. Perjalanan Rey sudah berhenti. Anak yang tak segan berdiri di atas panasnya api itu telah berusaha yang terbaik.
Meski kini waktu tak memihak, akan tiba masanya ia berdiri di samping orang yang berjalan di batas yang sama. Tidak ada satu tetes pun yang berakhir sia-sia. Kematian Rey … juga tak akan berakhir tanpa ketukan palu. Karena ia, sungguh tidak pernah bersalah.

Day 20
29 Januari 2021

RIP 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top